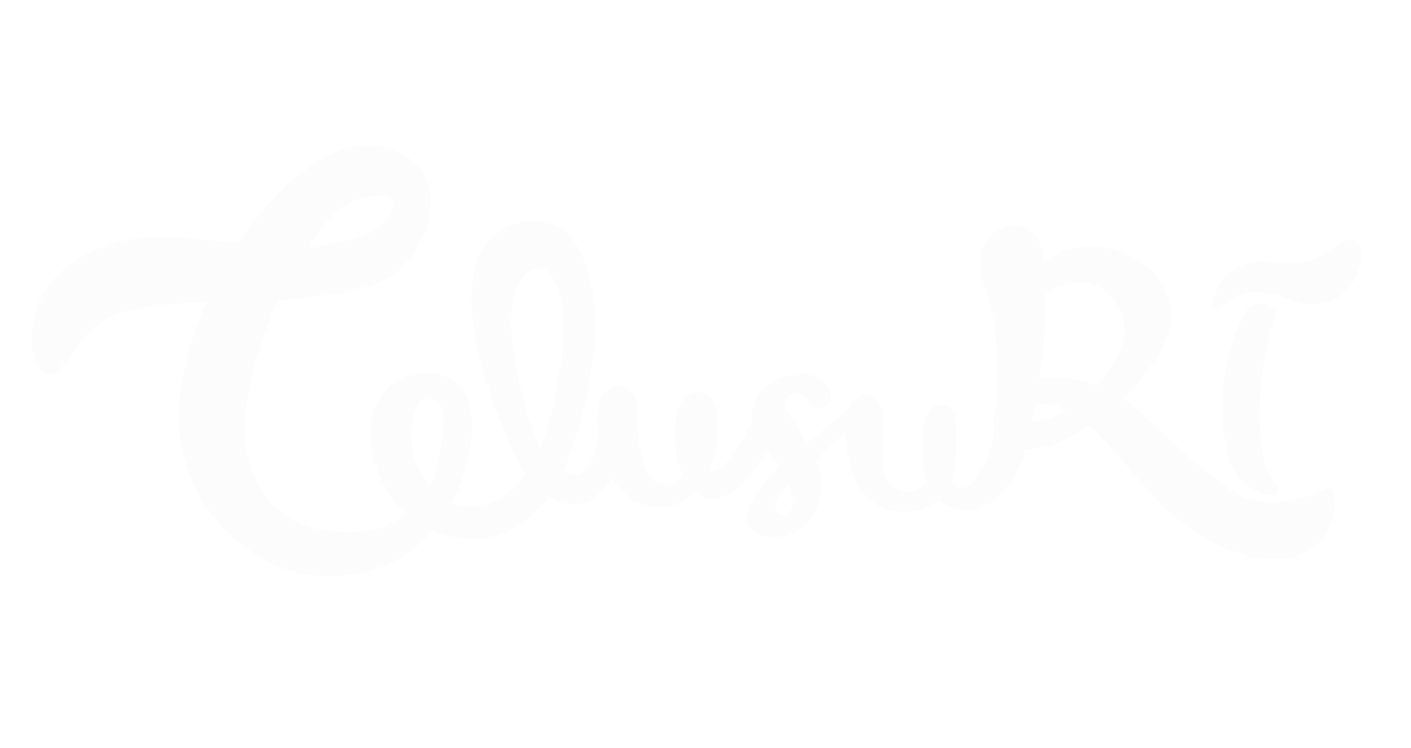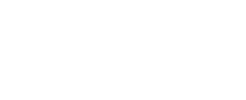Komunitas nelayan di Kampung Konda dan Wamargege terus berjuang demi mendapatkan dua aspek pengakuan: wilayah hutan adat dan pusat penghasil udang banana. Butuh perjalanan panjang dan sinergi multipihak untuk mencapainya.
Teks: Rifqy Faiza Rahman
Foto: Deta Widyananda & Mauren Fitri

“Woi! Ada udang, kah?” seru Piter Meres (38) lantang pada sekelompok pria di atas perahu bermesin tempel Johnson yang melambat. Orang-orang itu adalah nelayan yang baru pulang melaut sejak pagi. Sesaat lagi mereka akan merapat ke dermaga milik Misdam, warga keturunan Bone-Konda yang membuka usaha pengepulan dan rumah timbang udang.
Lokasinya tidak jauh dari tempat kami menyapa mereka, di rumah timbang udang milik Koperasi Fgan Fen Sisi. Koperasi ini dibangun atas inisiatif Yayasan EcoNusa, organisasi nirlaba yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan berkelanjutan berbasis masyarakat dengan fokus wilayah di kawasan Indonesia Timur. Dalam operasionalnya, EcoNusa menggandeng PT Ekosistem Bumi Lestari (KOBUMI) sebagai pembeli utama udang hasil tangkapan nelayan anggota koperasi. KOBUMI adalah perusahaan gabungan dari koperasi-koperasi milik masyarakat adat binaan EcoNusa di Papua dan Maluku dengan konsep bisnis berkelanjutan, untuk meningkatkan daya saing komoditas lokal dan kesejahteraan masyarakat adat.
Bangunan berbahan kayu nani laut dan merbau itu didirikan dengan model rumah panggung di tubir Sungai Kaibus. Terdapat dua bilik kamar—salah satunya gudang penyimpanan alat-alat melaut—dan teras luas terbuka untuk ruang tamu, lengkap dengan dapur kecil serta tiga chest freezer (kulkas pendingin dan pembeku ikan). Kami menginap di “basecamp” tersebut beberapa hari saat liputan ekspedisi Arah Singgah Papua 2024 di Kampung Konda dan Kampung Wamargege.
Dua kampung dengan jumlah populasi 1.500-an penduduk (BPS Sorong Selatan, 2022) tersebut memang bersebelahan. Membentang kurang lebih satu kilometer di pinggir aliran Sungai Kaibus. Jaraknya sekitar 15 km dari Bariat, terletak di ujung jalan penghubung Teminabuan–Konda yang penuh lubang. Untuk ke sini, ada dua opsi. Pertama, naik motor atau mobil dengan estimasi jarak 25 km dan waktu tempuh normal 1 jam dari pusat Kota Teminabuan. Kedua, seperti kata Piter, bisa naik perahu atau speedboat dari Pelabuhan Teminabuan dengan waktu tempuh sedikit lebih cepat.

Jalan kecil yang membentang lurus dari gereja lawas Migdal Eder menjadi garis batas wilayah administrasi kampung. Konda di timur, Wamargege di barat. Rata-rata masyarakat adat yang menghuni kedua kampung tersebut berasal dari subsuku Yaben, bagian dari suku besar Tehit. Sebagian lagi merupakan subsuku Nakna dan Afsya. Selain tetap memanfaatkan kawasan hutan untuk berkebun atau berburu, kebanyakan bekerja sebagai nelayan.
Udang menjadi komoditas laut yang paling diandalkan di sini, terutama udang banana. Melebihi lobster, kepiting bakau, atau ikan-ikan lainnya—baik kelompok demersal (hidup di dasar perairan) maupun pelagis (hidup dekat permukaan air). Udang banana (Penaeus merguiensis) atau banana shrimp adalah nama di pasar internasional. Dikenal juga dengan sebutan udang putih atau udang jerbung. Sala dkk (2021) menyebut lebih dari 50–70 persen hasil tangkapan masyarakat Konda dan Wamargege berupa udang banana. Bahkan mereka masih menjaga tradisi berupa ritual adat pemanggilan udang.
Sore itu (20/8/2024) kami memang menanti-nanti bagaimana bentuk udang banana yang jadi andalan masyarakat setempat itu. Walaupun tidak berharap banyak. Sebab, kami datang ke sini bulan Agustus. Kata Piter, ini bulan-bulan musim ombak dan angin kencang. Penduduk setempat menyebutnya angin selatan. Jarang nelayan yang berani melaut, terutama sampai ke laut lepas. Bulan ini juga bukan merupakan musim puncak udang banana.
Untuk itulah Onesimus Ebar atau akrab disapa Ones (37), koordinator program EcoNusa Sorong Selatan sekaligus ketua koperasi, meliburkan sementara aktivitas ekonomi di Fgan Fen Sisi. Aktivitas timbang udang masih berlangsung terbatas di segelintir pengepul lokal saja, seperti di tempat Misdam. Di sana kami membeli dua kilogram udang untuk dimasak ramai-ramai. Marcelina, ibu satu anak yang tinggal di rumah seberang koperasi, didapuk sebagai juru masak oleh Ones.
Udang Konda ingin lebih dikenal dunia lewat koperasi
Kampung Konda dan Wamargege memiliki salah satu kawasan ekosistem mangrove terbesar di Sorong Selatan. Terbentuk oleh alam selama berabad-abad. Ekosistem ini menjadi bagian dari hutan mangrove di DAS Kaibus, salah satu dari 14 DAS yang menyusun zona Green Belt (sabuk hijau) Sorong Selatan dengan luas tutupan mencapai 76.171 hektare (Proyek SEA USAID, 2018). Seperti halnya di distrik pesisir lain—Saifi, Kokoda, dan Inanwatan—habitat primer di Konda didominasi oleh jenis Rhizophora apiculata. Tegakan pohonnya bisa mencapai 30–40 meter.
Hutan mangrove di sepanjang aliran Sungai Kaibus tersebut menjadi rumah besar bagi berbagai satwa liar, mulai dari kepiting bakau, buaya muara, aneka burung, dan termasuk udang putih atau udang banana—komoditas dominan. Meski demikian, nelayan Konda dan Wamargege umumnya lebih memilih lokasi muara atau laut untuk mencari udang daripada daerah sungai maupun teluk (woronggey). Sebab, potensi hasil tangkapannya lebih besar. Mulut laut selatan itu terlihat cukup jelas dari kampung.
Ada dua periode puncak musim penangkapan udang, yaitu bulan-bulan antara Maret–Mei atau Oktober–Desember. Diperkirakan terdapat ratusan ton udang banana yang bisa dihasilkan saat musim puncak tersebut. Seblum Serio (30), anggota Koperasi Fgan Fen Sisi, mengungkap bahwa dalam satu perahu Johnson 15 PK berisi dua orang nelayan bisa mendapatkan rata-rata 50–100 kilogram tangkapan udang banana per hari. “Biasanya kami pergi melaut itu jam delapan pagi, pulang jam 5 sore,” katanya.
Dalam sekali melaut, untuk mesin Johnson, nelayan membutuhkan 20 liter minyak (bensin) dan seliter oli mesin yang cukup untuk pergi-pulang. Di Konda, harga bensin Rp15.000 per liter dan oli Rp50.000 per liter. Kalau ingin hemat pakai perahu jenis jolor, karena menggunakan solar dengan harga Rp5.000 per liter.
Ketika hasil tangkapan berlimpah, rumah-rumah timbang akan sibuk. Baik yang dikelola masyarakat maupun koperasi. Rata-rata rumah timbang akan menghargai sebesar Rp60.000 per kilogram udang banana. Seblum menambahkan, seorang nelayan minimal harus dapat 10 kilogram ke atas jika ingin mendapatkan pemasukan bersih setidaknya Rp50-100 ribu. Pada dasarnya nelayan berhak memilih dan akan mencari rumah timbang yang bisa membeli harga tinggi. Namun, ada perbedaan pengelolaan yang mendasar di antara keduanya.
Jika memilih menimbang di pengepul lokal seperti Misdam, ada imbal balik yang harus dilakukan nelayan. Nelayan mesti sekalian membeli bahan bakar minyak (BBM) di tempatnya. Misdam, yang selalu dibantu oleh Amir, adiknya, juga menyediakan persewaan jaring untuk nelayan. Maka setiap nelayan menjual udang ke Misdam, ada potongan sekitar Rp100 ribu untuk sewa alat tangkap tersebut.
Itu belum ditambah dengan potongan-potongan lain yang timbul karena adanya utang nelayan kepada Misdam. Begitu pun terjadi di pengepul-pengepul lain. Utang tersebut berupa modal keperluan melaut, seperti BBM, jaring, hingga bekal mencakup gula, kopi, dan rokok. Tak jarang seorang nelayan pulang ke rumah dengan tangan kosong karena hasil tangkapan hari itu belum cukup untuk melunasi utang. Yusup Sianggo (39), sekretaris koperasi, mengkonfirmasi ini.
Selama dua dekade terakhir, meski udang banana sudah menjadi produk unggulan, sebagian nelayan memang masih terkendala untuk mencapai taraf ekonomi yang diharapkan. Mereka pergi melaut demi bisa menutupi utang-utang yang kerap menumpuk karena hasil tangkapan kurang memuaskan. Bisa karena cuaca, keterbatasan alat tangkap, bahkan permainan pengepul di Teminabuan–Sorong atau perusahaan di tingkat atas yang terkadang mempermainkan harga. Kerap terjadi situasi yang “dikondisikan”, seperti tidak ada pembeli karena saking berlimpahnya panen udang. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan tidak terserap secara adil.

Untuk itulah Koperasi Fgan Fen Sisi berusaha hadir membantu masyarakat. Menurut Yusup, keberadaan koperasi untuk membantu nelayan agar dapat kepastian ekonomi dari udang banana maupun tangkapan ikan lainnya. Koperasi melalui KOBUMI akan mencarikan pasar atau pembeli udang banana hasil tangkapan nelayan. Selain membantu menyediakan alat tangkap jaring dan BBM dengan biaya terjangkau, koperasi juga memberlakukan sistem tabungan untuk nelayan. Tujuannya agar nelayan tidak terbebani dengan pengeluaran rutin atau ikatan utang setiap melaut.
“Misalnya, ada nelayan dapat 20 kg udang. Koperasi beli, tapi ada [hasil] 2–3 kg yang disisihkan untuk ditabung. Bendahara akan menyimpan uang dan mencatatnya dalam buku rekening yang dibawa oleh nelayan,” jelas Yusup. Sisa uang penjualan yang tidak ditabung bisa dibawa pulang nelayan. Sementara tabungan di koperasi tersebut, selain untuk simpanan mencukupi kebutuhan keluarga, juga bisa menjadi modal nelayan untuk melaut lagi di hari-hari berikutnya.
Kami melihat satu hal yang menarik perhatian di rumah timbang Misdam. Sebuah kondisi yang lazim berlaku di Konda dan Wamargege. Ternyata, setelah hasil tangkapan nelayan ditimbang dan dibeli, bagian kepala udang dibuang begitu saja. Sebab, sejauh ini, menurut Misdam, permintaan industri pengolahan udang di Kota Sorong tidak terlalu membutuhkan kepala udang. Sisanya disimpan dalam kotak es untuk selanjutnya disetor kepada pengepul di Teminabuan. Umumnya masyarakat belum terlalu mengetahui manfaat dari kepala udang.
Dari Teminabuan, udang-udang tanpa kepala itu akan dibawa ke Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), Jembatan Puri, Kota Sorong. Pabrik-pabrik pengolahan ikan di sana akan memberi lokasi usahanya (Sorong) pada label kemasan. Dari ujung barat Papua itu, udang-udang Sorong Selatan berkelana sampai ke Jawa, mendarat di Surabaya hingga Jakarta. Setibanya di destinasi tujuan, orang-orang Jawa akan lebih mengenalnya sebagai udang Sorong daripada udang Sorong Selatan.
Kenyataan tersebut disayangkan sekaligus diterima sebagai kenyataan oleh Yusup dan nelayan-nelayan di kampung. Ia berharap di masa depan kedua kampung ini bisa berdaulat dalam mengelola hasil tangkapan udang banana di tanah sendiri. Yang jelas, seperti kata Yusup, orang-orang Konda dan Wamargege di Sorong Selatan ingin lebih dikenal sebagai penghasil udang banana daripada Sorong.
Senada dengan Yusup, Ones juga mengungkap peran penting lain dari koperasi. “Pada prinsipnya koperasi akan mendorong bagaimana udang produksi asli Konda ini bisa terkenal di tempat lain. Mungkin di Jakarta, atau daerah Jawa pada umumnya,” jelas suami Sopice Sawor, mantan kepala Distrik Konda itu. “bagaimana kita bisa mempertahankan nama Konda itu sampai di Sorong? Bahkan diekspor ke luar [negeri]?”
Kaldu udang Mama Yulita berharap dukungan pemerintah
Di sisi lain, inisiatif ekonomi berbasis masyarakat datang dari Yulita Sawor (45). Sejak tahun 2022, perempuan Konda tersebut membuat kaldu udang di dapur rumahnya. Priskila Sawor, istri Ones yang juga mantan kepala Distrik Bariat, juga menempati rumah ini.
Ide pembuatan kaldu udang berasal dari keresahan Yulita terhadap banyaknya bagian kepala udang banana yang terbuang begitu saja di rumah timbang. Kecuali untuk konsumsi sendiri, nelayan akan menyimpan utuh seluruh bagian udang untuk dimasak. Maka ketika EcoNusa datang untuk memberi pendampingan pemberdayaan ekonomi lewat Koperasi Fgan Fen Sisi, Yulita menyambut hangat. Bantuan organisasi nonprofit itu membuat Yulita memiliki produk kaldu udang dengan kemasan yang lebih baik. Nama “Saipo” ia pilih sebagai merek usaha yang tercantum dalam label kemasan. “Saipo” dalam bahasa lokal artinya udang.
Dari satu kilogram kepala udang banana segar, Yulita bisa memproduksi 500 gram tepung atau kaldu udang. Biasanya ada dua mama di sekitar rumah yang ikut membantunya, yaitu Dorsea Sawor (70) dan Miriam Serio (55). Namun, itu pun dalam satu hari Yulita hanya mampu mengolah maksimal enam kilogram bahan baku kepala udang.

“Tidak bisa lebih karena [produksinya] memakan waktu lama. Butuh kesabaran dan kita harus istirahat juga,” kata Yulita. Jika suaminya, Abraham, ikut membantu, kapasitas produksinya bertambah empat kilogram lebih banyak.
Jika dimasukkan dalam botol kemasan 100 gram, maka terdapat lima botol dengan harga jual Rp25.000 per botol. Syarat estimasi produksi sebanyak itu hanya satu, bahan baku udang harus segar dan proses pengolahannya dilakukan pada satu hari yang sama. Sebab, Yulita tidak menggunakan pengawet, sehingga Yulita hanya membuat kaldu udang berdasarkan pesanan.
Saat ini, meski sudah mengantongi sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari dinas kesehatan kabupaten, Yulita mengaku masih mengalami sejumlah kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Selain pemasaran yang belum stabil, Yulita menilai dukungan pemerintah untuk industri rumah tangga di kampung pedalaman belum maksimal. Padahal, ia beberapa kali mewakili Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Sorong Selatan ke acara-acara bazar atau pameran di luar kota.
“Selama ini pemerintah tahu saya membuat kaldu, tapi tidak pernah ada perhatian [lebih lanjut] dari mereka untuk kami,” keluh Yulita. Ia berharap bisa mendapat akses permodalan untuk memperbarui dan meningkatkan kapasitas alat-alat produksinya, serta jejaring pemasaran yang menjamin stabilitas pendapatan Yulita dan tim produksi.


Proses pengupasan kepala udang sebagai bahan baku pembuatan kaldu udang di rumah Mama Yulita/Deta Widyananda
Tidak hanya kaldu saja yang Yulita bisa buat, tetapi juga kerupuk udang dan bakso udang. Dua produk olahan ini sudah mampu ia hasilkan sejak sedekade lalu. Meski, lagi-lagi produksinya hanya berdasarkan pesanan karena keterbatasan alat dan tenaga kerja.
Kesulitan lain yang Yulita alami adalah faktor iklim, yang sangat berpengaruh pada pasokan bahan baku. Jika musim angin kencang atau gelombang besar, seperti saat kami datang ke sana, tidak banyak nelayan yang turun melaut. Kalaupun ada yang melaut, tidak banyak udang yang didapat. Akibatnya, hasil tangkapan terbatas. Kalaupun Yulita harus pergi melaut sendiri, itu juga bergantung dengan ketersediaan perahu, bahan bakar, dan risiko keselamatan yang harus ia tanggung.
Namun, di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi, Yulita sejatinya masih belum putus harapan. Ia bermimpi kelak memiliki perusahaan kaldu udang sendiri, meski dalam skala industri rumah tangga. Ia percaya dengan masa depan Saipo, selama ada sinergi dukungan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat Konda-Wamargege itu sendiri dalam menjaga lingkungan habitat udang banana.

Mendesak pengakuan hutan adat
Mesin perahu dimatikan. Hanya terdengar kecipak air sungai yang membentur dinding perahu. Gelombangnya kemudian menerjang akar-akar bakau yang mencuat di atas permukaan air.
Dalam kesunyian hutan mangrove berusia tua itu, dari atas perahu Yohan Meres (70), tokoh adat Kampung Konda, bersenandung dalam bahasa lokal. Lagu yang dinyanyikan ibunya semasa ia kecil. Ia mengenang masa anak-anak saat diajak ibunya berlayar ke laut. Masa-masa saat alam masih asri, bulan bersinar terang, dan laut banyak ikan. Sesekali suaranya tertahan, tangannya menyeka air mata yang diiringi isak. Terbayang keindahan masa lalunya yang bersahaja.
Meski zaman sekarang berbeda, Yohan mengharapkan alam di Konda tetap terjaga seterusnya. Tak terkecuali ribuan hutan mangrove di perairan Sungai Kaibus yang selalu jadi pemandangan sehari-hari masyarakat Konda-Wamargege. Ia bahkan menyebut pohon-pohon bakau itu pun punya hak adat, sebab “mereka” sudah tinggal lama dan menyatu dengan alam di sekitarnya. Hak adat yang tidak hanya berlaku bagi ekosistem di laut saja, tetapi juga di darat.
“Jadi, kalau ada pengusaha-pengusaha yang datang untuk [penebangan] kayu, memang kami masyarakat ini menolak itu,” tegas pria berdarah Nakna itu. Penolakan masyarakat juga berlaku untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun industri ekstraktif lainnya.

Ones pun menguatkan sikap Yohan. Menurutnya, dari lima sistem perhutanan sosial yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Hutan Adat (HA) merupakan skema terbaik dan berkekuatan hukum paling kuat. Terutama di kawasan yang memiliki komunitas adat dan penerapan tanah ulayat seperti Papua. Sebab, hanya masyarakat adat yang lebih paham tentang cara menjaga hutan, sungai, dan lautan yang ada di wilayah mereka.
Begitu pun dengan Konda-Wamargege. Kepastian legalitas surat keputusan (SK) pengakuan hutan adat, yang nantinya dikeluarkan oleh pemerintah, akan menjamin kelangsungan ekosistem sumber daya perairan dua kampung itu. Keputusan Bupati Sorong Selatan pada Juni 2024, yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah hutan adat di Distrik Konda, harus dikawal hingga mendapat kepastian hukum mengikat di tingkat pemerintah pusat.
Jika mengacu pada riset Irwanto dkk dalam Proyek SEA USAID (2018), bisa jadi Distrik Konda jadi benteng terakhir hutan mangrove Sorong Selatan. Sebab, beberapa daerah di Kais, Metamani, Saifi, dan Kokoda telah terjadi penebangan hutan mangrove untuk keperluan akses perkebunan kelapa sawit maupun eksplorasi minyak dan gas. Dampaknya rawan terjadi konflik tenurial antarmarga karena penyempitan lahan adat.

Di satu sisi, harapan Yusup dan Ones agar udang Konda dan Wamargege lebih dikenal luas masih memiliki prospek cerah. Kelestarian ekosistem yang menjadi syarat dasar keberlanjutan hingga kini masih dijaga para nelayan. Kata Ones, jika sedang menangkap ikan, udang, atau kepiting, lalu menemukan ada yang masih bertelur, nelayan akan mengembalikan lagi ke laut. Tujuannya membiarkan satwa bertelur dan tumbuh ideal terlebih dahulu. Bahkan jika ada ikan yang tidak diperlukan lalu terjaring tidak sengaja, selama masih hidup, akan dilepaskan juga. Hal ini dilakukan agar menjaga ketersediaan satwa di laut secara berkelanjutan.
Kondisi itu sejalan dengan temuan menarik dari beberapa penelitian metode penangkapan ikan nelayan-nelayan di Sorong Selatan. Ratna (2019) mengungkapkan, indikasi frekuensi pelanggaran atau penangkapan destruktif kurang dari lima kasus per tahun. Sementara Sala dkk (2021) menyebut bahwa upaya penangkapan ikan oleh nelayan masih cukup jauh di bawah batas jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB).
Maka, selanjutnya melestarikan kemasyhuran udang banana Konda-Wamargege tergantung pada kerja sama warganya. Seperti tersirat dari nama koperasi, “Fgan Fen Sisi” yang bermakna “berjalan sama-sama”, mengindikasikan ajakan untuk sejalan dalam harapan dan kesejahteraan. Melestarikan warisan dan pesan luhur dari leluhur adat.
Dampaknya, masyarakat bisa memanfaatkan hasil alam secukupnya untuk ekonomi dan kebutuhan rumah tangga; tanpa terusik ancaman investasi ekstraktif atau gangguan apa pun. Tidak terkecuali hutan mangrove tua dan kawasan laut yang menjadi ujung Sungai Kaibus itu. Rumah bagi kepiting, ikan, dan udang banana yang harus terus dijaga. (*)
Referensi:
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Proyek Sustainable Ecosystems Advanced (SEA) USAID (2018). Kondisi Laut: Indonesia, Jilid Tiga: Menjelajahi Indonesia bagian Timur. Proyek SEA USAID – Lokasi dan Kegiatan. Jakarta, pp. 206. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XBT6.pdf.
Ratna. (2019). Sustainable Shrimp Fisheries Management at Sorong Selatan of West Papua Using EAFM Tools In Fishing Domain Techniques. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 7(91), July 2019. https://doi.org/10.31227/osf.io/g9tvx.
Sala, R. (2021) Sumber Daya Perikanan Laut Perairan Sorong Selatan: Pemanfaatan dan Pengelolaan Berkelanjutan. Yogyakarta: Deepublish.
Foto sampul:
Tumpukan udang banana hasil tangkapan nelayan Konda dan Wamargege. Udang banana merupakan komoditas laut yang diandalkan masyarakat kedua kampung/Deta Widyananda
Pada Agustus–September 2024, tim TelusuRI mengunjungi Sorong dan Sorong Selatan di Papua Barat Daya, serta Jayapura di Papua, dalam ekspedisi Arah Singgah: Suara-suara dari Timur Indonesia. Laporan perjalanannya dapat Anda ikuti di telusuri.id/arahsinggah.
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.