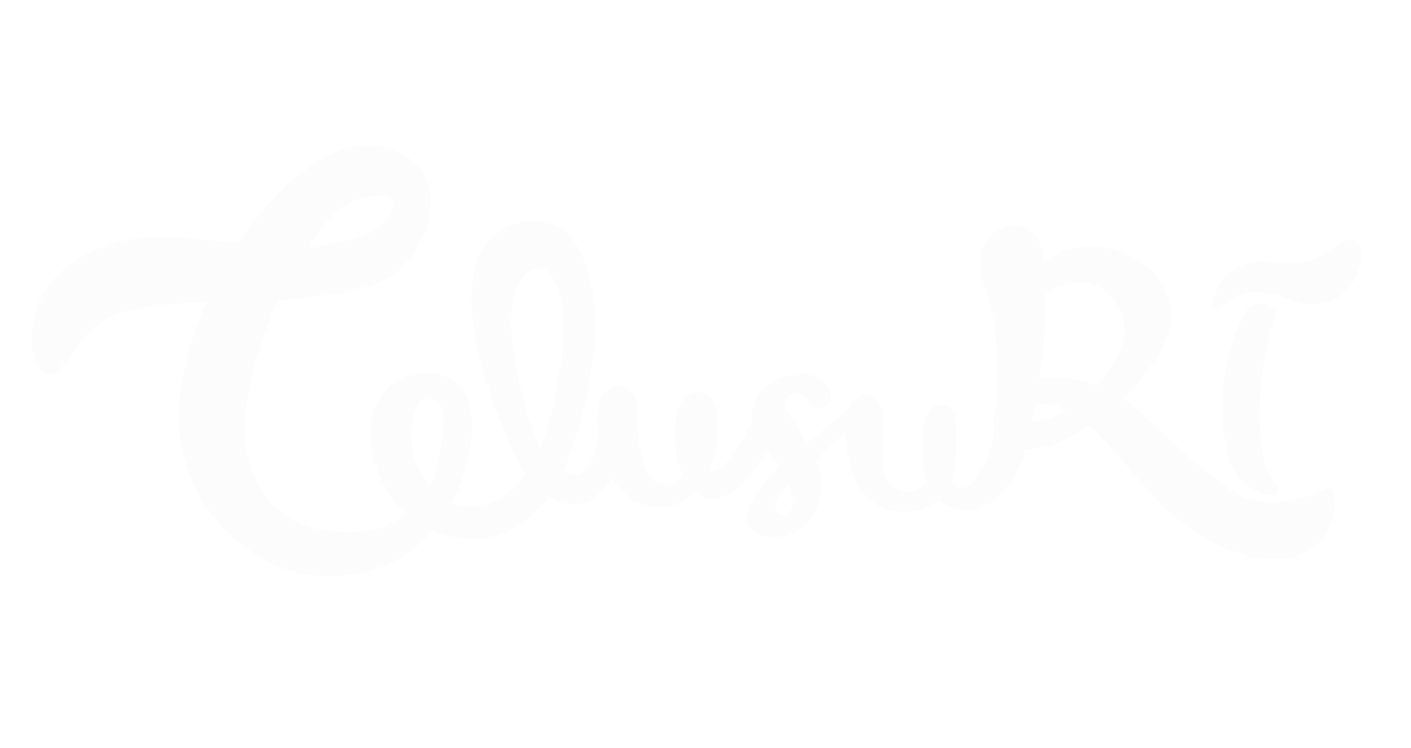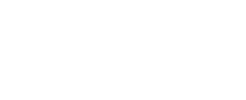Dari rawa hingga sawah, aneka jenis sumber pangan tersedia. Selanjutnya tergantung pada pengelolaan dan dukungan kebijakan yang kondusif agar Sanggase mandiri pangan.
Teks: Rifqy Faiza Rahman
Penyunting: Mauren Fitri ID
Foto: Deta Widyananda
Sepintas, Sanggase seperti kampung kecil pada umumnya di Kabupaten Merauke. Terpencil, aksesibilitas gampang-gampang susah, dan kondisi jalan perlu perhatian khusus. Dampaknya, ongkos logistik mahal. Biaya bahan-bahan pangan, bahan bakar minyak, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang hanya bisa disuplai dari luar kampung melambung tinggi. Satu-satunya infrastruktur publik yang patut disyukuri adalah keberadaan menara pemancar sinyal base transceiver station (BTS) dari Kominfo, sehingga jalur komunikasi seluler maupun internet relatif lancar.
Seolah menyadari keterbatasan yang ada, masyarakat adat Malind di Sanggase pun terlatih mengoptimalkan sumber daya yang ada di kampung. Terutama bahan-bahan pangan lokal, yang semuanya berasal dari alam sekitar—hutan, sungai, laut, dan rawa. Warisan wawasan leluhur secara turun-temurun sangat berperan dalam memanfaatkan anugerah Tuhan yang hidup dan tumbuh di wilayah adat Sanggase.
Siapa sangka, kampung di ujung timur Distrik Okaba ini punya ‘mutiara’ pangan yang berlimpah, dan memiliki potensi ekonomi tinggi. Bisa dibilang, hampir semuanya ada, tinggal bagaimana mengelolanya.

Memperkuat pasokan pangan lewat padi rawa
Topografi wilayah Kampung Sanggase memang lebih dominan hutan dataran rendah, rawa, dan dialiri kali-kali (sungai) yang bermuara ke laut selatan Merauke. Beberapa kompleks dusun sagu, sumber pangan utama masyarakat Sanggase, juga kelapa yang jadi bahan baku kopra, terletak di pedalaman hutan yang dipisahkan rawa. Untuk menjangkaunya, warga harus sedikit ‘menyelam’ di perairan rawa gambut setinggi dada orang dewasa.
Begitu pun lahan padi, yang ditanam di perairan rawa dan berlokasi cukup jauh dari kampung. Di Sanggase, padi menjadi alternatif baru yang tidak hanya menjadi sumber pangan pokok, tetapi juga sumber ekonomi alternatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sagu dipertahankan sebagai pangan utama, sementara beras hadir melengkapi dan memberi nilai tambah ekonomi dengan memanfaatkan areal rawa pasang surut sebagai lahan produktif.
Salah satunya, seperti yang dilakukan Agustina Matiwen (34). Kami menemuinya Sabtu siang (23/8/2025), di sebuah pondok sederhana yang dibangun setinggi dua lantai. Pondok seluas kira-kira 3×7 meter itu terletak di atas pematang, diapit sawah dan kali drainase yang berlimpah ikan. Bangunan dari kayu dan seng itu disebut pondok kadu atau pondok padi, karena digunakan sebagai tempat singgah selama menanam padi dan lumbung untuk menyimpan gabah (termasuk hasil panen tahun lalu).
Agustina tidak sendirian. Ia ditemani anak-anak dan kerabatnya, Yohana Matiwen dan Nina Kahol. Mereka jalan kaki hampir 6 kilometer ke arah timur dari kampung. “Kami datang untuk kasih bersih pondok, karena Senin besok (25/8/2025) mau tanam padi. Kami di sini tiga bulan, sampai panen,” katanya.
Maka di pondok tersebut tidak hanya berisi kelengkapan tanam dan panen, tetapi juga jala ikan, perabot masak, dan bahan-bahan makanan. Ruang bawah untuk gudang dan dapur, sedangkan ruang atas untuk tidur dan bersantai. Selama tiga bulan, mereka akan tinggal di pondok tersebut, menunggui sawah sampai masa panen tiba.



Agustina Matiwen menunjukkan pondok kadu miliknya yang terletak di tepi lahan rawa pasang surut dan gabah kering hasil panen tahun sebelumnya yang masih tersimpan
Lahan sawah yang hendak digarap di area pondok seluas satu hektare. Menurut perkiraan Agustina, butuh waktu dua minggu untuk merampungkan penanaman benih padi. Lahan ini milik marga adat Boiyen. Marga Matiwen sendiri punya lahan sawah di tempat berbeda. Meskipun begitu, sudah jadi tradisi jika setiap keluarga dari masing-masing marga saling gotong royong untuk menanam dan merawat sawah, termasuk dusun sagu sekalipun.
Dalam satu tahun, petani Sanggase bisa dua kali menanam padi, yang biasa terjadi pada semester kedua tahun tersebut. Satu hektare sawah bisa menghasilkan 150 karung gabah kering, dengan estimasi bobot sekitar 25–35 kg per karung. Agustina biasa menjual beras Rp15.000 per kilogram, dengan sasaran pasar di area kampung saja.
Pertanian padi termasuk komoditas yang terbilang baru dikembangkan di Sanggase. Melalui inisiatif Hendrik Roroh, pendeta GPI (Gereja Protestan Indonesia) di Distrik Okaba, dan kerja sama Yayasan EcoNusa dengan Dinas Pertanian Kabupaten Merauke, telah diadakan pelatihan pertanian padi dan sayuran organik pada 7–8 Juli 2022. Pelatihan tersebut diikuti puluhan peserta dari Sanggase dan Alatep, kampung tetangga.
Kepala Kampung Sanggase Yohanes Kilay (56) mengamini potensi budi daya padi di wilayahnya. Ia sejak lama terbuka terhadap rencana produksi pertanian padi untuk ketahanan pangan. Bahkan dengan dukungan para tetua adat, menyatakan sanggup menyiapkan lahan-lahan sawah potensial di area rawa pasang surut. Namun, dengan satu catatan, atau lebih tepatnya ada syarat wajib yang harus dipenuhi berkaitan dengan tata kelola.
“Pada prinsipnya kami tidak menolak [program swasembada pangan pemerintah], tetapi ada mekanisme yang perlu diubah, [yaitu dengan] masyarakat yang langsung kelola sendiri [program] itu, tidak melalui perusahaan,” tegas pria berdarah Ambon itu.

Mempertahankan sagu
Di tengah peluang besar pengembangan produksi padi, masyarakat Sanggase tidak melupakan daa (sagu). Ketika zaman dahulu sangat bergantung pada sagu, kini pun sagu tetap jadi penopang pangan keluarga ketika tidak sedang musim padi, atau tidak memiliki uang untuk membeli beras. “Kalau ada uang, kita beli beras. Kalau tidak ada uang, kita makan sagu,” ujar Albertina Nasemhe (53), yang saat ditemui sedang pangkur sagu di pekarangan dekat rumahnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa hutan sagu tetap harus dipertahankan sebagai sumber pangan masyarakat.
Rutinitas ke dusun sagu yang rata-rata jauh ke pedalaman hutan dan rawa, masih mudah dijumpai di Sanggase. Pekerjaan keluarga ini melibatkan cukup banyak orang, dari suami istri, hingga anak-anak, menantu, dan kerabat terdekat. Antara laki-laki dan perempuan memiliki peran berbeda. Para pria biasanya kebagian tugas menebas dan menggaruk (menokok) sagu, sedangkan para mama melanjutkannya dengan memangkur sagu.
Siang itu (25/8/2025) Albertina tidak sendiri. Ia ditemani suaminya, Yanuaris Janggai Mahuze (62), yang tengah beristirahat usai memanggul berkarung-karung empulur sagu dari dusun. Meski proses pengolahan sagu di Papua umumnya relatif sama, tetapi kadang-kadang setiap daerah memiliki bentuk alat dan fungsinya sendiri.
Di Merauke, alat pangkur sagu tidak didesain khusus seperti halnya Sorong atau Sorong Selatan. Albertina, dan umumnya masyarakat Sanggase, menggunakan sebilah kayu tanjung untuk menumbuk empulur sagu yang akan diramas. Lokasi pangkur pun sedikit berbeda. Jika masyarakat Sorong atau Sorong Selatan memangkur di area tebasan sagu, sementara masyarakat Sanggase memangkur di tempat yang sama dengan meramas.
Menurut Yanuaris, satu pohon sagu yang siap panen (kira-kira usia 10 tahun) di Sanggase bisa diolah berkali-kali. Dalam satu hari, ia dan istri mampu menghasilkan empulur sagu sebanyak 2–3 bakuma (keranjang dari anyaman daun kelapa). Bobot rata-rata 20 kilogram per bakuma. Dari jumlah segitu, pati sagu yang dihasilkan selanjutnya bisa diolah dan mencukupi kebutuhan pangan beberapa keluarga dalam hitungan minggu. Biasanya, olahan sagu yang dihasilkan lebih banyak dikonsumsi sendiri daripada dijual.


Albertina Nasemhe masih rutin mengolah sagu menjadi bahan makanan pokok untuk keluarga di rumah
Hasil perikanan berlimpah
Sumber pangan masyarakat Sanggase tidak hanya berhenti di padi, sagu, maupun hewan-hewan buruan di hutan. Posisi Sanggase sebagai kampung pesisir dan luasnya kawasan rawa yang mengepung permukiman menandakan potensi lain, yakni hasil perikanan.
Dari area pantai, umumnya warga atau nelayan memancing atau menjala ikan-ikan laut (pari, bandeng, sembilang, kakap), udang, dan kepiting. Sementara di kawasan rawa, terdapat ikan mujair, kakap rawa, gastor (gabus), belanak, dan betik.
Pada musim puncak ikan, biasanya sekitar Juli–Agustus, ikan-ikan beragam jenis dan ukuran akan lebih mudah dijumpai. Banyak titik penangkapan ikan, terutama di aliran kali dan daerah rawa. Selama periode ini, kita akan melihat rutinitas pemuda hingga orang tua pergi menjala atau memancing ikan. Hasil tangkapannya pun tampak ‘di luar nalar’, khususnya kakap rawa, karena tidak sedikit yang berukuran jumbo, sampai-sampai tidak muat disimpan di freezer standar. Ada ikan yang panjangnya hampir menyamai tinggi anak SD.

Ikan-ikan yang berukuran raksasa menandakan ekosistem rawa di Sanggase terbilang baik dan belum tercemar limbah kimia. Kondisi air pun relatif jernih, khas rawa gambut. Sumber pangan ikan-ikan pun melimpah dan sehat. Di kampung, ikan-ikan besar tersebut dihargai kurang dari 50 ribu rupiah per ekor. Kadang uang segini bisa mendapatkan seikat ikan berukuran sedang, cukup untuk stok makan seminggu.
Namun, sektor perikanan Sanggase menghadapi tantangan besar. Menurut Moses Ramsis Boi, program associate Yayasan EcoNusa Merauke, pada Juli–Agustus banyak ikan terbuang karena kurang terserap oleh pasar. Meskipun ada pengepul, kapasitasnya pun terbatas. Masyarakat pun tidak akan mampu makan banyak ikan dalam waktu singkat. Ia mencatat, tahun 2023 pernah ada 14 ton ikan (laut dan rawa) terpaksa membusuk dan dikubur karena tidak ada pembeli.
Kepala Kampung Sanggase juga melihat kendala ini. Pihaknya sedang mengupayakan untuk mencari jalur pengepul atau pedagang besar dari Merauke yang bisa membeli ikan dari Sanggase. Termasuk mempertimbangkan wacana membuka akses turisme minat khusus, yakni paket wisata memancing saat musim puncak ikan. Selain hasil tangkapan yang bisa diolah, manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata yang dikelola berkelanjutan juga dapat dirasakan masyarakat.
Cita-cita ekspor kopra
Kelapa (mes) adalah salah satu pohon paling dominan, mudah ditemui, dan banyak menghasilkan buah yang berlimpah di Sanggase. Dari barat ke timur kampung, di daratan maupun pesisir, nyiur-nyiur tumbuh menjulang. Saat siang terik, kelapa selalu jadi suguhan terbaik untuk menghapus haus tatkala berkebun, mencari ikan, hingga memanen sagu. Bahkan saat kampung belum memiliki kendaraan antar-jemput sekolah ke pusat distrik, anak-anak SMP–SMA biasa mengunduh kelapa segar di tengah perjalanan menuju atau sepulang sekolah.
Di Sanggase, kelapa tidak hanya berfungsi sebagai pelepas dahaga. Salah satu produk turunan dari olahan kelapa yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat adalah kopra. Jefri Ndiwaen (40) merupakan segelintir orang—bahkan sejauh ini satu-satunya—yang melihat harapan besar pada bongkahan-bongkahan batok kelapa kering itu.
Tahun 2023, Indonesia tercatat menempati peringkat teratas sebagai eksportir kopra terbesar di dunia. Negara dengan garis pantai terpanjang di dunia itu menghasilkan lebih dari 45 juta kilogram kopra dengan nilai ekspor 33,5 juta dolar Amerika Serikat. Jauh mengungguli India, Uni Emirat Arab, Vietnam, dan Sri Lanka. Dalam hitungan Jefri, jika kondisi pasar ideal (dengan rata-rata harga jual kopra Rp13.000-15.000 per kilogram), seorang petani kopra seperti dirinya bisa memperoleh pendapatan 20–30 juta rupiah per bulan.
Permintaan pasar terhadap kopra memang sangat tinggi karena punya banyak kegunaan. Selain minyak kelapa murni, kopra menjadi bahan baku untuk industri makanan (margarin hingga minyak nabati lainnya), produksi sabun dan deterjen alami, industri kosmetik dan produk-produk perawatan kulit, bahan bakar ramah lingkungan (biodiesel), pakan ternak, dan industri farmasi.



Serangkaian proses pembuatan kopra, mulai dari mengupas sabut kelapa, mencungkil kelapa, dan membakar kopra di bawah para-para
Proses pembuatan kopra sendiri cukup panjang dan melelahkan, karena berlangsung secara tradisional tanpa bantuan mesin. Semuanya membutuhkan fisik dan fokus yang prima. Mulai dari mengupas sabut kelapa kering, mencungkil dagingnya, membakar, hingga mengeringkan.
Ada beberapa hal menarik perihal pengolahan kopra di Sanggase. Pertama, sistem panen kelapa di Sanggase berlangsung secara alami, dan bisa dibilang berkelanjutan. Masyarakat tidak harus capek-capek memanjat, tetapi menunggu dan mengambil buah-buah kelapa yang jatuh ke tanah. Salah satu tantangan yang harus dihadapi, di antaranya lokasi dusun kelapa yang rata-rata jauh dari permukiman, bahkan harus menyeberangi rawa setinggi dada.
Kedua, sirkulasi ekonomi kopra berputar di masyarakat. Jefri menjadi pengepul terbesar yang menampung kelapa-kelapa hasil panen masyarakat kampung. Ia tidak mengetahui secara pasti, tetapi setidaknya 300-an petani kelapa menjual hasil panennya kepada Jefri.
“Saya sendiri punya dusun [kebun] kelapa juga. Cuma kita kan di sini saling membantu, karena tidak ada pembeli yang datang ke kampung. Akhirnya, saya sebagai anak [kampung] sini, bekerja membantu [membeli] kelapa dari masyarakat,” ungkapnya. Suami Indriani Golut itu membeli dari petani seribu rupiah per buah. Setiap petani bisa membawa belasan hingga puluhan kelapa buah kepada Jefri.
Di sisi lain, Jefri mengakui masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu penyebabnya, seperti yang ia lihat sendiri, banyak pengepul nakal yang menjatuhkan harga di bawah rata-rata pasar. Jika boleh memilih, ia lebih ingin menjual kopranya langsung ke eksportir pemilik kontainer dan kapal besar dari Surabaya, daripada menjual ke Kota Merauke. Sayangnya, akses langsung seperti itu belum dimiliki Jefri, yang kemampuan pengolahan dan kapasitas gudang penyimpanannya masih terbatas. Hal ini menunjukkan masih ada ‘pekerjaan rumah’ besar untuk meningkatkan nilai tambah kopra-kopra Sanggase dan kampung-kampung pedalaman lainnya di Merauke.
Namun, meski jalannya masih panjang dan terjal untuk bisa terlibat dalam ekosistem ekspor kopra dunia, optimisme Jefri tak akan surut. Keberhasilan mengantar anak pertamanya, Yulita Ndiwaen, kuliah jurusan akuntansi Universitas Musamus Merauke dari hasil jualan kopra, melecut semangatnya untuk terus menghasilkan kopra-kopra terbaik dari Sanggase. Ia hanya berharap pemerintah dan para eksportir mau membuka mata dan hati, membimbing kopra-kopra dari kampung kecil menjadi unggul dan berkualitas tinggi. Agar Riki dan Rikordus, kedua putranya, juga melihat masa depan cerah dari profesi petani kopra.

Minyak kelapa tradisional
Tampaknya, tiada seorang perempuan di Sanggase yang seenergik Diana Fatubun (50). Seorang janda lima anak berdarah Tanimbar–Merauke yang selalu lantang bersuara, baik saat bicara maupun tertawa. Polahnya ekspresif, mengundang gelak pendengarnya. Tak jarang ia harus mengusir anjing-anjing nakal yang berkeliaran mengganggu pekerjaannya, atau mengusik lingkaran gosip bersama mama-mama tetangga.
Energi besar itu pun tersalurkan lewat ketangkasan Diana mengolah kelapa menjadi minyak kelapa. Di pekarangan samping rumahnya, Diana menularkan keahlian turun-temurun itu kepada Natalia Gebze dan Maria Mahuze, kerabatnya, memproduksi minyak kelapa setiap tiga hari sekali.
Seperti halnya kopra, bahan baku produksi dibeli dari orang kampung, untuk membantu perputaran ekonomi masyarakat. Diana membeli kelapa dari saudara atau tetangga dengan harga Rp1.500 per buah. Selanjutnya, Diana bersama Natalia dan Maria mengupas sabut dan tempurung kelapa, lalu memarut daging kelapa menjadi serpihan halus dengan mesin parut. Hasil parutan kelapa kemudian diperas dengan campuran air, disaring, dan didiamkan semalam untuk mengendapkan ampasnya. Keesokan harinya, saringan tersebut dimasak dan diaduk dalam wajan besar dengan api besar sampai menghasilkan minyak.
Dalam sekali produksi, ia bersama Natalia dan Maria mampu mengolah 100 buah kelapa untuk menghasilkan minyak kelapa sebanyak 10 liter. Biasanya, minyak 10 liter tersebut ditampung dahulu ke dalam dua jeriken berkapasitas masing-masing 5 liter. Dari jumlah itu, Diana mendapatkan 20 botol beling ukuran 500 ml, dengan harga jual Rp10.000 per botol. Hasil keuntungan penjualan ia manfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan putar modal lagi untuk produksi berikutnya.
Barangkali, sifat energik Diana juga jadi caranya untuk memeriahkan hari-harinya. Sebab, keuntungan ekonomi dari usaha minyak kelapa tradisional pun tak menentu. Apalagi di Sanggase yang cukup terpencil dan sangat jauh dari pusat kota Merauke. Tujuan penjualannya masih seputar kios-kios kecil di kampung. Itu pun belum tentu cepat laku, sehingga Diana pun tidak setiap saat memproduksi minyak kelapa karena kapasitas penyimpanan kios juga terbatas. Jika kondisi begini, ia harus memutar otak untuk mencari sumber pendapatan lain.
“Jadi, kalau di kios mungkin minyak [kelapa] masih banyak, ya, sudah terpaksa mama istirahat dulu di rumah. Mama harus lari lagi [cari] pekerjaan lain, mungkin mama bikin kue atau kelapa itu mama asar [bakar], mama jadikan kopra,” ungkapnya.
Namun, Diana tak memungkiri tetap ada manfaat ekonomi yang dirasakan dari puluhan tahun jualan minyak kelapa dan kopra. Salah satunya bisa membayar uang sekolah anak-anak. Spirit dan kebebasan yang diberikan oleh mendiang suami, Felix Mario Sanuddin, juga turut melecut Diana untuk tetap produktif sehari-hari.



Sekelumit proses pembuatan minyak kelapa oleh Diana Fatubun di belakang rumahnya
Terbuka untuk pangan lokal, tertutup untuk sawit
Keberagaman sumber pangan masyarakat Sanggase adalah sinyal positif, bahwa masyarakat Malind-Anim di Merauke sesungguhnya memiliki harapan kemandirian pangan di masa depan. Berdaulat atas potensi pangan dari sumber daya alam yang dikelola sendiri, tanpa menunggu atau bergantung pasokan dari pusat kota. Sebab, kedaulatan pangan menjadi fondasi terwujudnya ketahanan pangan, yakni sebuah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap warga karena ketersediaan sumber pangan yang baik.
Salah satu prasyarat mutlak untuk menjamin mimpi kedaulatan pangan itu adalah kebijakan politik dan ekonomi yang kondusif. Kebijakan menjadi dasar program-program teknis yang muaranya pada peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk melindungi produsen dalam negeri—dalam hal ini masyarakat pelaku usaha pangan lokal—dari gempuran produk-produk pangan impor dan sistem perdagangan bebas yang tidak adil. Salah satu cara teknis untuk mendukung itu di antaranya membuka kemudahan akses permodalan dan pasar bagi petani dan nelayan kecil, profesi-profesi yang mendominasi 49% total angkatan kerja Indonesia.
Ambisi besar swasembada pangan pemerintah melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), yang kerangkanya memuat program ketahanan pangan, swasembada bioenergi, dan agribisnis, mestinya bisa bermanfaat luas jika ada keberpihakan pada masyarakat adat. Seperti Yohanes sampaikan, masyarakat adat akan terbuka jika program pangan berbasis keterlibatan masyarakat adat. Bukan lewat pembagian kue-kue konsesi pada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu.
Yohanes, bersama masyarakat adat Malind-Anim Imo Sanggase, juga memberi peringatan keras dengan tidak mengizinkan masuknya rencana investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam bentuk apa pun. “Kami di sini menolak [kelapa sawit], karena, ya, hutan kami memang harus dijaga. [Kami] takut kerusakan hutan nanti berdampak untuk kita semua,” pungkasnya.
Kolaborasi yang harmonis antara pemerintah kampung dan masyarakat adat tersebut patut diapresiasi. Mereka ingin memastikan, hutan, sungai, laut, dan rawa yang menghidupi kampung masih bisa diwariskan untuk anak cucu di masa depan.
Foto sampul: Lanskap rawa di Kampung Sanggase, salah satu sumber hasil perikanan yang melimpah. Area pasang surutnya juga bisa ditanami padi.
Pada Agustus–September 2025, tim TelusuRI mengunjungi Merauke (Papua Selatan), Jayapura (Papua), serta Tambrauw dan Sorong (Papua Barat Daya) dalam ekspedisi Arah Singgah: Tanah Kehidupan. Laporan perjalanannya dapat Anda ikuti di telusuri.id/arahsinggah2025.
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.
Jika tidak dituliskan, bahkan cerita-cerita perjalanan paling dramatis sekali pun akhirnya akan hilang ditelan zaman.