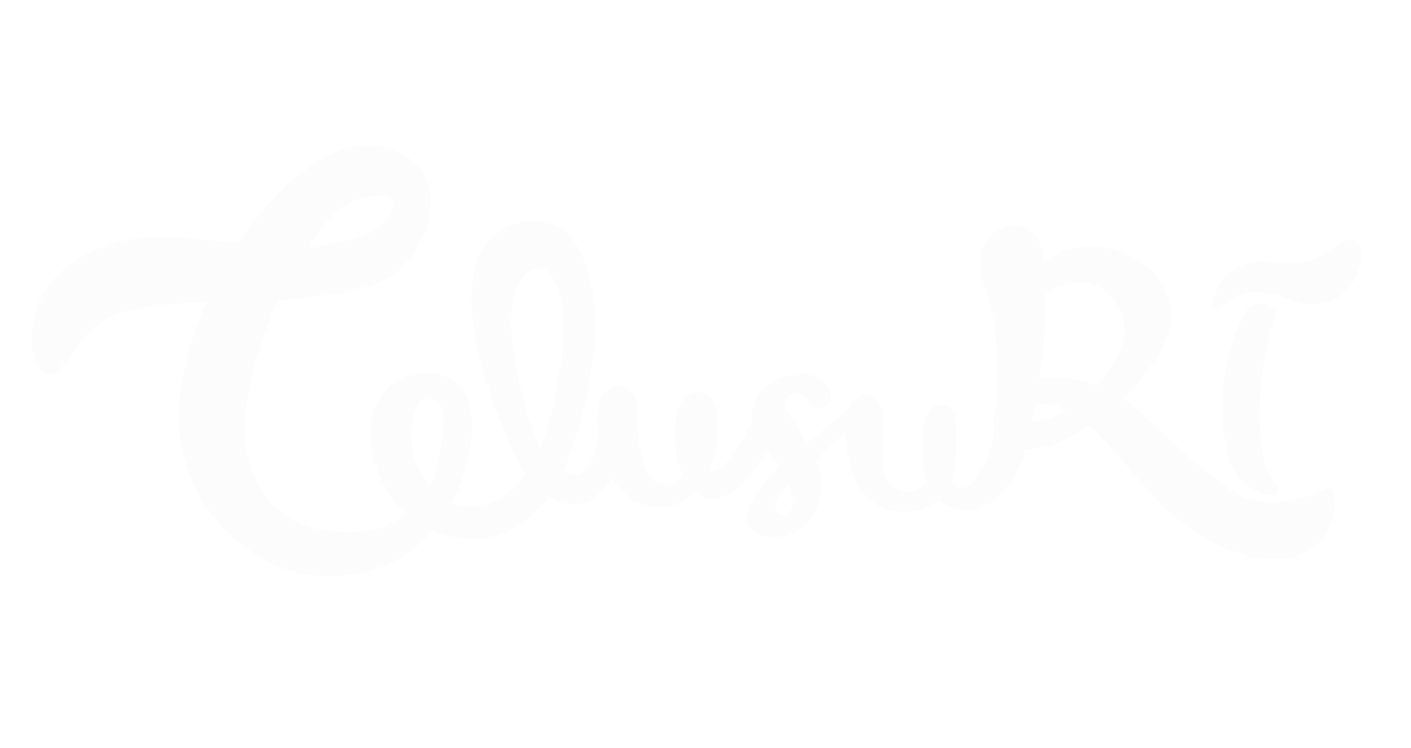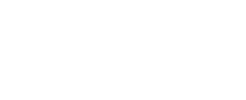Hutan adalah mama, hutan adalah ibu, begitulah cara orang-orang Papua menghormati hutan. Makin ke sini, makin setengah mati menjaganya.
Teks: Rifqy Faiza Rahman
Penyunting: Mauren Fitri ID
Foto: Deta Widyananda

Bisa jadi, selalu ada satu petak hutan yang hilang setiap harinya di Papua. Kebanyakan karena pembukaan lahan untuk kebutuhan korporasi, alasan pembangunan daerah, atau dalih pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Sebagian telah diketahui publik, sisanya mungkin masih banyak yang belum terendus. Terbaru, rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan, yang terus berjalan meski mendapat penolakan banyak pihak.
Dalam jangka panjang, megaproyek PSN Merauke berencana menggarap lahan hutan seluas 2,29 juta hektare—kira-kira 70 kali luas Jakarta—untuk cetak sawah dan perkebunan tebu baru di atas ekosistem hutan dan rawa gambut, serta pabrik gula dan bioetanol.1 Di sisi lain, rencana ekspansi industri ekstraktif semacam perkebunan kelapa sawit juga belum berhenti, baik itu di Sorong, Jayapura, Merauke, maupun Boven Digoel.
Pembukaan lahan hutan besar-besaran menambah daftar panjang riwayat deforestasi di Papua Selatan. Forest Watch Indonesia mencatat bahwa laju deforestasi di Papua Selatan meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 190.000 hektare (hampir setara tiga kali luas Jakarta) pada 2022–2023. Studi CELIOS memperkirakan akan ada emisi karbon sebesar 782,45 juta ton CO₂ yang terlepas, setara dengan kerugian karbon mencapai Rp47,73 triliun. Lonjakan emisi yang drastis tersebut kontradiktif dengan komitmen Indonesia mengejar Net Zero Emission pada tahun 2050.2
Secara keseluruhan, selama periode 2001–2024, Papua telah kehilangan sedikitnya 1,1 juta hektare tutupan pohon. Sekitar 65 persen di antaranya merupakan hutan primer basah.3 Ratusan juta ton emisi karbon terbuang, memperparah perubahan iklim. Sementara masyarakat adat Papua, dengan kearifan lokal dan pengetahuan nenek moyang yang telah berperan menjaga keutuhan hutan, tanpa disadari ikut terdampak deforestasi.
Sistem kehidupan masyarakat Papua yang berbasis adat tengah menghadapi saat-saat tersulitnya. Namun, di satu sisi ada ruang harapan dan keberpihakan yang tumbuh, meski harus meniti jalan yang penuh tantangan. Lalu bagaimana selanjutnya? Mengapa kita harus melindungi masyarakat adat?

Suara perlawanan dengan jalan yang elegan
Sepanjang perjalanan ekspedisi Arah Singgah di Papua tahun 2024–2025, kami melihat kesamaan perspektif yang gamblang dari masyarakat adat terhadap hutan maupun lingkungan alam di sekitarnya. Perspektif itu menjadi prinsip hidup yang absolut: hutan adalah ibu atau hutan adalah mama. Ibu atau mama dianggap sebagai sumber kehidupan, yang dari rahimnya sendiri bisa menghasilkan keturunan, memberi makanan, minuman, hewan buruan, obat-obatan, dan juga warisan pengetahuan leluhur.
Di dalam ekosistem hutan—tidak terbatas pada jenis hutan di darat maupun pesisir—keanekaragaman hayati hidup berdampingan dalam keteraturan, saling membutuhkan satu sama lain. Maka, kehilangan satu pohon sudah terlalu banyak. Sebab, ada satu entitas kehidupan—ibu—yang hilang.
Kami menemui masyarakat adat lintas generasi di banyak kampung, yang memiliki cara tersendiri dalam melindungi ‘ibu’ mereka. Seperti masyarakat suku Moi di Kampung Klabili, Tambrauw, Papua Barat Daya. Mereka menempati kampung kecil tepi jalan poros Sorong–Tambrauw, di pintu Lembah Klasow, hutan tropis terakhir tanah Moi. Keberadaan puluhan spesies burung endemik di dalamnya, mulai dari cenderawasih, mambruk, paok mopo-papua, paok hijau-papua, hingga julang papua; menjadi daya tarik magis untuk mengundang para pencinta kegiatan pengamatan burung atau paksiwisata (birdwatching).
Melalui ekowisata, warga Kampung Klabili memiliki ‘senjata’ terbaik untuk melindungi hutan mereka. Menjual (daya tarik) hutan, tanpa merusak hutan. Sebab, desas-desus tentang wacana proyek strategis nasional yang akan merambah Lembah Klasow pun telah sampai ke telinga mereka. Kekhawatiran mencuat, takut dusun sagu, hutan, dan habitat burung-burung tergusur industri ekstraktif seperti sawit, pertambangan, atau food estate tanpa kajian mendalam.
Kepala Kampung Klabili, Yoram Kalami, menegaskan ekowisata sebagai bentuk perlawanan terhadap rencana apa pun yang berpotensi merusak hutan suku Moi. Ia ingin ekowisata bisa menjadi jalan hidup masyarakat untuk memperbaiki taraf ekonomi. Selain itu ekowisata diharapkan dapat memproteksi hutan yang tidak hanya menyimpan kebutuhan sehari-hari masyarakat, tetapi juga menjaga tempat-tempat sakral leluhur suku Moi. Begitu pun yang dilakukan oleh orang-orang Moi di Malaumkarta Raya, mengedepankan ekowisata, edukasi dan pelestarian budaya untuk menunjukkan eksistensi diri.
Lalu Petronela Meraudje dan mama-mama anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Ibayauw di Kampung Enggros, Jayapura, membuktikan upayanya berdaya dengan aksi konservasi maupun pembuatan produk-produk UMKM. Petronela dan para mama berjuang mempertahankan ekosistem mangrove Hutan Perempuan Teluk Youtefa yang kian kritis karena pembangunan kota dan persoalan sampah perkotaan. Mereka bersuara dengan langkah-langkah nyata, termasuk mengkader dan mengedukasi anak-anak PAUD sebagai generasi penerus pejuang lingkungan dan ekonomi restoratif Enggros di masa depan.
Sementara nun jauh di ujung tenggara Papua, ‘suara perlawanan’ lainnya diserukan dengan cara agak berbeda di Sanggase, Distrik Okaba, Merauke. Pemerintah kampung menjadi benteng pertama untuk melindungi segala tradisi lokal dan kawasan hutan adat Malin Imo di Sanggase. Kepala kampung, Yohanes Kilay, merangkul masyarakat adat Malind Imo untuk membangun kampung. Pria berdarah Ambon itu melibatkan tetua adat, tokoh masyarakat, hingga generasi muda untuk berperan memajukan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kampung. Tak terkecuali rencana swasembada pangan, yang ia terima dengan syarat pengelolaan langsung oleh masyarakat, bukan perusahaan. Selain pangan, entah itu kelapa sawit, tambang, ataupun industri ekstraktif lainnya, ditolak keras di Sanggase.
Jatuh bangun masyarakat adat Papua dalam mempertahankan ruang hidupnya, menunjukkan dua sisi yang berlawanan. Satu sisi, kami diperlihatkan pelajaran berharga tentang cara dan pola hidup mereka dalam merawat hutan, rawa, dan lautan yang mengelilingi keseharian masyarakat. Di sisi lain, mereka seperti bersuara dan berjuang sendirian untuk sesuatu yang seharusnya bernilai, tetapi tidak selalu didengar apalagi dipahami pihak-pihak lain—yang menganggap ruang hidup tersebut sebagai tempat yang kosong atau tak ada tanda-tanda kehidupan.
Liku-liku hak masyarakat adat dan peluang COP30 untuk Papua
Di kanal YouTube KaderadotId, saya melihat penjelasan menarik dari Dr. Phil. Geger Riyanto, dosen Antropologi Universitas Indonesia, tentang konsep teritori masyarakat adat khas Nusantara. Ia hadir sebagai saksi ahli dalam sidang 11 warga adat Maba Sangaji, Halmahera Timur di Pengadilan Negeri Soasio, Tidore Kepulauan, Senin (6/11/2025).4
Kepada majelis hakim, lulusan S-3 Institut Antropologi Heidelberg, Jerman itu menceritakan penelitian koleganya tentang pola kehidupan masyarakat adat di Papua. Hasil risetnya mengungkap bahwa wilayah adat masyarakat Papua umumnya berbentuk seperti jaring laba-laba, bukan teritori kartografi modern serupa piringan yang membagi batas wilayah secara jelas. Masyarakat Papua memiliki dusun sagu, sumber air, tempat keramat, bahkan hutan untuk berburu maupun meramu obat-obatan tradisional di lokasi yang berbeda-beda, dan berjarak cukup jauh dari kampung atau tempat tinggal mereka. Bahkan beberapa suku di masa lalu hidup berpindah, dari kampung lama ke kampung baru atas pertimbangan adat demi penghidupan yang lebih baik.
Pola kehidupan tersebut menjelaskan bahwa umumnya keterikatan masyarakat adat dengan hutan tidak hanya berbicara soal tempat, tetapi juga sumber penghidupan, ritual adat, dan riwayat sejarah. Namun, konflik-konflik agraria yang masih terus terjadi di banyak tempat di Indonesia, menunjukkan pemerintah maupun korporasi tidak memahami kultur dan perspektif masyarakat adat. Blunder pernyataan pejabat setingkat menteri, seperti Bahlil Lahadalia yang menyebut tidak ada hutan di Merauke, atau Nusron Wahid yang menyebut ratusan ribu hektare lahan yang dilepas di Papua Selatan sebagai ‘tanah negara’ dan ‘tidak berpenghuni’, adalah bukti paling sahih yang melukai hati masyarakat adat. Padahal, setiap jengkal tanah hingga kawasan perairan di Papua memiliki penjaganya, yang tak lain masyarakat adat itu sendiri.
Berlarut-larutnya perebutan ruang hidup atas tanah dan sumber daya hutan menimbulkan efek samping yang tidak sepele— sosial, politik, dan ekonomi—dan semestinya bisa dicegah. Salah satu caranya adalah mengakselerasi pengakuan hak dan hajat hidup masyarakat hukum adat beserta hutan adat yang menjadi sumber penghidupan, baik itu di kawasan hutan negara maupun bukan.5
Dalam catatan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), sejak 2016 terdapat 33,6 juta hektare yang tercatat sebagai wilayah adat di Indonesia. Namun, pemerintah baru mengakui 156 hutan adat seluas 332.505 hektare. Khusus region Papua, yang memiliki 14,8 juta hektare wilayah adat, baru tujuh hutan adat yang diakui negara (satu di Papua Barat dan enam di Papua) dengan total hanya 39.912 hektare. Tidak sampai 0,3 persen dari keseluruhan wilayah adat.6
Di sisi lain, pemerintah justru lebih agresif melepas kawasan hutan untuk kepentingan komersial. Teranyar, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025 pada 18 September 2025, yang intinya melepas kawasan hutan Papua Selatan seluas 486.939 hektare, dan mengubahnya menjadi bukan kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kepentingan mendukung percepatan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional. Rinciannya: 333.966 hektare di Merauke, 143.142 hektare di Boven Digoel, dan 9.731 hektare di Mappi. Kebijakan ini tidak hanya merambah ruang hidup keanekaragaman hayati dan masyarakat adat, tetapi juga melampaui batas-batas wilayah administratif.
Padahal, konvensi internasional telah menyepakati Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). FPIC merupakan sebuah mekanisme yang memungkinkan masyarakat adat atau komunitas lokal menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap sebuah aktivitas, proyek, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di wilayah adat masyarakat dan berpotensi memberi dampak kepada tanah, kawasan, hingga sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.7

FPIC menegaskan empat hal. Free, bermakna masyarakat adat bebas dari tekanan untuk menyampaikan pendapat tanpa paksaan pihak mana pun. Prior, adalah proses perolehan persetujuan masyarakat adat yang mesti dilakukan sebelum proyek atau kebijakan diterapkan. Informed, yakni sebelum proses pemberian persetujuan, masyarakat adat harus benar-benar mendapat informasi proyek atau kebijakan yang utuh dalam bahasa dan bentuk yang mudah dimengerti, serta disampaikan oleh pihak yang memahami konteks budaya setempat dan memasukkan aspek pengembangan kapasitas masyarakat lokal. Consent, berarti setiap keputusan kolektif masyarakat adat—termasuk hak menolak—harus dihormati.
Dalam konteks PSN Merauke di Papua Selatan, termasuk proyek-proyek lainnya di Tanah Papua, FPIC tampaknya belum menjadi standar etika bahkan luput diperhatikan. Jika seseorang ingin memasuki rumah Anda, bukankah Anda berharap mereka mengetuk pintu dan bertanya terlebih dahulu untuk meminta izin? Tak heran situasi yang dihadapi masyarakat adat Papua mendapat sorotan dunia. Termasuk sembilan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Special Procedure Mechanism), yang menyurati pemerintah Indonesia dan PT Global Papua Abadi (perusahaan perkebunan tebu, pabrik gula dan bioetanol yang terafiliasi PSN Merauke) pada 7 Maret 2025 perihal dugaan pelanggaran hak asasi manusia, analisis dampak, dan kemungkinan evaluasi dari megaproyek tersebut.8
Menurut Abdi Akbar, Direktur Perluasan Partisipasi Politik Aliansi Masyarakat Adat nusantara (AMAN), dalam pernyataannya kepada Global Alliance of Territorial Communities (GATC), FPIC sangat penting sebagai fondasi untuk menentukan hak dan masa depan masyarakat adat sesuai dengan cara hidupnya sendiri. Ia menambahkan, FPIC memastikan setiap suara—perempuan, laki-laki, dan orang muda—didengar saat pengambilan keputusan yang memengaruhi wilayah dan kehidupan masyarakat adat.9
Sebagai aliansi global yang mewakili 35 juta orang dari 24 negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin—AMAN menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia dan Asia—GATC mendorong dunia memenuhi lima tuntutan agar hutan dan masyarakat adat tetap lestari, yakni hak atas tanah, FPIC, akses pendanaan untuk aksi iklim, perlindungan dari kekerasan dan kriminalisasi, dan perlindungan pengetahuan tradisional. Oleh karena itu, Conference of Parties (COP30) yang akan berlangsung di Belém do Pará, Brasil, pada 10–21 November 2025, bisa menjadi momentum yang tepat untuk menggaungkan FPIC sebagai mekanisme yang sah agar hak ulayat masyarakat adat terjaga.
Menurut Center of Economic and Law Studies (CELIOS), setidaknya ada tiga kesempatan besar bagi Indonesia jika proaktif membawa isu tersebut melalui COP30.10 Pertama, peluang kerja sama bilateral untuk mempertajam strategi bioekonomi antara Indonesia dan Brazil, dua negara berkembang dengan hutan tropis terbesar di dunia. Kedua, memperbarui komitmen target pengurangan emisi tahun 2050 dengan rencana lanjutan lewat second NDC (Nationally Determined Contribution), yang sebelumnya telah ditetapkan penurunan emisi 29 persen secara mandiri dan 41% persen dengan dukungan global. Terakhir, peluang mengakses pendanaan penanganan perubahan iklim melalui inisiatif global terbaru, yakni Tropical Forest Forever Facility (TFFF), yang berbeda dengan bursa karbon dan bersifat jangka panjang untuk lebih melindungi hutan dan masyarakat adat.
Di atas semua itu, COP30 seharusnya menjadi momen krusial bagi Indonesia—khususnya—bersama negara-negara tropis lainnya, seperti Brazil, Kolombia, Peru, dan Republik Demokratik Kongo yang menopang 70 persen hutan tropis dunia yang tersisa; membuktikan keberpihakan pada masyarakat adat. Populasi masyarakat adat tidak lebih dari lima persen dari populasi dunia, tetapi mengelola lebih dari 80 persen keanekaragaman hayati global.11 Masyarakat adat merupakan kontributor terkecil terhadap perubahan iklim, tetapi merekalah yang paling menderita terdampak krisis iklim, di antaranya kehilangan tempat tinggal dan akses ke sumber penghidupan.12
Dr. Jane Goodall, primatolog dan konservasionis terkemuka yang baru berpulang 1 Oktober 2025 lalu, juga mengingatkan peran penting masyarakat adat sebagai penjaga bumi. “Masyarakat adat di seluruh dunia, sebelum mereka membuat keputusan besar, [mereka] selalu bertanya pada diri sendiri: bagaimana keputusan ini memengaruhi masyarakat kita tujuh generasi ke depan?”
Sekali lagi, COP30 menjadi panggung yang tepat untuk menyuarakan peran kunci masyarakat adat dan komunitas lokal Nusantara. Merekalah solusi terbaik pelestarian hutan dan menghadapi krisis iklim global. Dari tindakan di kancah lokal, untuk kebaikan bersama di tingkat global. Penegasan FIPC hingga pengakuan negara terhadap masyarakat adat pun tidak hanya sekadar pilihan atau hadiah, tetapi juga merupakan kewajiban negara—sudah tugasnya negara. Terlebih Papua, pulau dengan hutan alam dan wilayah adat terluas di Indonesia.
Sementara itu, di dalam negeri, pekerjaan rumah paling pertama yang harus diselesaikan hanya satu: kapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang sudah berdebu puluhan tahun di meja anggota dewan itu rampung?

Butuh banyak kepala dan hati yang tulus dan selaras
Untuk alasan yang lebih sederhana, masyarakat adat atau komunitas lokal memiliki hak dan kebebasan yang sama sebagai warga negara pada umumnya. Posisi mereka setara dengan individu lain yang berhak mendapatkan perlindungan, jaminan hidup, layanan pendidikan dan kesehatan, serta akses kegiatan ekonomi. Mereka hanya sedikit berbeda dengan asal usul, pola hidup, sistem hukum dan kelembagaan adat secara turun-temurun, yang memiliki pranata sosial dan aturan tersendiri untuk merespons perubahan teknologi, pengetahuan baru, atau arus modernisasi.13
Sejatinya, beban negara akan jauh lebih ringan jika memercayakan penanganan urusan konservasi dan pelestarian alam kepada masyarakat adat. Melalui Kementerian Kehutanan, negara telah mengakomodasi hutan adat sebagai skema perhutanan sosial. Artinya, dengan kapasitas sumber daya manusia dan kekuatan jejaring maupun anggaran, semestinya negara bisa lebih kreatif merencanakan program-program non-ekstraktif dan tidak merugikan masyarakat adat maupun komunitas lokal. Mereka jauh lebih paham tanah tempat mereka terlahir, hidup, hingga mati; serta bagaimana merawatnya sebagai warisan untuk anak cucu di masa depan.
Beragam kampanye hingga pembahasan di forum internasional seperti tiada lelah meneriakkan pentingnya keadilan untuk masyarakat adat Indonesia, baik itu Papua dan pulau-pulau lainnya di Nusantara. Di luar sana, masyarakat adat dari berbagai belahan dunia pun berada di garda perjuangan yang sama, bahwa ada warisan bumi dan leluhur yang patut dipertahankan. Sebab, ada napas-napas yang hidup dan detak jantung yang berdenyut di atas tanah-tanah (yang dianggap tak bertuan) itu.
Di tengah tekanan negara, korporasi, dan ketidakadilan yang dialami, mereka tanpa lelah berjuang dan bersuara hingga serak: kami hidup dan kami ada. Lalu, bagaimana selanjutnya? Jawabannya adalah kita, the answer is us. Dari mana pun kita berasal, status sosial apa pun, kita punya hak dan kewajiban menyambut suara-suara parau itu untuk melindungi masyarakat adat. Merawat hutan Papua, berarti merawat masa depan peradaban manusia, termasuk segala elemen kebudayaan di dalamnya. Sebaliknya, jika merusak hutan Papua, maka hilanglah identitas masyarakat adat papua ditelan sejarah.
Bukan hanya masyarakat adat yang menerima pilu, melainkan juga kita—yang mungkin hidup tersekat jarak samudra nan luas dengan Papua—yang menanggung dampak-dampak terburuk. Tak ada lagi pohon-pohon yang menyediakan oksigen alami untuk bernapas. Tak ada lagi sumber makanan dari tanah, perairan, atau sumber daya alam yang sebelumnya berlimpah; sesuatu yang membuat hidup kita tergantung padanya. Tak ada lagi wali kelola warisan keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya terbesar di bumi, yang telah berakar di dalam nadi suku-suku Tanah Papua.
Saya jadi teringat kutipan terkenal Dr. Jane Goodall, yang mengkritik begitu maruknya manusia terhadap alam sehingga merusak keseimbangan ekosistem. “Di sinilah kita, bisa dibilang makhluk paling cerdas yang pernah hidup di planet Bumi, dengan otak yang luar biasa ini, namun kita menghancurkan satu-satunya rumah yang kita miliki.”
Maka, sebelum satu-satunya rumah masyarakat adat Papua itu hancur, lalu nestapa dan penyesalan besar itu benar-benar terjadi, saatnya membuka mata dan telinga lebar-lebar. Tutur-tutur lisan dan langkah kaki mereka perlu disambut dan digelorakan lebih luas. Butuh banyak tangan untuk bahu-membahu mempertahankan wilayah adat yang tersisa. Bukan hanya masyarakat adat yang menjaga, kita pun turut menjadi penjaga hutan dengan cara dan kemampuan kita masing-masing.
Tampaknya, menjaga hutan dan seisinya akan menjadi pekerjaan bersama seumur hidup. Pekerjaan abadi, yang menanti para penjaganya mati dan hidup berulang kali.
- Raden Putri Alpadillah Ginanjar, “Daftar Perusahaan Penggarap Proyek Food Estate Merauke Jokowi”, Tempo.co, 2024, September 25, https://www.tempo.co/ekonomi/daftar-perusahaan-penggarap-proyek-food-estate-merauke-jokowi-5855. ↩︎
- Forest Watch Indonesia, “Press Release: Indonesia Perparah Krisis Iklim Akibat Food Estate Merauke”, 2024, Desember 9, https://fwi.or.id/indonesia-perparah-krisis-iklim-akibat-food-estate/. ↩︎
- Global Forest Watch, https://www.globalforestwatch.org/. ↩︎
- Sebelas warga adat Maba Sangaji ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Maluku Utara setelah menggelar upacara adat di hutan adat Maba Sangaji, 19 Mei 2025.Upacara ini dilakukan sebagai protes kepada aktivitas penambangan nikel PT Position yang mencemari hutan adat. Mereka dianggap mengganggu ketertiban masyarakat dan dituding membawa senjata tajam, meski sebenarnya tidak terbukti. Sumber: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 15 Agustus 2025. ↩︎
- Martua Sirait dkk., “Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam era Otonomi”, 2021, Marte, https://www.cifor-icraf.org/publications/sea/Publications/files/book/BK0047-04.pdf. ↩︎
- ↩︎
- Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia, “Rekomendasi Kebijakan Instrumen Free, Prior, Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat dan atau Masyarakat Lokal yang akan Terkena Dampak dalam Aktivitas REDD+ di Indonesia”, UN-REDD Programme, Maret 2011, https://www.un-redd.org/sites/default/files/2021-09/FPIC%20Indonesian%20version%20%28419844%29.pdf. ↩︎
- Communication report and search, “Subject: Information received regarding alleged violations of the rights of Indigenous Peoples, particularly in the Merauke Regency of South Papua Province, Indonesia, linked to the implementation of National Strategic Projects (NSPs). We are also bringing these allegations to the concerned companies’ attention. Two companies — PT Global Papua Abadi and PT Murni Nusantara Mandiri (part of the Global Papua Abadi Group) — have reportedly been granted Plantation Business Permits to clear land, covering vast areas that overlap with the customary territories of these Indigenous tribes”, The Office of the High Commissioner for Human Rights, Ref.: AL IDN 1/2025, 2025, March 7, https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=29741. ↩︎
- Global Alliance of Territorial Communities,18 Juli 2025, https://www.instagram.com/reel/DMOcoj2Pj5F/. ↩︎
- Celios, 8 September 2025, https://www.instagram.com/reel/DOVJMJGgJOA/. ↩︎
- Interfaith Rainforest Initiative, “Masyarakat Adat Pelindung Hutan: Pesan bagi pemimpin agama dan masyarakat beragama”, Prakarsa Lintas Agama untuk Hutan Tropis, 2020, Januari 25, https://www.interfaithrainforest.org/s/Interfaith_IssuePrimer_IndigenousPeoples_ID.pdf. ↩︎
- Victoria Tauli-Corpuz et al., “Panduan tentang Perubahan Iklim dan Masyarakat Adat: Edisi Kedua”, Tebtebba Foundation, 2009, https://www.downtoearth-indonesia.org/sites/downtoearth-indonesia.org/files/itebcc-2nd-ed.pdf. ↩︎
- Amnesty International, “Hak Masyarakat Adat”, Amnestypedia, 2022, Agustus 11, https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/hak-masyarakat-adat/08/2022/. ↩︎
Foto sampul: Yustus Mahuze dan Paskalina Gebze, warga Malind Imo di Sanggase, Merauke, mengangkut hasil panen kelapa dari dusun untuk diolah menjadi kopra. Masyarakat adat Malind bergantung pada dusun-dusun kelapa dan sagu di pedalaman rawa dan rimba untuk kebutuhan sehari-hari.
Pada Agustus–September 2025, tim TelusuRI mengunjungi Merauke (Papua Selatan), Jayapura (Papua), serta Tambrauw dan Sorong (Papua Barat Daya) dalam ekspedisi Arah Singgah: Tanah Kehidupan. Laporan perjalanannya dapat Anda ikuti di telusuri.id/arahsinggah2025.
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.
Jika tidak dituliskan, bahkan cerita-cerita perjalanan paling dramatis sekali pun akhirnya akan hilang ditelan zaman.