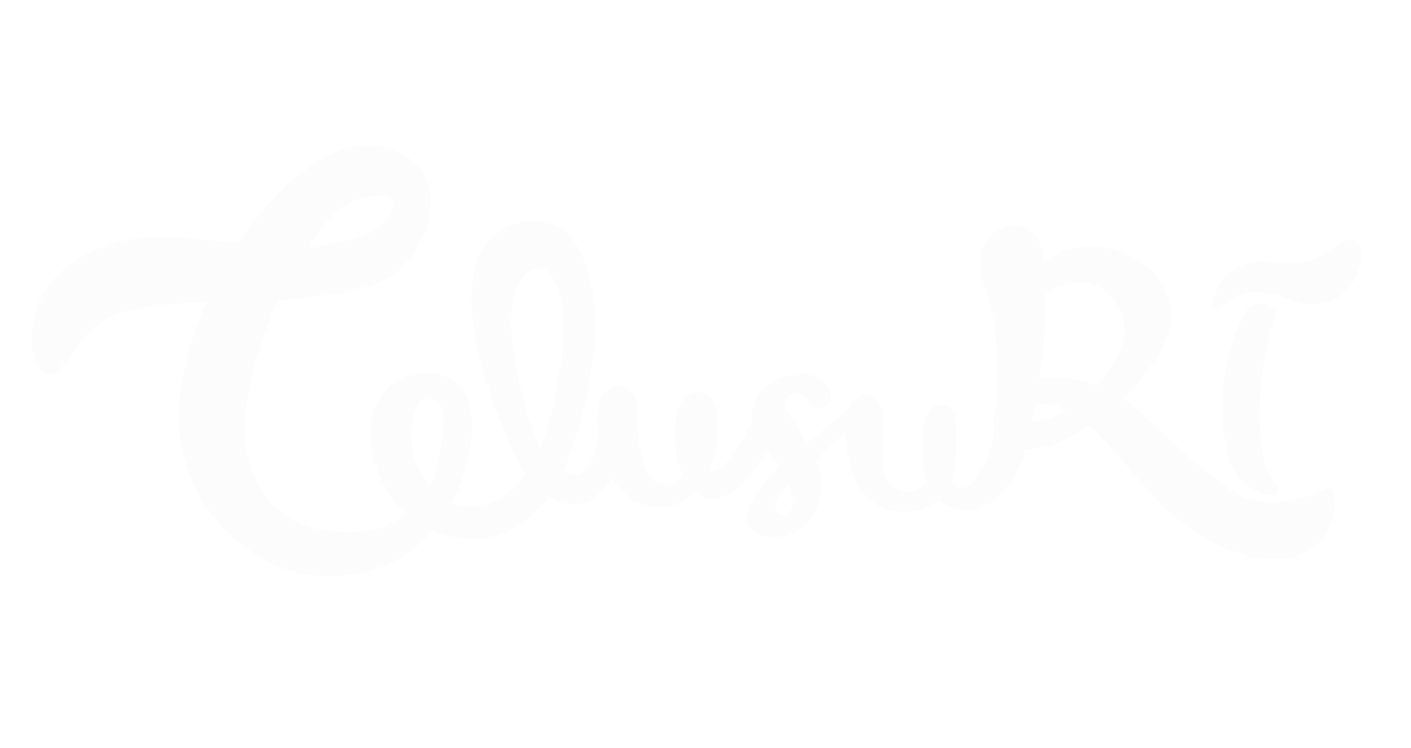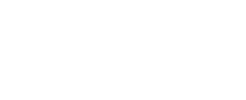Perjalanan Arah Singgah di Papua menguak bukti sahih keharmonisan hidup turun-temurun antara manusia adat dengan alam. Tugas bersama menjaga kedamaiannya dari gangguan para pengusik adalah pekerjaan keabadian—sebuah perjalanan sekali jalan.
Teks: Rifqy Faiza Rahman
Penyunting: Mauren Fitri ID
Foto: Deta Widyananda


Bentang alam Kampung Onggari, bersandar pada hutan rawa dataran rendah dan menghadap laut selatan Merauke
Dalam perjalanan pulang dari Sanggase menuju kota Merauke, kami singgah sebentar di Onggari. Jaraknya sekitar 30 kilometer dari dermaga Kali Bian, dengan waktu tempuh kira-kira satu jam kalau lancar. Onggari adalah sebuah kampung kecil di pinggiran Distrik Malind yang juga dibangun dekat pantai, serta dikelilingi rawa-rawa dan sabana mahaluas. Tipikal kampung-kampung di pesisir selatan Kabupaten Merauke.
Kami tidak lama di Onggari. Niat kami sekadar menemui perangkat kampung, lalu meminta izin mendokumentasikan lanskap kampung. Mencari bahan dokumentasi tambahan yang menggambarkan permukiman suku Malind selain Sanggase. Rupanya, kemunculan kami dengan dua mobil dan bergerombol menimbulkan kecurigaan. Sebab, kami datang tanpa membuat janji atau memberitahu siapa pun di sana.
Saat mampir ke sebuah kios kecil untuk belanja bahan kontak (pinang kering dan kapur), sejumlah pemuda merapat, ‘menginterogasi’ kami. Salah satu pemuda berperawakan gempal, dengan dahi berkerut dan mata menatap tajam, bertanya, “Kakak-kakak ini dari mana?”
Kami bilang, kami dari media. Sedikit kami ceritakan tujuan perjalanan kami ke Merauke, termasuk liputan di Sanggase, serta upaya kami mendokumentasikan potensi sumber daya alam dan suara-suara masyarakat adat Malind. Tak terkecuali menggali dampak-dampak yang timbul dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke. Berbeda dengan Sanggase, kedamaian Kampung Onggari telah terusik. Lahan adat seluas 50.772 hektare di kampung ini telah masuk dalam kepemilikan PT Borneo Citra Persada, perusahaan perkebunan tebu yang terafiliasi dengan PSN Merauke. Penetapan peta konsesi (penyerobotan lahan adat) tersebut berlangsung sepihak tanpa melibatkan masyarakat.
“Kalian bukan dari perusahaan, kan?” pemuda itu memastikan. Sebuah pertanyaan yang tampaknya timbul dari rasa takut dan trauma karena hutan adat mereka akan diambil alih negara secara tiba-tiba. Kami buru-buru mengklarifikasi, sekali lagi. Beruntung, Ramsis mencairkan suasana. Ia menyebut sejumlah nama tokoh adat Onggari yang memang ia kenal akrab. Salah satunya Stefanus Gebze, yang biasa ia panggil Bapak Fanus.
Situasi yang sempat canggung pun berubah hangat. Kedatangan kami diterima. Kami diarahkan ke kantor kepala kampung untuk menemui Bapak Fanus (58) dan Justinus Kaimo Ndiken (62), Sekretaris Kampung Onggari. Meski singkat, perbincangan dengan keduanya justru menjadi salah satu momen paling kontemplatif dalam ekspedisi kali ini.
Bagi Justinus, hutan adalah identitas budaya masyarakat Malind, termasuk di Onggari, yang menyimpan nilai-nilai luhur warisan nenek moyang. “Seandainya ada kerusakan terhadap hutan, ya, kita punya budaya ini otomatis [juga] akan hilang,” ucapnya, “[karena] tidak ada hal yang kita bisa ambil untuk melakukan ritual-ritual adat.” Untuk itulah pihaknya menolak siapa pun investor atau perusahaan datang ke Onggari.
Adapun Bapak Fanus mengajak kami merenungi lebih dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sumber hukum tertinggi; dan Pancasila, dasar ideologi negara. Menurutnya, masih banyak amanat perundang-undangan yang belum diterjemahkan dengan baik oleh penyelenggara negara. Pengelolaan sumber daya alam oleh negara belum memberi kesejahteraan kepada orang asli Papua, tak terkecuali masyarakat adat Malind di Merauke, Papua Selatan.
Ia menambahkan, sudah 80 tahun Indonesia merdeka, tetapi alam justru semakin rusak dan ketimpangan masih terjadi akibat pembangunan berkelanjutan belum merata. Ada pembangunan pun, lebih mengakomodasi kepentingan korporasi dan segelintir kelompok, tak ada keberpihakan pada masyarakat adat pemilik hak ulayat. Tanah adat dianggap tak bertuan, pemangku wilayah adat tak diajak duduk bersama. Bapak Fanus mengatakan, negara semestinya menghargai sistem adat yang berlaku, sehingga program yang dicanangkan benar-benar dibuat untuk kesejahteraan masyarakat adat. Ini senada dengan Kepala Kampung Sanggase, Yohanes Kilay, yang pada prinsipnya siap mendukung program pemerintah selama memberi ruang prioritas bagi masyarakat adat untuk berkontribusi.
Pernyataan kedua tokoh Onggari tersebut membuat kita berpikir ulang, lalu apa sebenarnya makna kemerdekaan yang dirayakan republik ini sejak 1945? Kenapa keadilan seperti tersegregasi antara wilayah barat dan timur?
* * *

Perjumpaan dengan masyarakat adat Tobati di Jayapura, serta Moi di Sorong–Tambrauw, selalu memberikan pelajaran yang sama seperti perjalanan kami di Bumi Anim Ha. Bahwa ada suara-suara yang harus didengar, ada segunung pertanyaan yang harus dijawab. Rasa takut dan trauma yang hinggap di masyarakat adat selama bertahun-tahun bukan persoalan sepele. Sebab, ini menyangkut tanah yang memberi mereka kehidupan, tempat mereka berdiri, tidur, dan menggantungkan harapan. Di relung sanubari, meski gigih menyerukan perlawanan, masyarakat adat seakan sadar tak akan mampu melawan kuasa besar—yang melakukan segala cara demi mewujudkan kehendak atas nama pembangunan nasional.
Padahal, masyarakat hukum adat sudah hidup jauh sebelum negara hadir. Sistem hukum adat dan pengelolaan tanah ulayat pun telah dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (perubahan kedua): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
Namun, kenyataannya, negara seperti sulit mengakui hak-hak dan keberadaan masyarakat hukum adat. Persoalan agraria menjadi momok menakutkan bagi masyarakat adat, tidak hanya Papua, tetapi juga daerah-daerah adat maupun kampung-kampung tradisional lainnya di Indonesia. Bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menyerukan hutan adat sebagai kawasan yang terpisah dari skema hutan negara, serta mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat, tak kunjung dipatuhi pemerintah. Keputusan MK tersebut berawal dari gugatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terhadap UU Nomor 41 Tahun 199 tentang Kehutanan—undang-undang ini memiliki pasal yang menyatakan hutan adat merupakan hutan negara.
Terlebih di Provinsi Papua—sebelum pemekaran, Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat termasuk di dalamnya—sebelumnya telah terbit UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Lima ayat dalam Pasal 43 sangat jelas memberi mandat perihal kewajiban pemerintah provinsi mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat. Kemudian ditambah Pasal 44 tentang kewajiban pemerintah provinsi melindungi hak kekayaan intelektual orang asli Papua sesuai peraturan perundang-undangan.
Akan tetapi, lagi-lagi, tampaknya rencana alih fungsi hutan adat—termasuk hutan lindung—demi pembangunan atau swasembada pangan nasional tidak mengenal kata rem. Artinya, hukum yang ada tidak bertaji. Pengabaian hukum dan amanat undang-undang ini, seperti disinggung Bapak Fanus, tentu mengundang pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Atau lebih spesifik, apa yang sedang disembunyikan negara?
Keresahan masyarakat adat Nusantara pun jadi perhatian dunia. Termasuk Global Alliance of Territorial Communities (GATC), sebuah aliansi global yang mewakili 35 juta orang dari 24 negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin—AMAN menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia dan Asia. GATC mendesak para pemangku kepentingan di setiap negara agar masyarakat adat tetap lestari dengan melindungi hak mereka atas tanah dan hutan adat yang ditinggali, keadilan mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) untuk setiap program pemerintah di lahan masyarakat adat, kemudahan akses pendanaan untuk aksi iklim, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, serta perlindungan dari kekerasan dan kriminalisasi. Conference of Parties (COP30) yang akan berlangsung di Belém do Pará, Brasil, pada 10–21 November 2025, mestinya bisa menjadi panggung yang tepat untuk memberi pengakuan dan dukungan bersama terhadap hak ulayat masyarakat adat.
* * *

Sepertinya, tak kurang-kurang masyarakat adat bersuara dan menyatakan sikap atas hak-hak yang tercerabut dari tanahnya sendiri. Begitu banyak jalan jadi pelantang, mulai dari program-program advokasi, pemberdayaan ekonomi, hingga publikasi media demi mengetuk kesadaran para pemangku kebijakan. Begitu pun sekelumit yang kami lakukan dalam perjalanan jurnalistik melalui Arah Singgah.
Ketika meninggalkan Onggari, hati kami masygul. Sampai sekarang, kisah getir orang-orang Malind-Anim di Merauke, mama-mama Enggros di Jayapura, hingga generasi Moi di Sorong dan Tambrauw, masih mengisi labirin ingatan di kepala. Apalagi dengan tekanan perubahan iklim yang berpengaruh signifikan pada kacaunya kalender musim, menggiring masyarakat adat dalam ketidakpastian hasil alam. Krisis iklim merupakan sesuatu yang mereka tidak tahu-menahu, tetapi menempatkan masyarakat adat pada kondisi rentan. Sebuah ironi besar; masyarakat adat sebagai garda terdepan penjaga hutan malah terkena imbas masifnya eksploitasi sumber daya alam terlalu berlebihan. Seiring kegelisahan yang bersemayam, ada suar optimisme yang membuncah di antara jerih payah dan deras peluh mereka dalam menjaga hutan; ada semangat dan harapan baik dari seutas senyum yang terlukis di wajah.
Di kampung-kampung yang kami kunjungi, kami selalu membawa pulang pesan yang sama, yakni legitimasi betapa krusialnya hutan adat bagi masyarakat adat Papua. Tak hanya krusial, tapi juga sakral. Sebab, hutan—dan seisinya—serupa urat nadi yang mengalir dalam tubuh orang-orang Papua. Sistem dan hukum adat menjadi pagar dalam menjaga keberlanjutan hutan agar tetap bisa diwariskan hingga anak cucu. Kini kita tidak usah lagi muluk-muluk bicara tentang status paru-paru dunia atau bangsa besar dengan nasionalisme populis. Saatnya lebih membumi dan mau melihat lebih dalam, karena kabar tentang hutan terakhir itu bukan bualan.
Rasa-rasanya, tak ada jalan lagi selain terus bersuara. Saling bergandeng tangan dan berkolaborasi antarpemangku kepentingan dan masyarakat adat lintas generasi. Tak ada upaya terbaik selain terus-menerus mengetuk nurani negara, mendoakan lewat pintu langit, dan memohon satu pinta yang sederhana: masyarakat adat hanya perlu diberi kebebasan mengelola tanah dan hutan adatnya sendiri. Mungkin, inilah makna kemerdekaan yang sesungguhnya, terutama bagi saudara-saudara kita di Papua.
Mari bertanya sekali lagi pada diri sendiri: seperti apa kacamata kita melihat Papua? Kalau kami boleh saran, jangan memandang Papua sebelah mata, apalagi menutup kedua mata dan telinga. Seperti kata Bapak Fanus, jangan lupakan sila ketiga Pancasila saat melihat Papua.
Foto sampul: Seorang mama berjalan di lepas pantai Kampung Sanggase, Merauke, untuk memasang jaring ikan di laut yang sedang surut.
Pada Agustus–September 2025, tim TelusuRI mengunjungi Merauke (Papua Selatan), Jayapura (Papua), serta Tambrauw dan Sorong (Papua Barat Daya) dalam ekspedisi Arah Singgah: Tanah Kehidupan. Laporan perjalanannya dapat Anda ikuti di telusuri.id/arahsinggah2025.
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.
Jika tidak dituliskan, bahkan cerita-cerita perjalanan paling dramatis sekali pun akhirnya akan hilang ditelan zaman.