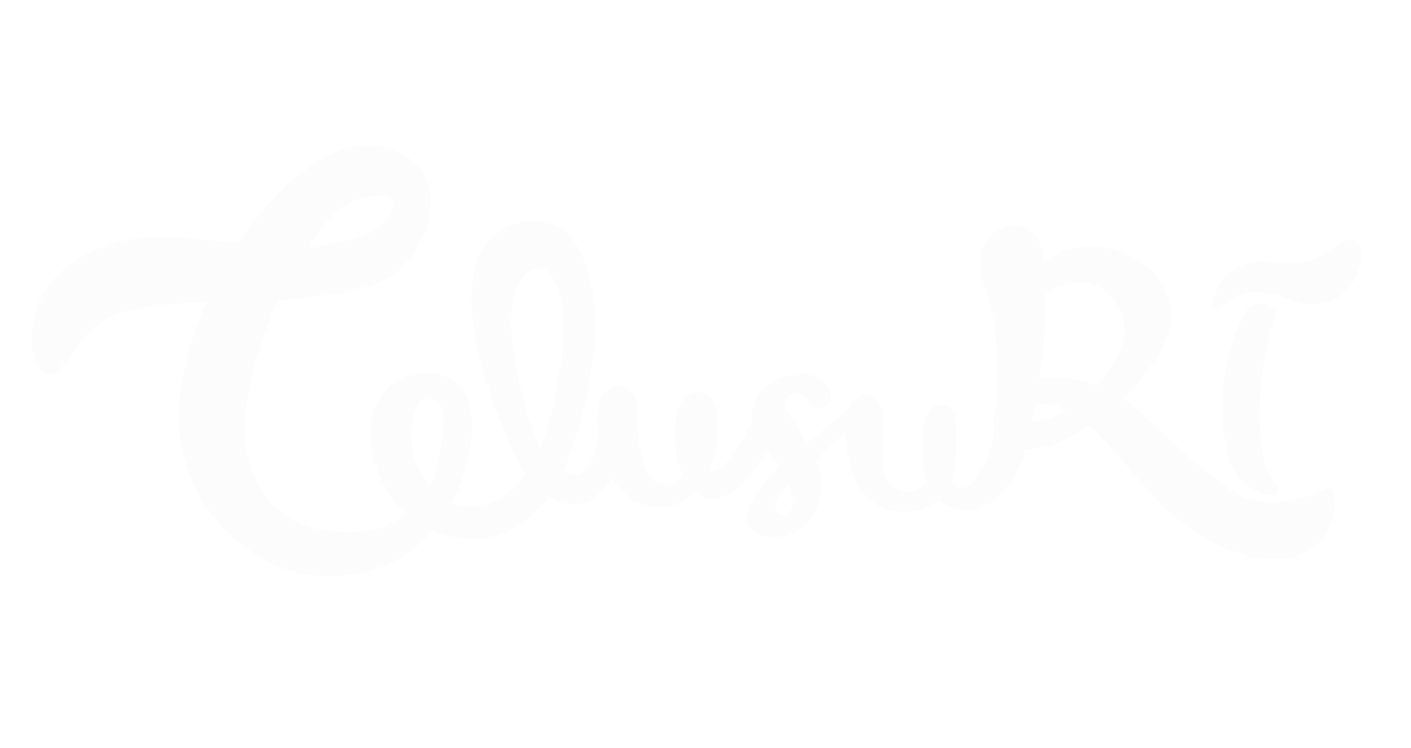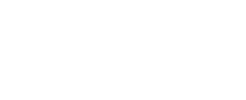Wacana membuka 20 juta hektare lahan hutan yang keluar dari lisan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni seperti tidak menunjukkan marwah kementerian yang mengurusi hutan. Sekalipun itu untuk dalih mendukung proyek ambisius food estate, memperkuat cadangan pangan, energi, dan air. Hal ini diperparah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyamakan perkebunan sawit dengan hutan, yang menganggap deforestasi bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan.
Riset Satya Bumi menyebut daya dukung tampung lingkungan hidup untuk perkebunan sawit di Indonesia sudah mendekati ambang batas. Angka ambang batas atas (cap) sawit di Indonesia adalah 18,15 juta hektare, dengan daerah cakupan terluas ada di Pulau Sumatra dan Kalimantan, yang luasannya sudah melampaui kebutuhan (surplus). Sementara menurut data MapBiomas, luas perkebunan sawit saat ini sudah mencapai 17,7 juta hektare. Daripada memaksakan ekspansi sawit, mestinya pemerintah memerhatikan tata kelola yang lebih baik.
Arah kebijakan yang tidak memiliki sensitivitas pada alam tersebut berpeluang menimbulkan bahaya berupa bencana ekologis, mengancam ketahanan dan diversifikasi pangan lokal, serta merebut ruang hidup masyarakat adat. Belum lagi pemusnahan habitat satwa-satwa endemis yang populasinya sudah makin kritis.
Padahal, keanekaragaman hayati dan masyarakat yang majemuk justru menjadi nilai plus Indonesia. Masyarakat atau komunitas adat lokal, yang telah hidup berharmoni dengan hutan secara turun-temurun, terbukti mampu melestarikan tegakan hutan—baik itu hutan tropis di daratan maupun hutan mangrove di kawasan perairan—sekaligus menjaga ekosistem kehidupan di dalamnya.

Deforestasi untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh PT Permata Nusa Mandiri (PNM) di wilayah adat Namblong, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. PT PNM mendapatkan izin lokasi seluas 32.000 hektare dari Bupati Jayapura Mathius Awoitauw pada 2011. Kemudian izin konsesi kawasan hutan dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan lewat SK.680/MENHUT-II/2014 tanggal 13 Agustus 2014 dengan luas wilayah 16.182,48 hektare. Kawasan seluas itu telah mencaplok lebih dari separuh wilayah adat suku Namblong seluas 53.000 hektare yang membentang di Lembah Grime. Izin konsesi tersebut kemudian dicabut oleh Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar lewat SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022. Namun, aktivitas PT PNM masih berjalan. Pembabatan hutan terus berlangsung dan ratusan hektare lahan berhutan milik sejumlah marga telah rata dengan tanah. Meski belum ada kegiatan penanaman, tetapi perusahaan yang tidak memiliki kantor tetap itu telah menyiapkan bibit-bibit sawit siap tanam. Keberadaan industri ekstraktif ini sedang “dilawan” oleh masyarakat lokal dengan beragam cara, di antaranya pengelolaan sumber daya alam oleh Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA)/Foto oleh Deta Widyananda
Inilah cara kreatif “menjual” hutan tanpa harus membabat hutan
Pengalaman dari perjalanan ekspedisi Arah Singgah oleh TelusuRI di Sumatra, Kalimantan, dan Papua dalam dua tahun terakhir telah memberikan sudut pandang nyata soal harmoni manusia dan alam, serta tantangan internal-eksternal yang bisa mengancam eksistensinya. TelusuRI ingin mengajak pemerintah maupun para pemangku kepentingan dengan kesadaran penuh untuk bercermin dari jalan hidup para local champion dan masyarakat adat tersebut. Mereka cerdas dan bijak dalam memanfaatkan hasil hutan dan mendapat keuntungan ekonomi, tetapi tanpa harus merusak hutan.
Inilah cara-cara mereka, yang (seharusnya) bisa menjadi pedoman nyata pemerintah agar lebih kreatif dan bijaksana dalam membuat kebijakan ramah lingkungan.
1. Ekowisata Tangkahan, Langkat, Sumatra Utara
Sepanjang 1995–2000, sekitar 400 hektare hutan di Tangkahan dibabat habis oleh pembalakan liar. Masyarakat dan cukong bekerja sama dalam bisnis kotor pada balok-balok kayu damar senilai jutaan rupiah. Padahal, kampung di pinggiran Sungai Sei Batang Serangan ini berbatasan langsung dengan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Satu dari lima taman nasional tertua di Indonesia, satu-satunya tempat empat mamalia besar endemis berada dalam satu ‘rumah’: harimau, gajah, orang utan, dan badak.
Pada 2001, sejumlah pembalak liar mulai menemukan kesadaran dan berubah haluan, yang kemudian membentuk komunitas pemuda Tangkahan Simalem Ranger tanggal 22 April. Salah satu inisiatornya adalah Rutkita Sembiring. Tugas utamanya antara lain menghentikan illegal logging, juga mengajak rekan-rekan pembalak untuk bertobat dan mencari jalan hidup yang lebih baik.
Inisiatif tersebut lalu berkembang melahirkan Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT). Terinspirasi dari ekowisata Bukit Lawang, yang telah membuktikan upaya “menjual” hutan tidak dengan menebang, tetapi melalui ekowisata. LPT menggerakan ekonomi alternatif dan merestorasi alam melalui ekowisata berkelanjutan. Sampai sekarang, LPT bekerja sama dengan Conservation Rescue Unit (CRU) dan TNGL, yang bertanggung jawab menampung gajah-gajah sumatra di Pusat Latihan Satwa Khusus (PLSK) Tangkahan. Gajah-gajah tersebut umumnya dievakuasi dari konflik manusia-satwa di Aceh-Sumatra Utara. Di PLSK, sejumlah induk dan anak gajah dirawat oleh mahout (pawang gajah), yang juga bertugas memberi edukasi konservasi kepada para tamu LPT, baik domestik maupun mancanegara.
2. Kelompok Tani Hutan Konservasi, Langkat, Sumatra Utara
Tidak hanya di Tangkahan. Selama lebih dari tiga dekade, riwayat perusakan kawasan penyangga TNGL juga merambah 16.000 hektare hutan di daerah pedalaman Besitang. Alih fungsi lahan yang masif mengubah area hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan karet. Mafia tanah pun merajalela, konflik horizontal antara masyarakat dengan pemangku kawasan konservasi tak terelakkan.
Pada 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk program Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) sebagai upaya memulihkan kawasan. Terdapat 16 KTHK yang masing-masing beranggotakan petani mitra sekitar dengan cakupan lahan mencapai hampir 1.000 hektare. Setiap petani diberi lahan garapan seluas dua hektare untuk menanam komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti durian, jengkol, cempedak, aren, petai, dan rambutan. Tanaman-tanaman HHBK ini disebut juga Multi-Purpose Tree Species (MPTS). Program KTHK membuat masyarakat anggota kemitraan tersebut memiliki potensi ekonomi alternatif sekaligus merestorasi kawasan hutan, sehingga tidak lagi bergantung pada perambahan, pembalakan, maupun sawit.
Salah satu kelompok yang masih aktif sampai sekarang adalah KTHK Sejahtera pimpinan Hatuaon Pasaribu. Mantan guru yang getol menggalakkan semangat konservasi dan ekonomi restoratif di tengah keterbatasan dan masih adanya ancaman mafia tanah. Sejauh ini, Pasaribu dan para anggota maupun sejumlah kelompok lainnya telah membuktikan hasil positif dari KTHK. Mereka hanya perlu dukungan pemerintah untuk menjamin keamanan pekerjaaan di lapangan, serta menjangkau akses pasar dan sarana-prasarana budidaya lebih luas lagi.
3. Hutan Mangrove Teluk Pambang, Bengkalis, Riau
Bertahun-tahun, setidaknya sampai 2002, Desa Teluk Pambang, Kabupaten Bengkalis rutin dihajar rob setengah meter setiap Oktober–Desember. Permukiman, rumah penduduk, dan lahan pertanian terendam air asin. Produktivitas karet menurun. Air kelapa tidak lagi segar. Hutan mangrove menyusut akibat perambahan dan pembalakan liar oleh panglong, perusahaan penebangan kayu setempat. Data mencatat, terjadi penurunan luas hutan mangrove sebanyak 5,25 persen di Pulau Bengkalis dalam kurun waktu 1992–2002. Dari sekitar 8.182,08 hektare pada tahun 1992 menjadi 6.115,95 hektare pada tahun 2002.
Situasi itu menggerakkan hati Samsul Bahri, seorang nelayan kecil berdarah Jawa untuk menyelamatkan ekosistem mangrove. Pada 2002, ia mulai membudidayakan dan menanam bibit-bibit mangrove di hutan rawa belakang rumahnya. Dua tahun kemudian, Samsul membentuk dan mengetuai Kelompok Pengelola Mangrove (KPM) Belukap, yang diperkuat surat keputusan Bupati Bengkalis saat itu. Selain Belukap, juga ada KPM Perepat yang dipimpin M. Ali B. Dua kelompok ini merupakan pelopor pengelolaan mangrove dengan skema perhutanan sosial.
Lambat laun, 40 hektare hutan mangrove berhasil direstorasi. Pohon tertingginya bisa mencapai 20 meter. Banjir rob sudah berkurang signifikan. Kerja kerasnya mendapat atensi pemerintah dan sejumlah lembaga nirlaba internasional, yang kemudian memberi bantuan pendanaan kegiatan dan advokasi sampai terbentuknya legalitas Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Teluk Pambang. Kini, bukan hanya konservasi semata, Samsul dan masyarakat Teluk Pambang menatap masa depan ekonomi restoratif melalui ekowisata dan perdagangan karbon dari 1.001,9 hektare ekosistem mangrove yang telah merimbun.
4. Kampung Merabu, Berau, Kalimantan Timur
Masyarakat suku Dayak Lebo di Kampung Merabu adalah jagawana ekosistem karst Sangkulirang-Mangkalihat. Ekosistem karst terbesar di Kalimantan. Meski dikepung sawit yang tumbuh menjamur di kampung tetangga, orang-orang Merabu masih gigih mempertahankan hutan yang menjadi sumber penghidupan utama mereka. Sebab, Dayak Lebo lama dikenal sebagai suku pemburu dan peramu obat-obatan tradisional. Madu hutan alami juga jadi salah satu produk unggulan. Sejak 2014, ekowisata menjadi sumber ekonomi alternatif yang dikelola berbasis masyarakat dan berkelanjutan.
Perbukitan karst Sangkulirang-Mangkalihat benar-benar jadi berkah untuk Merabu. Selain menyimpan jejak prasejarah lewat gua-gua purba, kawasan ini juga memiliki bentang alam yang menjadi daya tarik wisata, seperti Danau Nyadeng dan Puncak Ketepu. Pengelolaan ekowisata berada di tangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam). Sudah tak terhitung tamu yang datang untuk berwisata di Merabu, terutama mancanegara.
Program menarik yang memanfaatkan nilai hutan Merabu adalah adopsi pohon. Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Kerima Puri. selaku penanggung jawab program, telah menghimpun hampir 300-an pohon yang diadopsi oleh banyak pihak, mulai dari turis biasa, lembaga nirlaba, hingga instansi pemerintahan. Rata-rata jenis pohon yang diaopsi antara lain damar, meranti merah, dan merawan. Nama yang disebut terakhir diadopsi sejak 2016 oleh Vidar Helgesen, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia periode 2015–2018. Dana hasil adopsi pohon tersebut kemudian dialokasikan untuk biaya sekolah anak-anak Merabu dan biaya sosial warga kampung yang kurang mampu.
5. Ekowisata Malagufuk, Sorong, Papua Barat Daya
Suku Moi merupakan komunitas adat terbesar di Kabupaten Sorong, gerbang barat Tanah Papua. Masyarakat Moi dikenal dengan tradisi egek, yang membatasi atau melarang kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu di hutan maupun kawasan pesisir, agar kelestarian alam dan keanekaragaman hayatinya terjaga. Meski sejumlah daerah di Sorong sudah beralih fungsi menjadi area pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit, ada satu titik yang masih keras mempertahankan tanah ulayatnya, yaitu Malaumkarta Raya.
Di antara lima kampung, hanya Malagufuk yang menempati pedalaman rimba Hutan Klasow. Sisanya berada di pesisir. Jalan kaki sejauh 3,5 kilometer di atas jembatan kayu adalah satu-satunya cara mencapai Kampung Malagufuk. Keterisolasian ini justru jadi nilai lebih Malagufuk, yang kemudian mendunia karena daya tarik ekowisata pengamatan burung (birdwatching). Terdapat lima spesies cenderawasih yang bisa ditemukan di Malagufuk, yaitu cenderawasih kuning-kecil, cenderawasih kuning-besar, cenderawasih raja, cenderawasih mati kawat, dan toowa cemerlang. Tidak hanya cenderawasih, burung-burung endemis lainnya juga ada, antara lain julang papua, mambruk, dan kasuari. Satwa unik seperti nokdiak atau landak semut dan kanguru tanah juga bisa ditemukan di sini.
Perputaran ekonomi restoratif melalui ekowisata dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat gelek (marga) Kalami dan Magablo di Malagufuk. Mulai dari pemandu, pengelola homestay, porter, hingga juru masak terlibat di dalamnya. Masyarakat Malagufuk mampu melihat nilai lebih dari hutan mereka tanpa harus merusak hutan. Keberagaman potensi burung dan satwa di Malagufuk mengundang turis pegiat birdwatching lintas negara. Di Papua, Malagufuk kini jadi destinasi pengamatan burung paling populer selain Raja Ampat, Pegunungan Arfak, dan Jayapura.
6. BUMMA Yombe Namblong Nggua, Jayapura, Papua
Inisiatif luar biasa dalam mewujudkan ekonomi restoratif berbasis masyarakat lahir di Kabupaten Jayapura. Tepatnya di Lembah Grime, kawasan adat suku Namblong seluas 53.000 hektare yang menempati tiga distrik: Nimbokrang, Nimboran, dan Namblong. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Mitra BUMMA, dan Samdhana Institute berkolaborasi dengan masyarakat adat Namblong membentuk Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA) Yombe Namblong Nggua pada 12 Oktober 2022. Per Oktober 2024 lalu, BUMMA resmi berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), dengan 44 Iram (pemuka marga) sebagai pemegang saham.
BUMMA Yombe Namblong Nggua merecik harapan ekonomi kerakyatan di tengah tekanan deforestasi akibat alih fungsi lahan perusahaan kelapa sawit PT Permata Nusa Mandiri (PNM), yang hak konsesinya sudah dibatalkan pemerintah sejak 2022 lalu. Langkah progresif tersebut pertama di Papua, seiring penetapan pengakuan ribuan hektare hutan adat Namblong oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain Jayapura, BUMMA juga dibentuk di Mare, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.
Pendirian BUMMA muncul atas keinginan mengelola sumber daya alam berbasis masyarakat adat secara berkelanjutan. Setidaknya terdapat tiga sektor unggulan yang dikerjakan, yaitu budi daya vanili, ekowisata, dan perdagangan karbon melalui restorasi hutan—termasuk memulai penanaman sagu di lahan-lahan terdampak konsesi sawit.

Tunggu apa lagi, Pak Presiden dan Pak Menteri?
Contoh riil di akar rumput tersebut mestinya sudah lebih dari cukup sebagai bukti agar pemerintah membuka mata lebar-lebar. Pemahaman sederhana soal keseimbangan ekosistem mestinya juga sudah didapat jika memang pernah melewati masa pendidikan sekolah dasar. Bahwa jika memutus satu rantai dalam ekosistem, maka akan menghapus entitas kehidupan yang bergantung padanya. Sebagaimana menghilangkan pohon-pohon pembentuk ekosistem pemberian Tuhan. Tidak hanya akan memusnahkan habitat keanekaragaman hayati, tetapi juga identitas kebudayaan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan.
Dampak keserakahan dan ambisi akibat menjadikan lahan hutan sebagai ladang bisnis telah nyata merusak segala lini kehidupan yang menjadi hak rakyat. Suku-suku adat terusir dari tanahnya sendiri, satwa-satwa endemis mengais-ngais makanan di tempat yang tidak semestinya—karena hutannya sudah hilang. Belum lagi konflik antara manusia dan satwa, yang sudah amat sering terjadi hingga soal bencana ekologis yang akan timbul. Banjir bandang, sungai meluap, dan tanah longsor merenggut banyak hal, yang seringkali hujan lebat maupun cuaca ekstrem menjadi sasaran tuduhan pemerintah, yang tutup mata pada masalah sebenarnya: hilangnya pohon-pohon di hutan sebagai penyerap dan penahan air.
Ayolah, Pak Presiden dan Pak Menteri. Masyarakat adat dan komunitas lokal lebih memahami hutan mereka. Mereka hanya perlu pengakuan legal dan pendampingan, agar hutan alami yang menghidupi mereka terjaga sampai anak cucu. Sebab, jika masih tutup mata, slogan Indonesia sebagai paru-paru dunia sejatinya sudah menjadi sekadar romantisme belaka. Setop mengoceh soal Indonesia yang kaya sumber daya alam, jika kebijakan-kebijakan di tingkat elite tidak berpihak pada alam itu sendiri.
Foto sampul oleh Deta Widyananda
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.
Seorang penulis perjalanan, pemerhati ekowisata, dan Content Strategist di TelusuRI. Penikmat kopi. Gemar mendaki gunung demi gemintang, matahari terbit dan tenggelam.