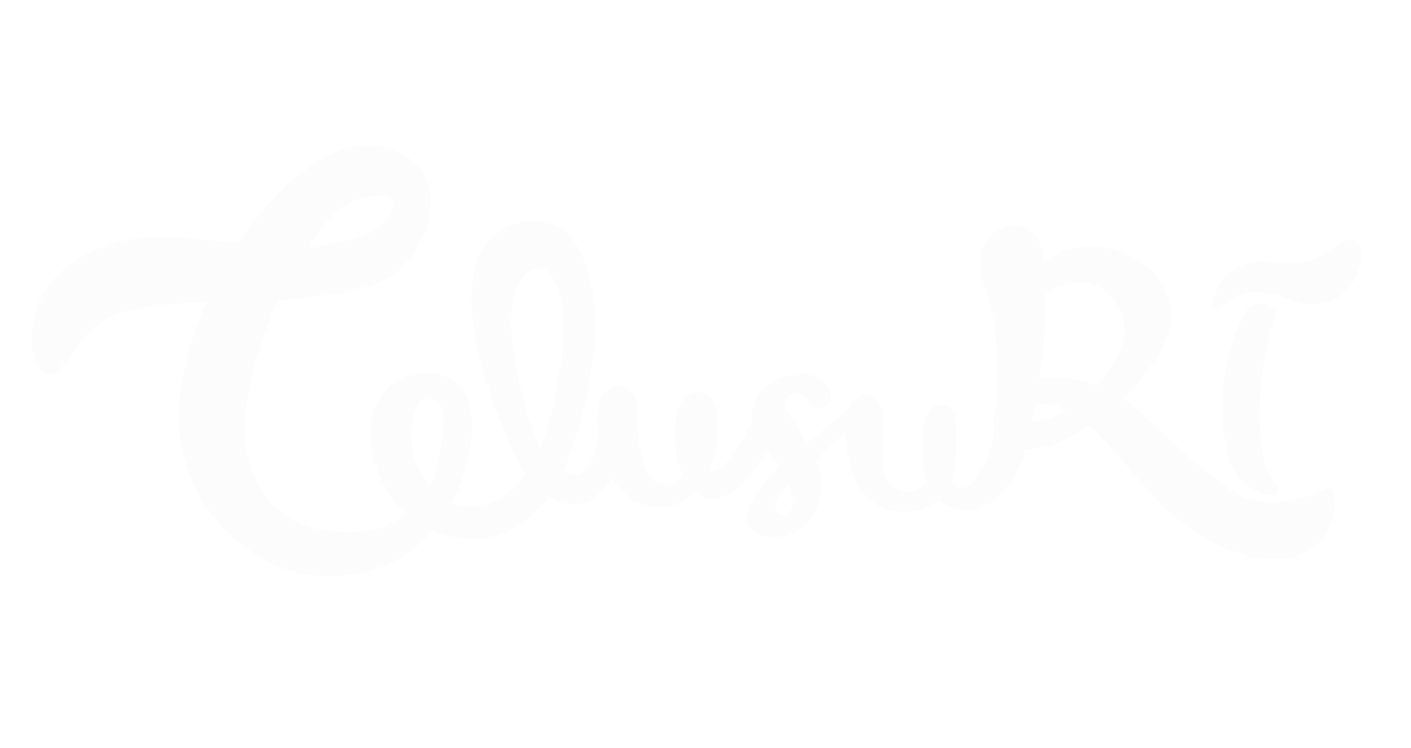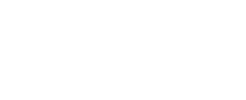Meski belum terdampak langsung, bayang-bayang proyek food estate telah menyelimuti Kampung Sanggase. Fokus pemetaan wilayah adat sebagai mitigasi.
Teks: Rifqy Faiza Rahman
Penyunting: Mauren Fitri ID
Foto: Deta Widyananda

Dahulu, Sanggase punya rekam jejak kelam di seantero Distrik Okaba dan umumnya pesisir selatan Kabupaten Merauke. Stigma negatif masa lalu Sanggase diakui oleh warga kampung sendiri. Terutama generasi tua. Istilah orang kampung, Sanggase dulu ‘merah’. Riwayat kekerasan, perang suku, bahkan pengaruh gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pun sempat menyuruk ke pemikiran masyarakat. Kampung-kampung tetangga harus pikir-pikir jika ingin berurusan dengan kampung paling timur Distrik Okaba itu.
“Sanggase dulu keras. Sangat keras,” kenang Yohanes Kilay (56), kepala kampung yang sudah menjabat dua periode sejak 2018.
Suku Malind terkenal sebagai komunitas adat terbesar di Bumi Anim Ha—sebutan lain Merauke. Kampung Sanggase yang berpenghuni hampir 700 jiwa merupakan rumah bagi subsuku Imo, satu dari empat golongan besar Malind (Mayo, Sosom, dan Esam), dengan Gebze dan Mahuze sebagai marga paling dominan. Untuk itu mereka biasa disebut sebagai masyarakat atau suku Malind Imo Sanggase. Mereka biasa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggarap dusun sagu dan kelapa, berburu binatang (rusa, saham atau kanguru tanah, babi hutan), dan menangkap ikan.
Di balik cara hidup yang tampak umum, karakter yang keras dan relatif tertutup dengan dunia luar sempat menjadi tebing terjal terhadap setiap rencana pembangunan, baik itu pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terlebih Yohanes merupakan pria berdarah Ambon, termasuk dalam kelompok orang yang dianggap ‘rambut lurus’ dan minoritas. Dahulu suaranya sempat tidak digubris apalagi dipercaya oleh masyarakat Sanggase, yang 98 persen merupakan suku Malind, orang asli Papua.
“Untuk membangun masyarakat lokal di sini, kita tidak bisa pakai hitung-hitungan. Kita harus bangun dengan hati,” ungkap suami Siti Rohana, guru SD asli Banyuwangi yang berdinas di SD YPKK Sanggase.
Tantangan sebagai kepala kampung berusaha ia hadapi satu per satu. Termasuk keterbatasan akses transportasi, lokasi yang sangat jauh dari ibu kota kabupaten, dan faktor keamanan. Beruntung, watak keras dan mental berani mati demi kemajuan kampung membantunya bertahan dan bertahap merebut simpati para tetua adat dan masyarakat. Perhatian lebih pada pendidikan dasar dan menengah, serta harmoni agama dan adat, membawa Sanggase ke titik seperti sekarang.
Usai berdamai dengan masa lalu, Yohanes dan masyarakat Imo Sanggase kembali siaga, karena kini bahaya lain mengintai di depan mata. Sebuah proyek lumbung pangan (food estate) dari pemerintah pusat sudah menginjakkan kaki di sejumlah distrik tetangga di Merauke. Alat-alat berat telah membabat pohon dan menguruk rawa di kawasan-kawasan hutan adat, sumber penghidupan banyak masyarakat adat yang kerap dianggap tanah tak bertuan.

Tentang PSN Merauke dan yang semestinya dilakukan
Merauke telah lama lekat dengan program food estate, sebuah proyek skala jumbo yang dipandang sebagai solusi mengatasi krisis pangan dan ketahanan energi nasional. Pada 2010, di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah meluncurkan program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Luas areal proyek tersebut 1.282.833 hektare1, merenggut lebih dari 25 persen wilayah administrasi Kabupaten Merauke yang total luasnya mencapai 4.679.163 hektare2. Namun, seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah, MIFEE dianggap gagal karena keterbatasan dana dan daya dukung lahan yang rendah.3 Deforestasi besar-besaran yang terjadi pun berimbas pada hilangnya ruang hidup masyarakat adat, konflik horizontal, dan persoalan degradasi kualitas lingkungan.4
Berselang satu dekade kemudian, Presiden ke-7 Joko Widodo melanjutkan konsep MIFEE dengan kemasan baru: Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Pangan & Energi di Kabupaten Merauke—selanjutnya disebut PSN Merauke. Pemerintah berambisi menyongsong swasembada padi dan gula di tahun 2027–2028, termasuk di dalamnya rencana penyediaan bioetanol sebagai upaya transisi energi ke bahan bakar nabati.5 Dalih krisis pangan akibat perubahan iklim, gelombang panas dan kering yang panjang, kedaulatan dan ketahanan pangan, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi, mendasari megaproyek triliunan berbasis korporasi tersebut. Keputusan ini menggemparkan publik, terutama masyarakat adat di Merauke.
Dalam jangka panjang, PSN Merauke berencana menggarap lahan hutan seluas 2,29 juta hektare—kira-kira 70 kali luas Jakarta—untuk cetak sawah dan perkebunan tebu baru di atas ekosistem hutan dan rawa gambut, serta pabrik gula dan bioetanol.6 Untuk tahap awal, pada 2023–2024 lalu pemerintah daerah dan pusat telah menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Surat Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan kepada 10 (sepuluh) perusahaan perkebunan tebu, pabrik gula, dan bioetanol, dengan lahan seluas 541.094,37 hektare yang tersebar di Distrik Tanah Miring, Animha, Jagebob, Eligobel, Sota, Ulilin, Malind, dan Kurik.

Pada peta sebaran konsesi PSN Merauke yang dirilis Pusaka Bentala Rakyat, untuk tahap awal Distrik Okaba, termasuk Kampung Sanggase dan delapan kampung lain (lingkaran merah) memang tidak—atau belum—dinyatakan terdampak langsung oleh proyek ambisius ini. Namun, menilik rencana Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) yang berwarna kuning, Distrik Okaba dikelompokkan ke dalam Klaster 4 bersama Distrik Tubang dan Ngguti, dengan ketersediaan lahan 352.00 hektare. Dari jumlah ini, total 241.000 hektare di antaranya berstatus HPK (Hutan Produksi yang dapat Dikonversi). Artinya, Sanggase dan kampung-kampung se-Distrik Okaba kelak bisa bernasib serupa dengan distrik-distrik tetangga.
Situasi yang terjadi sebagai dampak PSN Merauke sesungguhnya tidak diharapkan terjadi di Kampung Sanggase. Masyarakat khawatir hutan adat Imo Sanggase akan ikut-ikutan rusak. Dari keterangan Yohanes, pada dasarnya Sanggase tidak menolak program pemerintah, tetapi harus memperhatikan dua catatan khusus: hanya untuk komoditas padi rawa dan masyarakat sendiri yang mengelola. Jika program dikelola melalui perusahaan, atau bahkan timbul wacana pembukaan lahan untuk kelapa sawit maupun komoditas nonpadi, Yohanes dan tokoh masyarakat Sanggase menolak.
Kristianus Nasemhe (54), ketua adat umum Imo Sanggase, menegaskan akan melindungi batas-batas hak ulayat masyarakat dan tidak membiarkan perusahaan masuk kampung. Pernyataannya diperkuat Siprianus Heri Gebze (48), tokoh adat dan ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Sanggase, yang meminta negara dan perusahaan menghargai ketua adat, serta melarang keras segala program yang merusak alam dan hutan adat Imo Sanggase. Sebab, dari alamlah masyarakat bisa mencari sumber makanan, obat-obatan, atribut-atribut adat, sampai dengan harta untuk mas kawin. “Itu yang kita harus jaga. Tidak bisa perusahaan masuk (untuk) merusak tanah Malind, tidak bisa,” ujarnya.

Pemetaan wilayah adat dan tantangan pengarsipan budaya
Menurut Maryo Saputra Sanuddin, Koordinator Yayasan EcoNusa Regional Papua, pemetaan wilayah adat adalah upaya paling dasar untuk menjamin keberadaan hutan adat masyarakat Malind di Kampung Sanggase. Program ini mempertegas batas-batas wilayah adat, marga, dan administratif kampung, serta memperkuat hak dan legitimasi masyarakat Sanggase atas tanah yang menjadi sumber penghidupan sehari-hari.
Pemetaan wilayah adat menjadi upaya dini untuk mengantisipasi Proyek Strategis Nasional (PSN) itu. Lebih dari itu, pemetaan akan mendorong pengakuan hukum yang kuat dan mengikat terhadap wilayah adat sebagai bagian dari identitas budaya dan warisan leluhur. Pada 6–13 Februari 2025, EcoNusa bersama masyarakat Sanggase melakukan pemetaan partisipatif dan menghasilkan usulan batas wilayah seluas 49.203 hektare. Kegiatan tersebut mencakup sosialisasi program dan pemetaan indikatif, pelatihan GPS bagi pemuda kampung supaya kelak mampu merekam titik koordinat secara mandiri, serta menandai batas wilayah marga dan antarkampung, yang kemudian akan diverifikasi melalui musyawarah adat untuk memastikan keabsahannya.7
Tidak hanya pemetaan wilayah, EcoNusa juga melakukan pemetaan atau pengarsipan tradisi-tradisi suku Malind di Sanggase. Pendokumentasian segala bentuk ritus hingga aksesoris adat, yang melekat sejak kelahiran sampai kematian manusia, juga tidak kalah pentingnya mengingat pengetahuan-pengetahuan leluhur tersebut diwariskan secara tutur, bukan lewat tulisan.
Moses Ramsis Boi (27), program associate EcoNusa Merauke yang bertanggung jawab pada program pendampingan di Sanggase, mengaku menghadapi tantangan tersendiri saat mendokumentasikan budaya dan hal-hal lain yang melekat pada adat dan kehidupan suku Malind. Sebab, umumnya suku Malind relatif tertutup kepada orang-orang atau pihak luar. Terkadang, untuk menceritakan sebuah tempat keramat atau prosesi adat, mereka hanya mengungkap bagian permukaan atau informasi umum saja, tidak serta-merta menunjukkan lokasi atau bentuknya secara langsung karena bersifat sakral atau rahasia.
Di satu sisi, Ramsis juga mengalami kesulitan lantaran segala pengetahuan leluhur hanya diwariskan lewat tutur lisan dan ingatan, bukan catatan tertulis atau rekam visual. Mengutip pernyataan tetua adat, Ramsis menamsilkan, “Generasi muda mempelajari lewat ingatan di kepala, lalu menyimpannya di kaki.” Ajaibnya, anak-anak muda tahu dan mengerti lokasi-lokasi keramat, nama-nama tempat di kampung dan hutan, hanya mengendalikan ingatan tanpa catatan tertulis, bahkan tahu hanya dengan menunjuk titik di peta wilayah adat.
Demi hasil maksimal, alumnus Fakultas Hukum Universitas Musamus itu harus melalui proses panjang, seperti sosialisasi, kunjungan berulang, duduk adat, hingga pendekatan personal untuk mengumpulkan data-data penting. Pria asli Bajawa, Flores itu perlu menumbuhkan ikatan kepercayaan agar masyarakat Sanggase mau menyampaikan informasi adat tersebut.

Mempertahankan wilayah adat Malind Imo Sanggase adalah harga mati.
Dalam dokumen Profil Masyarakat Hukum Adat Suku Malind Imo Sanggase (2025) yang kami terima dari EcoNusa, suku Imo Sanggase setidaknya memiliki enam elemen adat: (1) wilayah kelola adat; (2) hukum adat; (3) kelembagaan dan sistem pemerintahan adat; (4) harta dan kekayaan adat (rumah, perahu, dayung, senjata tradisional, alat musik, tarian dan nyanyian, atribut adat); (5) sistem kepercayaan (ritual dan doa adat); (6) sumber pangan dan obat-obatan tradisional.
Seperti umumnya suku-suku di Papua, masyarakat Malind di Sanggase juga menerapkan pembagian zonasi adat berdasarkan peruntukannya. Tata ruang tersebut mencakup areal dusun sagu sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan, tempat-tempat keramat yang berhubungan dengan leluhur, dan wilayah pemanfaatan sumber daya alam secara tradisional (pesisir pantai, rawa, dan hutan).
Kentalnya tradisi Malind Imo Sanggase tercermin pada dua ritual adat yang sempat kami lihat di kampung. Pertama, upacara penerapan denda adat kepada seorang warga yang berselisih paham kepada tetangganya. Di sanggar, sesuai kesepakatan tetua dan warga, orang tersebut harus membayar denda berupa pemberian tanaman wati.
Wati atau Piper methysticum Forst. f. (Piperaceae) merupakan tumbuhan yang memabukkan dan bersifat narkotik, yang sejak lama digunakan sebagai dalam acara-acara atau ritual adat. Tumbuhan ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dapat dijadikan sebagai mas kawin dan denda adat.8 Jika dirupiahkan, nilai setangkai tanaman wati setara dengan uang 2,5–3 juta rupiah. Secara tradisional, masyarakat Sanggase biasa mengonsumsi wati dengan cara memeras sari-sarinya, atau mengunyah langsung lalu dicampur dengan air.
Ritual adat kedua yang kami saksikan adalah seremonial pelepasan tanah adat (toki babi atau upacara bunuh babi). Dalam tradisi suku Malind Imo Sanggase, hak milik dan kelola tanah adat bisa didapatkan oleh orang-orang di luar marga maupun yang tidak berhubungan dengan marga. Namun, dengan satu catatan, mereka sudah lama memiliki hubungan kekerabatan dengan masyarakat Sanggase. Pada upacara ini, selain babi, pihak marga penyelenggara juga harus menyediakan tujuh tanaman wajib sebagai mahar. Tanaman-tanaman itu terdiri dari kelapa, sagu, pisang, gembili (ubi-ubian), daun puring (anggin), pinang, dan tebu. Lalu, syarat wajib tambahan yang harus dihadirkan dalam ritual adalah tari Gatzi. Tarian Gatzi atau Nggatzi merupakan tarian berirama rancak, ceria, dan biasa dilakukan saat perayaan-perayaan tertentu. Baik dari kalangan anak-anak, dewasa, maupun orang tua, diharuskan menggunakan busana, riasan tubuh dan wajah, serta atribut tradisional.9
Yohanes mengakui, pihak kampung sangat terbantu dengan inisiatif EcoNusa dalam melakukan pemetaan wilayah adat Sanggase. Menurutnya, program pemetaan hak ulayat tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga hak ulayat terproteksi dan budaya pun lestari. “Di sini ada tempat-tempat keramat yang memang perlu dilindungi. Dan itu juga supaya dia bisa menjadi peta khusus untuk wilayah adat, bisa jadi cerita untuk anak cucu, sehingga mereka tidak lupa tentang tanah-tanah [dan] wilayah adat yang ada di Kampung Sanggase,” ujarnya.
Seiring pemetaan wilayah adat dan pengarsipan budaya, EcoNusa juga sedang dalam proses pemetaan potensi ekonomi kampung. Beberapa komoditas unggulan Sanggase antara lain kopra dan padi.

Titipan untuk generasi penerus adat Malind
Fondasi adat telah diletakkan para tetua sejak anak-anak usia dini. Berlangsung turun-temurun menembus waktu, melintasi generasi—yang ajaibnya—mampu terekam kuat di memori dan hati tanpa sempat tercatat dalam buku-buku atau produk audiovisual. Ke depan, penerus estafet adat Imo Sanggase itu akan berpindah ke generasi muda. Tanpa pedoman agama dan adat, di tengah modernisasi dan akses informasi yang kian masif, suku Malind Imo Sanggase bisa hilang ditelan sejarah.
Oleh karena itu, mempertahankan kawasan hutan dan bentang alam sekitarnya— rawa, sungai, dan laut—berarti mempertahankan sumber pengetahuan dan ladang penghidupan masyarakat Sanggase. Melindungi alam berarti pula melindungi kebudayaan dan identitas Malind-Anim di Merauke. Yohanes mengingatkan, “Hutan itu jangan sampai rusak. [Jika] dirusak akhirnya [akan] berdampak terhadap lingkungan dan masa depan generasi orang Malind.”
Kristianus dan Heri bahkan sepakat pesan-pesan leluhur untuk menjaga adat tidak hanya disuarakan, tetapi juga didokumentasikan dan disampaikan kepada publik, baik kepada orang Papua sendiri maupun orang-orang luar Papua. Bahwa mereka ada dan perannya krusial dalam menjaga salah satu kawasan hutan tropis dataran rendah terakhir di Merauke.
“Untuk anak muda, generasi muda, kita sudah kasih [pendidikan adat dan kekayaan sumber daya alam yang harus dikelola] lebih dulu. Sekarang tinggal jaga itu saja,” ujar Kristianus memberi nasihat. Ia ingin anak-anak Sanggase mau mendengar arahan para orang tua tentang seluk-beluk adat, serta pentingnya menempatkan adat dan agama secara setara dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menyangkut urusan pekerjaan. Apa pun hal-hal baik dalam adat yang sudah dilakukan orang-orang tua terdahulu, selanjutnya diteruskan generasi muda.
Setali tiga uang, Heri juga memberi peringatan dan melarang keras anak-anak Sanggase menjual kampung dan hutan adat hanya karena alasan uang. Pria yang tinggal di rumah paling ujung barat kampung itu berharap, anak cucu mereka kelak juga harus menikmati anugerah sumber daya alam yang sama seperti sekarang dirasakan para orang tua.
“Dalam bahasa kami, awasi hutan kami, alam kami; jaga dia [alam] baik sesuai dengan keputusan [perintah] Yang Maha Kuasa. [Begitu juga] dengan peninggalan orang tua kita, ya, itu kami [harus] pertahankan,” tegasnya.
Sebagaimana makna sangga yang berarti ‘tangan’ dalam bahasa Malind, orang-orang muda Sanggase tak akan letih memberdayakan tangannya untuk berkarya, mengolah kekayaan sumber daya alam yang terjaga karena harmoni agama dan adat. Dari sagu hingga kelapa, dari rusa hingga ikan rawa.
- Pusaka Bentala Rakyat, “Briefing Paper Yayasan Pusaka Bentala Rakyat: Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Pangan & Energi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan: Melanggar Hak Asasi Manusia dan Meningkatkan Krisis Lingkungan HIdup”, Hutan Hujan, 2024, September, https://www.hutanhujan.org/files/id/2024-Briefing%20Paper%20PSN%20Merauke%20(Pusaka).pdf. ↩︎
- Pemerintah Kabupaten Merauke, “Letak dan Luas Wilayah”, merauke.go.id, 2018, https://portal.merauke.go.id/page/33/letak-dan-luas-wilayah.html. ↩︎
- Vindry Florentin, “Food Estate Merauke Bisa Kembali Gagal. Mengapa?”, Tempo.co, 2024, September 22, https://www.tempo.co/arsip/mifee-food-estate-merauke-23307. ↩︎
- Konsorsium Pembaruan Agraria, “Terbukti Selalu Gagal, Pertanian Food Estate Bukan Jawaban Pemenuhan Pangan Nasional”, 2024, Oktober 15, https://www.kpa.or.id/2024/10/terbukti-selalu-gagal-pertanian-food-estate-bukan-jawaban-pemenuhan-pangan-nasional/. ↩︎
- Diperkuat dengan Perpres Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang menetapkan program pangan sebagai proyek strategis prioritas, Permenko Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), Perpres Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel), Keppres Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol (Satgas Gula Bioetanol) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. ↩︎
- Raden Putri Alpadillah Ginanjar, “Daftar Perusahaan Penggarap Proyek Food Estate Merauke Jokowi”, Tempo.co, 2024, September 25, https://www.tempo.co/ekonomi/daftar-perusahaan-penggarap-proyek-food-estate-merauke-jokowi-5855. ↩︎
- Rievki Pramudya, “Pemetaan Partisipatif Kampung Sanggase: Meneguhkan Warisan Budaya dan Hak Adat Imo Suku Malind”, EcoNusa, 2025, Februari 14, https://econusa.id/id/galeri/pemetaan-partisipatif-kampung-sanggase-meneguhkan-warisan-budaya-dan-hak-adat-imo-suku-malind/. ↩︎
- Andria Agusta et al., “ANALISIS KOMPONEN KIMIA DAUN WATI {Piper Methysticum Forst. F) [Analysis of Chemical Compounds of Wati {Piper Methysticum Forst. F].”, Berita Biologi, vol. 4, no. 2, 1998, http://e-journal.biologi.lipi.go.id/index.php/berita_biologi/article/view/1276. ↩︎
- Widra, “Nggatzi/Gatzi”, Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, 2021, Januari 12, https://budaya-indonesia.org/ngaatzigatzi. ↩︎
Foto sampul: Siprianus Heri Gebze, tokoh adat Malind Imo, mengenakan atribut adat berupa mahkota bulu kasuari dan cenderawasih, serta ikat lengan dari gelang rotan dan daun puring (anggin). Simbol kebanggaan masyarakat Sanggase terhadap adat.
Pada Agustus–September 2025, tim TelusuRI mengunjungi Merauke (Papua Selatan), Jayapura (Papua), serta Tambrauw dan Sorong (Papua Barat Daya) dalam ekspedisi Arah Singgah: Tanah Kehidupan. Laporan perjalanannya dapat Anda ikuti di telusuri.id/arahsinggah2025.
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.
Jika tidak dituliskan, bahkan cerita-cerita perjalanan paling dramatis sekali pun akhirnya akan hilang ditelan zaman.