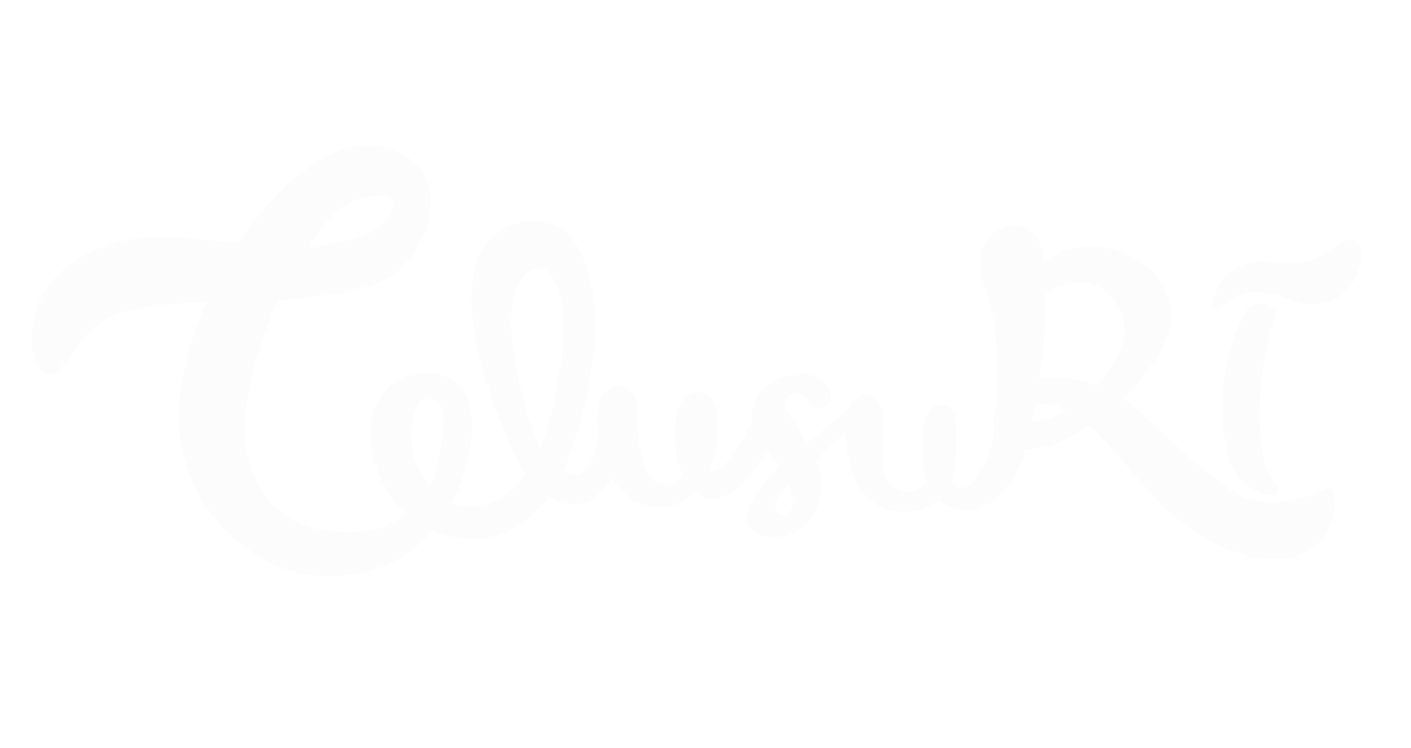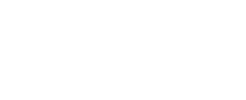TelusuRI kembali lagi ke Papua. Meski kali ini banyak cerita yang berbeda, tetapi tantangan besar yang dihadapi masyarakat adat selalu sama.
Teks: Rifqy Faiza Rahman
Penyunting: Mauren Fitri ID
Foto: Deta Widyananda

Beberapa dekade belakangan, isu-isu seputar Papua yang menghiasi lini masa media, daring maupun luring, selalu jadi bahasan hangat. Topiknya beragam. Mulai dari politik, ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, hingga eksotisme wisatanya.
Tak terkecuali pula keresahan atas krisis iklim dan ekologis sebagai dampak eksploitasi sumber daya alam, yang bahkan menembus radar global. Isu lingkungan ini turut menempatkan pertanyaan besar pada nasib hutan-hutan tropis Papua di masa depan. Serupa halnya hutan Amazon—kawasan hutan hujan tropis terbesar dunia—di Brazil (60 persen hutan ada di sini), tuan rumah konferensi iklim COP30 yang akan berlangsung pada 10-21 November, 2025.
Sayangnya, bagi sejumlah kalangan, mendiskusikan Papua seolah sedang membicarakan sesuatu yang aneh atau asing. Dari ibu kota negara, Jakarta—terletak di pulau terpadat Indonesia yang “terlalu” sentralistis untuk segala urusan negara—Papua terpisah lautan luas berjarak ribuan kilometer jaraknya. Sejauh kesenjangan sudut pandang yang terpampang nyata, sebagaimana stigma sempit yang melekat di kebanyakan orang tentang Papua. Padahal, di balik itu terukir kiprah-kiprah sederhana masyarakat adat yang berdampak besar pada keseimbangan alam, tetapi jarang tersorot kamera.
Syahdan, era terkini membuat warga yang memiliki akses informasi tidak hanya membahas tambang emas Grasberg di jantung Pegunungan Maoke, atau konflik-konflik horizontal yang tak kunjung ketemu solusinya. Ada pula persoalan-persoalan genting yang rasanya terlalu muskil untuk dilewatkan bahkan harus terus didengungkan. Salah satunya gelagat pembiaran deforestasi yang mengancam 33,12 juta hektare hutan di Papua.1 Sebuah persoalan serius yang mesti digaungkan dengan lantang ke pelbagai penjuru, termasuk forum internasional COP30. Sebab, kehilangan hutan bukan hanya berbicara soal karbon yang terlepas ke atmosfer, melainkan juga hak masyarakat adat yang menggantungkan hidup di atas tanahnya.
Sebagaimana telah menjadi tatanan dan kesepakatan bersama, seluruh tanah dan hutan di Papua pada dasarnya adalah tanah adat dan hutan adat. Hukum adat berkelindan dengan hukum formal, yang membuat Papua begitu istimewa. Namun, segala tarik ulur kepentingan tertentu justru mengorbankan masyarakat adat. Hutan yang begitu melekat dengan adat sebagai identitas budaya, jika musnah, berarti punah pula identitas adat tersebut. Termasuk di dalamnya bahasa, pelbagai ritus, keanekaragaman hayati, hingga wawasan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.
Besarnya peluang kehilangan identitas adat bagaikan momok menakutkan yang menghantui orang asli Papua. Namun, di balik keterbatasan, di antara sekian jalan terbentang untuk bertahan, tampak setitik suluh harapan yang pantas mendapat tempat lebih untuk menjadi benderang.
Tak sedikit yang kukuh berjuang, membuktikan diri bahwa mereka ada dan berdaya. Masyarakat adat lintas generasi melahirkan inisiatif-inisiatif sederhana, tetapi bisa memberi dampak signifikan agar lebih didengar. Di sini, jawaban dari krisis iklim tak selalu lahir dari ruang rapat atau deratan angka kebijakan, melainkan dari manusia-manusia yang hidup berharmoni dengan alam, yang sehari-hari hidup tenang dengan merawat apa yang bumi sediakan.
Untuk itu, hanya melalui sebuah perjalananlah, membuka pintu dan pergi jauh dari rumah, kita bisa sedikit melihat Papua dan kompleksitasnya dari dekat. Lewat “Arah Singgah 2025: Makan Key Almig”, TelusuRI mencoba menyelami kekayaan warisan alam dan budaya Papua yang luhur, yang rasanya terlampau berharga untuk dilupakan dan sekadar jadi cerita pemanis belaka. Dalam bahasa Malind-Sanggase, “Makan Key Almig” berarti tanah kehidupan, menggambarkan keterikatan serta penghargaan masyarakat adat Papua—secara umum—terhadap tanah, hutan, dan lingkungan alam yang memberikan napas dan harapan hidup.
Dari Papua, kami ingin kembali mengingatkan bahwa menjaga tanah kehidupan ini tak cukup hanya dengan bergema di ruang konferensi atau panggung-panggung besar dunia; tetapi juga membumikan napasnya di antara kampung-kampung terpencil, pasir yang berbisik, dan embusan angin yang menggoyangkan pepohonan.

Dari Merauke hingga Sorong
Sejak 2022, ekspedisi jurnalistik Arah Singgah telah meninggalkan jejak di Bali, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Riau, Kalimantan Timur, Papua Barat Daya, dan Papua. Tahun ini, persinggahan kami bertambah di satu provinsi baru, yakni Papua Selatan. Tepatnya di Kabupaten Merauke. Dari Kota Rusa, kami kembali ke Jayapura, lalu dipungkasi dengan kunjungan ke wilayah adat suku Moi yang berada di Tambrauw dan Sorong.
Misi utama kami tidak berubah. Kami berupaya mendengar dan merekam kisah-kisah sunyi dari masyarakat adat yang inspiratif, menggugah benak serta sanubari. Tutur kisah dan laku para keluarga dari berbagai marga yang bertahan hidup dengan warisan leluhur dan hak ulayat, demi masa depan anak cucu.
Fokus tema besar ekspedisi tahun ini tidak beda jauh seperti sebelumnya, yaitu ekonomi restoratif. Sebuah upaya peningkatan taraf hidup berbasis masyarakat dan sumber daya alam lokal, dengan tetap mempertahankan keseimbangan lingkungan. Dalam bahasa sederhana, memanfaatkan hasil alam sebagai sumber penghidupan tanpa merusak alam.
Edisi Arah Singgah kali ini menjadi yang pertama kalinya kami menginjakkan kaki di Merauke, ibu kota Provinsi Papua Selatan. Bumi Anim-ha, rumah bagi sebagian besar masyarakat adat Malind-Anim. Kami pergi ke arah barat, tepatnya Kampung Sanggase. Kampung ini terletak di ujung timur Distrik Okaba. Selama kurang lebih sembilan hari, kami berkeliling melihat potensi ekonomi berbasis sumber daya alam dan masyarakat. Kami juga menyaksikan masih kentalnya adat yang berlaku di daerah pesisir selatan Merauke itu.
Dari Merauke, kami singgah sejenak di Kota Jayapura. Kami menyempatkan berkunjung ke Kampung Enggros, perkampungan apung di atas Teluk Youtefa. Kami diajak oleh Petronela Merauje untuk melihat kondisi terkini hutan perempuan dan potensi UMKM yang dihasilkan para mama di sana.
Papua Barat Daya kami tetapkan sebagai destinasi penutup ekspedisi. Kami kembali ‘baku sapa’ dengan orang-orang Moi Kelim di pantai utara Tambrauw dan juga Malaumkarta Raya, Kabupaten Sorong. Tempat yang kami anggap seperti ‘rumah kedua’, sehingga ke wilayah suku Moi serasa pulang ke rumah. Selain mengamati burung-burung endemik yang eksotis, kami juga melihat langsung waili, proses memasak tradisional dengan bahan pangan lokal ala komunitas adat terbesar di Sorong Raya tersebut.
Di tempat-tempat itu, di tengah tantangan perubahan iklim dan arus modernisasi, sejatinya masyarakat adat konsisten mengisi hari-harinya di bumi yang selaras dengan alam. Melanjutkan warisan-warisan luhur dari nenek moyang. Namun, telah lama pula, tradisi lokal berlangsung di bawah bayang-bayang ancaman perebutan ruang hidup masyarakat adat.
Deforestasi, atau alih fungsi lahan hutan hingga wilayah perairan akibat eksploitasi industri ekstraktif, menjadi salah satu tengara paling kentara. Anugerah Tuhan lewat alam Papua yang kaya, nyatanya harus bernapas tersengal tanpa banyak didengar. Pohon-pohon sagu yang rubuh, hutan-hutan keramat yang lenyap, kicau burung-burung endemik yang samar-samar menghilang, seperti mewakili isi hati bumi yang kian menua. Entah karena alasan pembangunan daerah, atau terekam radar negara sebagai proyek strategis nasional potensial untuk cetak sawah, perkebunan tebu dan kelapa sawit, hingga pertambangan.

Mengapa kembali ke Papua?
Jika harus menjawab alasan kembali ke Papua, pada akhirnya kami kembali pada kesadaran, bahwa di sinilah kami kembali belajar tentang makna merawat tanah yang memberikan kehidupan. Bahwa solusi iklim berakar dari lokalitas. Oleh karenanya, isu-isu masyarakat adat—khususnya Papua—harus terus disuarakan. Di tengah keterbatasan dan tekanan dalam mempertahankan tanah adat dan hak ulayat yang melekat, mereka perlu uluran tangan dan pikiran, melantangkan suara lirih dan hati yang tulus untuk menjaga bumi cenderawasih, tempat manusia dan segala isi alam berdiam.
Arah Singgah adalah salah satu jalan kecil yang TelusuRI pilih untuk mengabarkan cerita yang kami dengar kepada publik. Kami ingin berbagi perspektif dan harapan sederhana tentang masa depan Papua. Dari para tete adat, mama-mama, generasi muda, bahkan flora-fauna yang berkembang biak dengan nyaman di dalam belantara. Soal harapan dan dampak yang mungkin timbul, itu tergantung dari sejauh mana kita mau merenung dan mengambil langkah.
Barangkali, masih terlampau muluk untuk bisa mencapai titik ideal seperti kata Jurgen Habermas dalam The Structural Transformation of the Public Sphere (1989). Bahwa seyogianya media berperan memicu kesadaran individu pada isu-isu sosial, apalagi memengaruhi opini publik. Namun, kami percaya, niat-niat baik akan menemui jalannya sendiri.
Kami merasa amat bersyukur dan beruntung bisa hadir di platform ini, memberi kabar kepada Anda tentang Papua dari segala indra yang kami punya. Mungkin saja, the answer is us; jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar Anda terhadap Papua, bisa Anda temukan di sini. Siapa tahu, kesadaran dan kepedulian kita terhadap Papua tumbuh seiring berjalannya waktu.
Selamat menikmati perjalanan kami ke sudut-sudut Papua, yang mungkin belum banyak orang datang, tahu, apalagi dikisahkan. Selamat mendengar suara hati mereka, yang tak segan mempertaruhkan hidup demi menjaga warisan nenek moyang.
- Catatan terakhir Badan Informasi Geospasial tentang tutupan hutan hujan tropis di Indonesia tahun 2023, dikutip dalam Forest Watch Indonesia, “Hutan Papua dan Kalimantan Alami Deforestasi yang Tinggi”, Agustus 9, 2024, https://fwi.or.id/hutan-papua-dan-kalimantan-alami-deforestasi-yang-tinggi/. Hutan di Papua menyelimuti 32,2 persen dari total luas tutupan hutan Indonesia. ↩︎
Foto sampul:
Jalan kampung membelah hutan rawa lebat yang ditumbuhi sagu, kelapa, dan mangrove di Sanggase, Distrik Okaba, Merauke
Pada Agustus–September 2025, tim TelusuRI mengunjungi Merauke (Papua Selatan), Jayapura (Papua), serta Tambrauw dan Sorong (Papua Barat Daya) dalam ekspedisi Arah Singgah: Tanah Kehidupan. Laporan perjalanannya dapat Anda ikuti di telusuri.id/arahsinggah2025.
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.
Jika tidak dituliskan, bahkan cerita-cerita perjalanan paling dramatis sekali pun akhirnya akan hilang ditelan zaman.