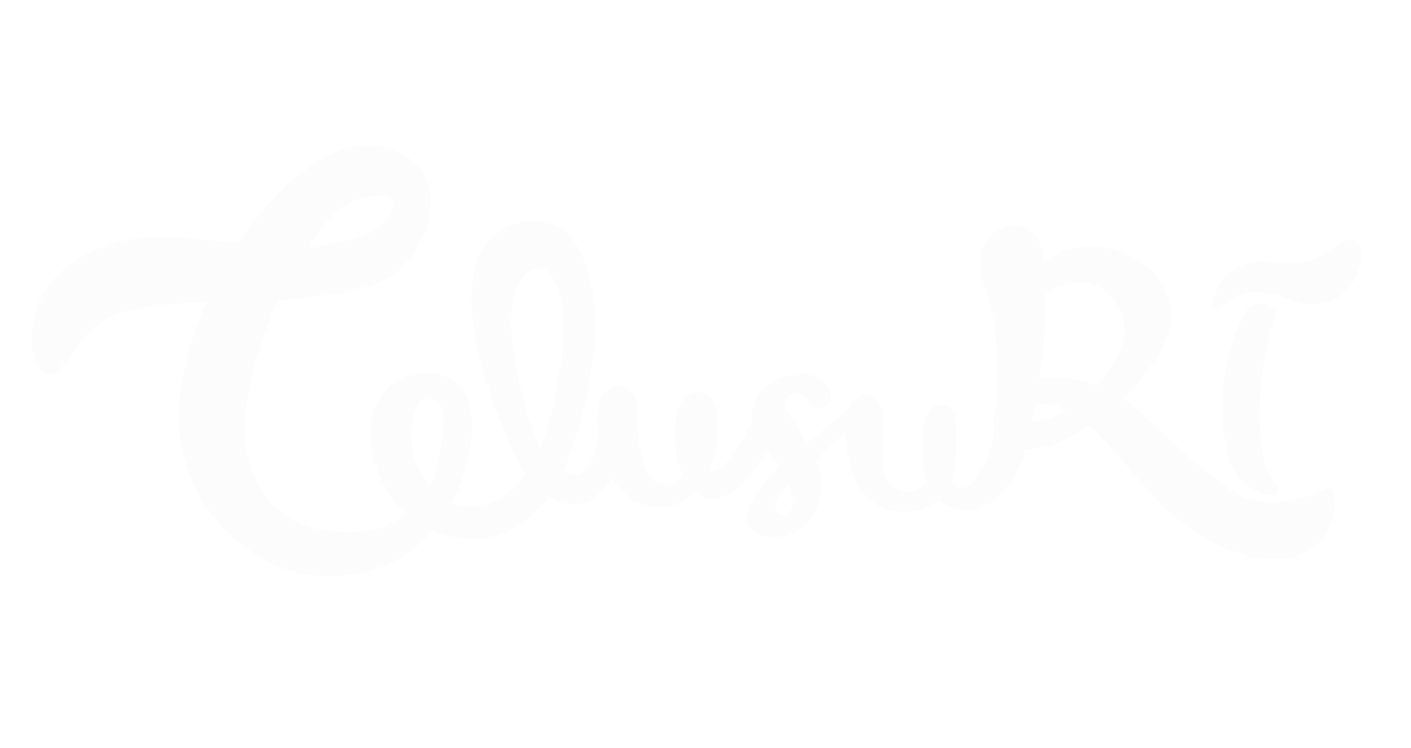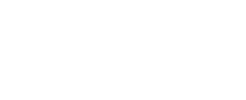Bagi banyak orang, garam hanyalah butiran putih yang murah dan mudah ditemukan. Ia hadir setiap hari di meja makan, ditaburkan begitu saja di atas masakan tanpa pernah benar-benar dipikirkan dari mana asalnya. Namun, di sebuah desa bernama Mokantarak di pesisir Flores Timur, garam adalah cerita panjang yang sarat makna. Ia bukan sekadar rasa asin, melainkan simbol ketahanan hidup, warisan budaya, dan identitas komunitas yang diwariskan dari tiap generasi.
Suatu hari, saya berjalan menuju tepian pantai desa ini. Deburan ombak memukul karang, sementara asap tipis membumbung dari tungku kayu sederhana. Udara dipenuhi aroma asin yang bercampur hangatnya kayu bakar, menciptakan suasana yang akrab. Dari kejauhan, pemandangan ini tampak biasa saja seperti potret kehidupan nelayan di pesisir lain. Namun, ketika saya melangkah lebih dekat, saya bertemu Mama Merry, seorang petani garam yang sedang memikul ember. Ia tersenyum ketika saya menghampiri dan bertanya tentang proses pembuatan garam.
“Di sini kami semua kerja manual dari ambil pasir dekat pohon bakau di sana (tepi pantai) sampai masak dengan kayu,” Kata Mama Merry sambil menunjuk gugusan pohon bakau. Darinya saya memahami bahwa setiap butir garam yang lahir dari desa ini membawa kisah panjang yang jarang terdengar oleh dunia luar.
Garam Mokantarak bukan hanya tentang produksi dan perdagangan. Ia adalah sebuah warisan yang mengajarkan tentang ketekunan dan kebersamaan. Dalam setiap butirnya, tersimpan cerita tentang tangan-tangan yang bekerja dalam diam, tentang tubuh-tubuh yang terbakar matahari, dan tentang harapan yang terus dijaga meski sering kali tak terlihat.


Kisah Tersembunyi di Balik Asinnya Garam
Garam dari Mokantarak tidak lahir dari hamparan tambak luas seperti yang sering kita lihat dalam sosial media atau televisi. Di sini, proses pembuatannya jauh lebih sederhana, bahkan terlihat rapuh, karena sepenuhnya mengandalkan tenaga manusia dan peralatan tradisional. Metode ini telah diwariskan turun-temurun, menjadi pengetahuan kolektif yang terus dipelihara agar tidak hilang ditelan zaman.
Semua dimulai dari pasir yang diambil dari pantai. Pasir itu dijemur di bawah terik matahari selama satu–dua hari. Proses ini tampak sederhana, tetapi membutuhkan kesabaran karena pasir harus benar-benar kering agar kadar garam di dalamnya mudah diekstraksi. Setelah kering, pasir digemburkan dengan tangan. Aktivitas ini memakan tenaga besar, terlebih dilakukan di bawah panas yang menyengat.
Pasir yang sudah digemburkan kemudian dimasukkan ke wadah penyaring berbahan kayu dan bambu. Wadah itu tampak sederhana, tetapi setiap detailnya dirakit dengan cermat berdasarkan pengalaman panjang. Perlahan, air laut dituangkan ke atas pasir. Air ini merembes ke bawah, membawa serta garam, meninggalkan kotoran dan lumpur di permukaan. Dari bagian bawah wadah, tetesan air yang lebih bersih keluar sedikit demi sedikit dan ditampung dalam ember.
Proses ini harus diulang berkali-kali. Setiap tetes air garam yang terkumpul memiliki nilai yang sangat berharga. Tidak ada yang tergesa-gesa, semuanya dilakukan dengan ritme yang tenang namun penuh perhatian, seperti ritual yang sakral.


Seorang petani garam perempuan menyaring air laut dengan tanah/Muh. Chairul Sahar
Setelah air garam terkumpul dalam jumlah cukup, tahap selanjutnya adalah perebusan. Air dipindahkan ke dalam wajan besar yang diletakkan di atas tungku kayu. Perebusan ini berlangsung selama berjam-jam dengan kayu bakar. Dari tungku, uap putih mengepul ke udara, menebarkan aroma khas yang memadukan garam, kayu, dan udara laut. Saat air perlahan menguap, yang tersisa hanyalah kristal-kristal garam yang berkilau di dasar wajan.
Metode ini menghasilkan garam beryodium dengan rasa yang khas. Namun, jumlah yang dihasilkan sangat terbatas. Jika dibandingkan dengan produksi pabrik modern, hasilnya mungkin terlihat kecil. Namun, nilai yang terkandung dalam garam ini tidak bisa diukur hanya dengan angka. Setiap butirnya adalah hasil dari kerja keras, kesabaran, dan cinta.
Di Mokantarak, garam bukan hanya tentang produksi, melainkan juga bahasa yang dipahami bersama. Saat melihat uap putih mengepul dari tungku, saya merasa seolah tengah menyaksikan doa yang naik ke langit, membawa harapan dari para pembuatnya.


Proses memasak air laut dengan kayu bakar (kiri) dan garam yang sudah jadi/Muh. Chairul Sahar
Keringat Perempuan yang Tak Terlihat
Jika ada yang benar-benar memegang kendali dalam tradisi pembuatan garam ini, mereka adalah perempuan-perempuan Mokantarak, seperti Mama Merry yang tubuhnya legam terbakar matahari, tetapi senyumnya tidak pernah pudar. Ia pusat dari seluruh proses produksi. Ketika banyak laki-laki muda memilih merantau ke kota untuk bekerja, perempuanlah yang tetap tinggal, menjaga tradisi sekaligus mengurus rumah tangga.
Banyak dari mereka sudah berusia paruh baya, bahkan ada yang sudah menjadi nenek. Sejak matahari terbit, mereka mulai bekerja di lahan garam. Tubuh mereka terbakar panas, tangan mereka cekatan menggemburkan pasir, menuangkan air laut, dan mengangkat ember-ember berat. Namun, tak ada keluhan yang terdengar. Mereka bekerja dalam diam, seolah rasa lelah sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Ketika senja tiba, pekerjaan fisik di lahan garam selesai. Namun, bagi mereka, hari belum berakhir. Pekerjaan rumah tangga menanti.. Seolah tidak ada ruang dalam hidup mereka untuk benar-benar beristirahat. Yang paling menyedihkan, kerja keras mereka jarang diakui padahal garam yang menjadi bumbu dasar di setiap dapur lahir dari tangan mereka.
Ada yang unik, mereka tidak menjual garam dengan uang tunai. Sistem barter masih berlaku di pasar tradisional desa ini. Segenggam garam tidak dinilai dengan uang, melainkan ditukar dengan beras, ikan, atau sayuran.
“Biasanya dibawa ke pasar di kota (Larantuka), ditukar sama sayur-sayur atau ikan atau yang lain,” ujar Mama Merry.
Praktik ini menghadirkan gambaran tentang kemandirian sekaligus keterbatasan. Tidak hanya kemandirian karena mampu membangun mekanisme tukar-menukar sendiri tanpa uang tunai, tetapi juga keterbatasan karena garam yang mereka hasilkan tidak pernah melampaui lingkaran kecil pasar tradisional
Namun, di balik keterbatasan itu, tersimpan kekuatan luar biasa. Perempuan-perempuan ini terus bertahan bukan hanya demi penghasilan, melainkan demi menjaga warisan yang mereka anggap suci. Garam bagi mereka bukan sekadar produk, tetapi cerita tentang kebersamaan dan identitas. Mereka bekerja dalam senyap, menjaga sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri.

Surat Sederhana untuk Presiden
Jika suara perempuan petani garam bisa terdengar hingga ke telinga presiden, mungkin suaranya akan menyerupai surat sederhana yang ditulis dengan tangan yang penuh kapalan dan hati yang penuh harapan.
Mereka tidak meminta proyek besar dengan janji-janji yang utopis. Harapan mereka sederhana, hanya alat produksi yang lebih ringan agar tubuh mereka tidak terlalu cepat lelah, pelatihan yang berkelanjutan agar pengetahuan mereka berkembang, dan pendampingan yang konsisten, bukan sekadar kunjungan seremonial lalu dilupakan.
Di sela percakapan sore di bawah bale-bale sederhana, ketika saya menanyakan harapan mereka kepada pemerintah, Mama Merry tersenyum lebar sebelum menjawab dengan nada penuh harap, “Untuk Pak Prabowo, kami di sini butuh pendamping sama alat, biar beban kerjanya bisa agak berkurang. Sama bisa dibantu kemasan juga supaya bisa dijual ke toko,” harapnya.
Lebih dari itu, mereka ingin memiliki akses ke pasar yang adil. Mereka bermimpi garam dari Mokantarak tidak hanya ditukar dengan segenggam sayuran di pasar lokal, tetapi bisa dikenal lebih luas, bahkan hingga ke luar pulau. Garam yang mereka hasilkan layak dihargai, tidak hanya oleh keluarga mereka sendiri, tetapi juga oleh dunia luar. Surat sederhana ini adalah simbol mimpi yang ingin mereka wujudkan, mimpi agar anak-anak mereka kelak bisa melanjutkan tradisi ini tanpa harus hidup dalam keterbatasan yang sama.
Setiap kali saya melihat uap putih yang mengepul dari tungku kayu, saya teringat perjalanan panjang setiap butir garam. Dari pasir yang dijemur di bawah matahari, air laut yang disaring dengan penuh kesabaran, hingga perebusan yang memakan waktu berjam-jam. Semua ini dilakukan oleh tangan-tangan yang mungkin tak pernah dikenal oleh orang-orang yang menikmati hasil akhirnya.
Di balik rasa asin yang kita kecap, tersimpan kisah tentang kerja keras, cinta, dan ketabahan yang luar biasa. Garam lebih dari sekadar bumbu dapur. Ia adalah pengingat tentang pentingnya keadilan dan kemanusiaan.
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.
Suka hal sederhana seperti rebahan atau ngopi, sesekali ngebacot, dan sedang berusaha berpetualang memungut CINTA.