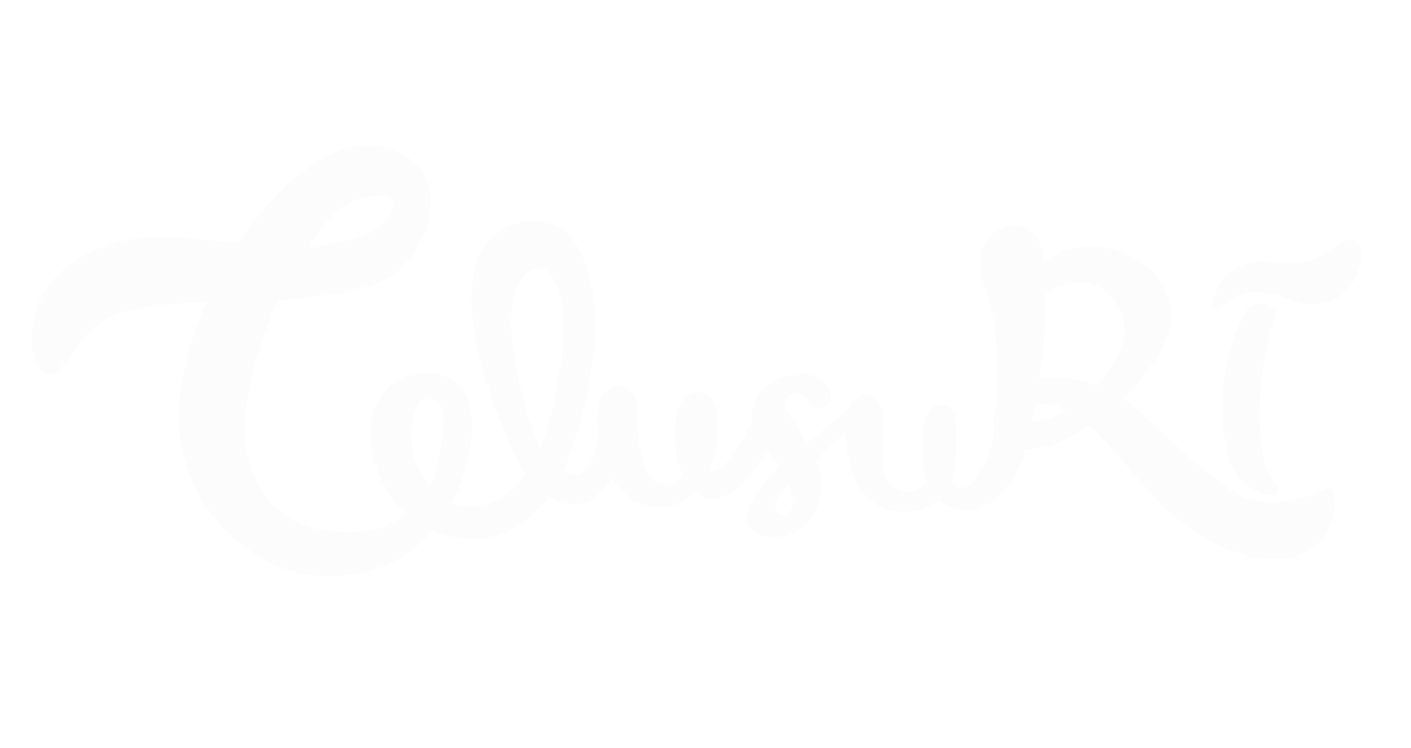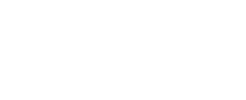Kamis sore (12/3/2025), panas terik menyelimuti Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Saya berencana menziarahi makam Kyai Raden Jalalain, seorang tokoh agama di wilayah Salam semasa Mataram Islam awal.
Makamnya terletak di Dusun Kuncen, Kelurahan Seloboro. Di antara lembah bukit Gunung Sari yang menyimpan keheningan dan ketenangan.
Usai bersiap, saya segera mengemudi ke tempat yang dituju. Wilayah ini bukan daerah terpencil karena aksesnya tidak jauh dari Muntilan. Namun, kemungkinan tersesat sangat tinggi bila tidak memahami rambu yang ada.
Saya sudah beberapa kali berziarah ke sana. Jalannya yang berkelok dan masuk gang perkampungan mungkin akan membingungkan bagi sebagian orang.
Saat saya sampai di Kuncen ternyata sudah memasuki waktu Asar. Saya memutuskan untuk salat dahulu di masjid Kyai Raden Jalalain. Udara kering dan embusan angin menerbangkan debu yang menempel di sarung dan peci saya.

Warisan Kyai Raden Jalalain
Masjid Kyai Raden Jalalain menggunakan arsitektur Jawa, khas masjid-masjid Kagungan Dalem Keraton. Pelatarannya luas untuk tempat parkir. Agaknya masjid ini sering dikunjungi peziarah.
Pak Parmuji, salah satu jemaah, tengah duduk menikmati cuaca yang panas tapi sejuk di serambi masjid. Kalau dilihat, usianya sudah tidak lagi muda, dengan rambut yang memutih dan kulit mulai berkerut. Sorot matanya teduh menanti kewajiban yang akan datang, salat Asar berjemaah. Saat saya mengucapkan salam kepadanya, ia langsung menerima dan mempersilakan saya masuk.
Pak Parmuji menjelaskan, masjid ini asli peninggalan para leluhur Mataram Islam. Dahulu, di depan masjid terdapat kolam sebagai tempat membasuh kaki, khas masjid kuno di Jawa. Beduk dan soka—pilar masjid—juga masih asli peninggalan sang kiai sejak masjid berdiri.
Ketika saya cermati, memang masjid ini menggunakan atap gaya meru, dengan empat pilar yang menyangga—semuanya terbuat dari kayu nangka. “Blumbang niki kebak (kolam ini dulu penuh),” ujarnya.


Parmuji menjelaskan, Kyai Jalalain merupakan sosok yang suka menghidangkan suguhan kepada tamu. Dari kisah turun-temurun yang ia terima, sang kiai merupakan sosok yang dermawan dan saleh.
Kyai Raden Jalalain adalah cucu dari Pangeran Singosari (Kyai Raden Santri). Kyai Raden Santri merupakan anak Ki Gede Pemanahan—perintis Mataram Islam—yang memilih menyepi di Gunungpring, Muntilan. Ia dikenal sebagai wali pertapa dan penyebar tatanan Islam Mataram di wilayah Magelang. Dapat dikatakan secara genealogis wilayah itu merupakan bagian dari peradaban awal kerajaan Mataram Islam di abad ke-16.
Pak Parmuji melanjutkan, setiap hari Jumat di masjid ini selalu ramai. Banyak jemaah dari luar wilayah Kuncen mengirimkan nasi megono, sebagai ucapan syukur atas terkabulnya hajat si pengirim. Para pengirim merupakan mereka yang berwasilah kepada Kyai Raden Jalalain untuk keberhasilan hajat mereka.
“Kalau tiap hari Jumat orang yang mengirim nasi megono itu banyak, dasarno ketrimo penuwune (karena terkabul hajatnya),” tuturnya. Ia menambahkan, jemaah yang mengirimkan nasi megono itu datang dari berbagai daerah, menunjukkan pengaruh besar sang kiai.
Masjid ini dirawat dan dikelola langsung oleh Keraton Yogyakarta. Suksesi kerajaan Mataram Islam mengangkat beberapa orang sebagai abdi dalem guna merawat masjid dan makam.

Pasukan Kera dan Nisan Keramat
Hari semakin sore dan saya sudah bersembahyang. Saya segera membenahi pakaian dan mohon pamit pada Pak Parmuji.
Makam yang saya maksud berada 50 meter ke utara dari masjid. Saya hanya perlu memindahkan sepeda motor ke dekat tangga masuk makam, kaki bukit Gunung Sari.
Saya terkejut setelah memarkirkan sepeda dan berjalan. Di depan saya, kawanan monyet ekor panjang memenuhi jalanan, ada yang duduk, mengayun di rimbun bambu, dan bersila di atas batu. Satu hal yang bisa saya pastikan, mereka satu pandangan ke arah saya.
Saya sedikit tersenyum, mengingatkan pada pasukan kera Sugriwa yang menyambut Sri Rama. Dalam epos Ramayana itu, kelak para monyetlah yang akan membantu Prabu Ramawijaya dan Lesmana menggempur Alengka.
Nyuwun lamit kulo tamune simbah, ujar saya ke mereka. Aneh bin ajaib, mereka lantas menyingkir dari jalan lalu membiarkan saya lewat. Mata mereka masih melihat saya.
Monyet-monyet ini adalah satwa asli penghuni bukit. Hal itu bisa menjadi pertanda bukit ini masih asri dan mengandung banyak sumber makanan bagi mereka.
Dikelilingi pohon bambu, akhirnya tampak gerbang depan pintu makam menghadap ke sisi selatan. Gerbang itu berukuran sekitar empat meter dengan tangga naik di tengahnya.
Saya segera naik ke makam Kyai Raden Jalalain. Makam tersebut diberi tanda dengan bangunan khusus di sisi barat pemakaman ini. Dalam petak makam Kyai Raden Jalalain, terdapat nisan lain yang hampir sama coraknya.
Segera saya mengambil sikap bersila, mengeluarkan tasbih, dan menutup mata. Dalam rapalan Yasin dan tahlil yang saya baca dalam hati, saya terhanyut dalam keheningan bukit Gunung Sari

Makna Ukiran Naga
Saya terpukau dengan desain dan suasana yang terbangun dari makam ini. Ketika berada menghadap makam sang kiai, saya seperti berada di dunia lain.
Nisan dari batu andesit dengan coraknya beraneka ragam itu gagah membujur di depan saya. Menurut salah satu peneliti nisan, Kyai Yaser Arafat di akun Facebook-nya, nisan di sini memiliki corak yang khas. Guratan motifnya semarak, menandakan makam ini layak disebut makam priyayi masa lampau.
Nisan Kyai Raden Jalalain berhias dua ukiran naga. Batu nisan itu dicat warna emas untuk mempertegas gambar naganya. Sayang, bagian kakinya patah sehingga hanya kepala nisan yang masih berdiri.
Bagi masyarakat Jawa, naga merupakan makhluk mitologi yang dikeramatkan. Setiap ukiran naga pasti memiliki makna tertentu, sesuai konteksnya. Naga bisa sebagai simbol dari waktu, bahkan gelar kehormatan.
Dalam salah satu mitos peradaban Islam di Jawa, naga menjadi jelmaan dari petir yang ditangkap Ki Ageng Selo, tokoh kunci yang menjadi leluhur kerajaan Mataram Islam dan orang saleh yang terkenal sakti. Namun, karena gagal menjadi prajurit Demak, ia memilih menjadi petani di Grobogan. Dalam kegiatan bertani itulah ia menangkap petir yang akhirnya menjelma sebagai naga.
Sejauh pengalaman saya, naga dapat menjadi simbol waktu seperti di Keraton Yogyakarta. Namun, makna ukiran naga di nisan ini masih belum diketahui. Menafsirkan hal seperti ini baiknya merujuk sumber literatur atau cerita tutur yang beredar di kalangan sekitar. Sangat berbahaya kalau menggunakan asumsi saya pribadi, bahkan penelusuran gaib.
Orang yang terlampau klenik dan ngawur menafsirkan ukiran tersebut kemungkinan besar dapat tersesat. Seperti berpendapat bahwa dahulu sang kiai selama hidup memiliki khodam peliharaan dua ekor naga. Naudzubillah.

Mendadak Pusing di Makam Bernisan Megah
Saya menyempatkan berkeliling. Beberapa nisan megah sempat memukau hati. Di atas pintunya tertulis K.R.T. Wiraguna. Entah siapa sosok tersebut, tetapi kemegahan nisannya menandakan beliau pasti bukan orang sembarangan.
Bergeser sedikit ke sisi timur, saya menemukan barisan nisan megah tanpa cungkup, berderet dan berhiaskan ukiran yang bermacam-macam. Saya mendekati dan mencermatinya lebih detail, sembari mengisap batang kretek yang saya bakar. Satu nisan memiliki ukiran unik, terlihat seperti ukiran sosok humanoid. Kalau orang yang tidak paham bahasa nisan mungkin sudah menduga itu ukiran tuyul.
Saat fokus mencermati nisan, kepala saya mendadak pusing. Saya merasa seolah ada kekuatan dari luar diri saya memaksa tunduk. Hal itu berlangsung sedikit lama meski masih tidak saya hiraukan.
Tiba-tiba Pak Muhaji menghampiri dan mengejutkan saya. Saya segera memperkenalkan diri dan bersalaman.


Makam Kyai Wirawerna (kiri) dan ukiran sosok humanoid/Rizqy Saiful Amar
Ia berpakaian rapi, bersarung, dan berpeci, hendak berziarah ke makam orang tuanya. Itu adalah makam Kyai Wirawerna, kisahnya, seorang ratu—sebutan khas orang Jawa kepada raja, dan kiai yang terkenal dermawan. Pak Muhaji mendapat kisah tersebut ketika bersama rekan-rekannya dulu sowan ke kediaman KH. Ahmad Abdul Haq.
Mereka mendapat pesan dari ulama karismatik di Magelang itu untuk merawat makam dengan baik. Sebab, Kyai Wirawerna dahulu memang terkenal sebagai pemimpin wilayah setempat yang baik.
“Niki Wirawerna, lumane ra ilok (Ini makam Wirawerna, orangnya sangat dermawan),” pungkasnya.
Kepala saya masih pusing. Mungkin sang kiai ingin berkenalan, batin saya. Segera saya berpindah dan duduk bersila di samping nisan. Rapalan kalimat tahlil membawa saya kembali ke alam keheningan.
Nisan kuno, menurut sebagian pegiat sejarah memiliki makna yang tidak biasa, yang dapat menjadi penanda dari mana tokoh itu berasal, kedudukan yang dimiliki, dan sanad keilmuannya. Nisan-nisan di pemakaman ini banyak yang tercecer, dilalap rumput ilalang, bahkan patah. Semoga ke depannya ada pihak-pihak yang sadar dan menyelamatkan rekaman fisik peradaban Islam ini.
Usai berdoa, saya kembali ke rumah. Berharap suatu saat bisa menjadi penerus para pembangun peradaban itu.
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.
Amar seorang remaja kabupaten Magelang. Suka menjelajah daerah pinggiran dan gang-gang sempit. Suka memancing wader dan kontemplasi.