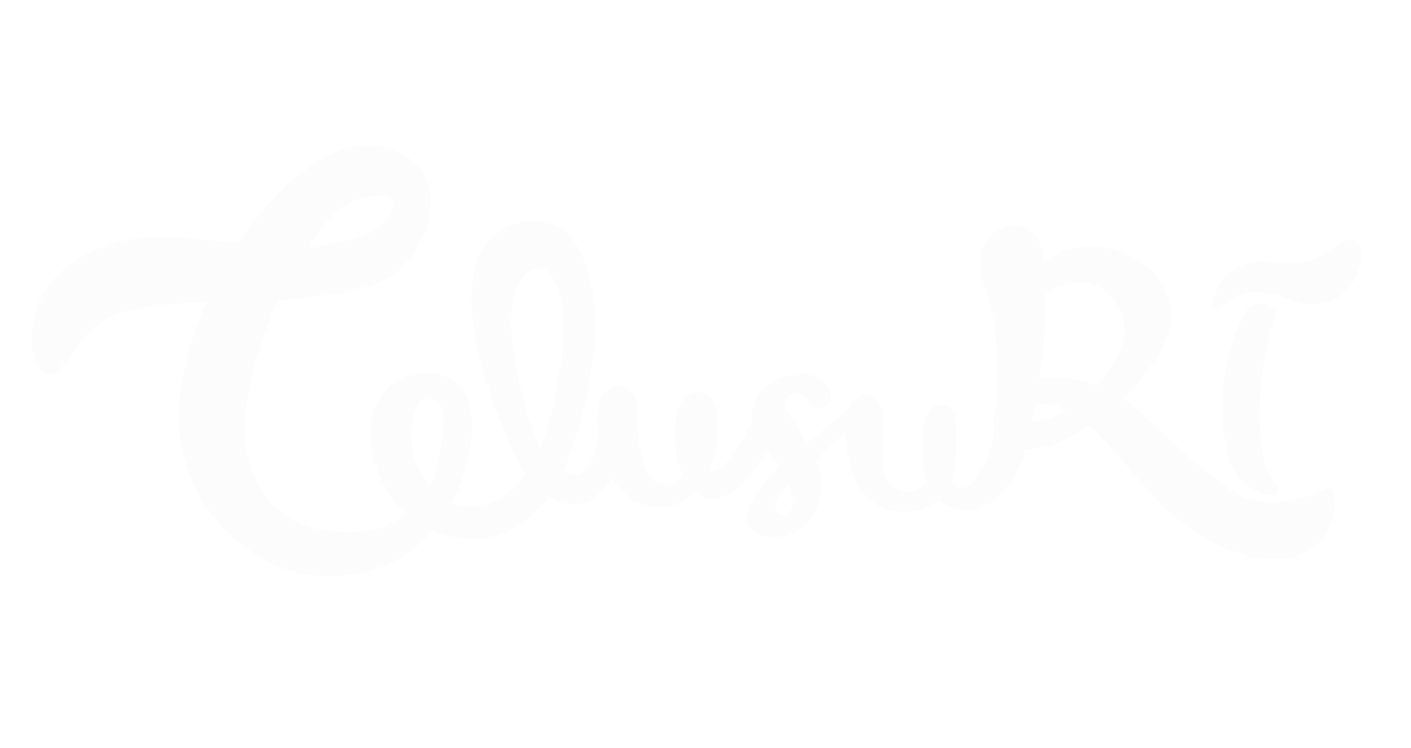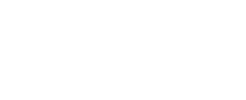Apa yang terjadi jika 20 kampung bertemu, bukan untuk bertanding, melainkan bersuara bersama lewat bedug dan napas tradisi?
Tiga hari di awal Juni 2025, Pandeglang tak hanya membuka ruang publik. Ia juga membuka ingatan kolektif. Ada 20 kampung dari berbagai penjuru Kabupaten Pandeglang berpartisipasi dalam Gebrag Ngadu Bedug, sebuah kompetisi yang sejatinya adalah nyanyian budaya. Ia lantang, berakar, dan menyentuh.
Beduk-beduk dipukul secara bergiliran, bersama lagu-lagu tradisional dan gerak tubuh yang bersatu dalam semangat perayaan. Anak-anak, remaja, hingga orang tua semuanya ambil bagian, lengkap dengan kostum, dan aksesoris. Setiap kampung melalui saung tagog masing-masing menyampaikan sebuah narasi: tentang siapa mereka, dari mana suara itu datang, dan untuk siapa ia diperdengarkan.
Tahun ini kegiatan mengambil tema Baralak Kalapa Sawara Diluhur Tagog“ yang berarti “Daun Kelapa Mewarnai Bedug di Ketinggian”. Mengakar pada simbol pohon kelapa sebagai alam yang bagi mereka memiliki banyak kegunaan. Kemeriahan tak berhenti di bedug. Ada pawai budaya, tarian kolosal, iringan kendang pencak, serta kehadiran lebih dari 30 pelaku usaha lokal yang turut meramaikan denyut kegiatan. Namun, di antara segala keramaian itu, tabuhan beduk tetap jadi poros perhatian!

Makna Ngadu Bedug
Sebutan Ngadu Bedug bisa menimbulkan salah paham jika hanya dimaknai sekilas secara harfiah. Tidak ada aksi saling menghantam beduk. Yang terjadi justru sebaliknya: kelompok-kelompok saling membalas irama, berdialog lewat pukulan bedug dalam harmoni.
Di tengah kemeriahan kegiatan, aku sempat berpikir: dari mana asal tradisi ini? Apa yang membuatnya diterima masyarakat?
Ternyata, akarnya cukup panjang. Sebelum hadir langsung, aku sempat membaca pernyataan Bupati Pandeglang Irna Narulita tahun lalu. Ia menyampaikan, masyarakat Pandeglang di era 1950–1965 telah mengenal tradisi Ngadu Bedug. Setelah itu, tradisi ini sempat mengalami pasang surut, bahkan pernah terhenti karena berbagai faktor. Namun, dari tradisi inilah muncul bentuk baru kesenian yang disebut Rampak Bedug.
Jika ditarik lebih dalam, seniman lokal Endang Suhendar pernah mengurai dalam film dokumenter Adi Chandra Purnama, kalau Ngadu Bedug merupakan perkembangan dari tradisi yang lebih awal, yaitu nganjor atau nganjang: menyambut bulan Ramadan dengan berkeliling kampung membawa beduk. Tradisi ini awalnya sarat makna silaturahmi, tapi kemudian bergeser menjadi arena adu kekuatan yang nyaris menimbulkan gesekan sosial, memicu konflik.
Untuk mencegah konflik berlarut, pemerintah setempat kemudian mengalihkan energi kompetitif ini dalam sebuah festival atau perlombaan resmi bernama Ngadu Bedug. Di sinilah nilai kesenian dan kekompakan mulai diutamakan.
Kini aku melihat, Ngadu Bedug sebagai pertunjukan musik dan gerak yang menonjolkan permainan beduk secara berkelompok. Inti dari pertunjukan memainkan lagu-lagu tradisional melalui tabuhan beduk yang ritmis. Ada pula yang menyisipkan unsur-unsur religius seperti selawat. Pertunjukan juga selalu diiringi dengan gerak tari yang dinamis. Ada penabuh yang fokus penuh pada instrumen bedugnya, ada juga yang menabuh sembari bergerak atau menari, menciptakan harmonisasi visual dan audio. Para penampil juga memperhatikan aspek kostum dan tata rias, yang menambah daya tarik visual bagi penonton.
Namun, yang patut dicatat, bukan hanya para penampil yang layak diapresiasi. Penonton pun berperan penting dalam membangun suasana. Setiap kali satu kampung hendak tampil, para penonton dari kampung tersebut sudah bersiap penuh semangat, seperti penggemar setia yang hendak menyambut idolanya di atas panggung konser.
Aku sempat berdiri di depan beberapa saung menjelang giliran tampil. Di sana kutemukan euforia yang sama sekali tidak dibuat-buat. Wajah-wajah penuh harap, sorakan dukungan, hingga yel-yel penuh antusias. Sebuah energi komunal yang hangat.
Meski begitu, ada satu catatan kecil yang sulit aku abaikan: ketika aku tiba di ujung gerbang lokasi kegiatan, Alun-alun Pandeglang, suara beduk dari peserta yang sedang tampil tidak begitu terdengar. Untuk bisa benar-benar menikmati pertunjukan, aku harus mendekat ke tengah arena. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pengunjung yang baru datang dari kejauhan atau sekadar ingin menyimak tanpa menyusuri kerumunan.
Beduk dan Bunyi yang Berubah Makna
Sebagai seorang muslim, beduk bukanlah sesuatu yang asing bagiku. Sejak kecil, aku mengenalnya sebagai penanda waktu salat. Momen paling kuat yang selalu tinggal di ingatan juga tabuhan saat malam takbir. Maka, sungguh menarik ketika menyaksikan beduk dimainkan dalam bentuk yang berbeda di kegiatan ini.
Sebelum beduk menjadi pusat sorotan dalam pertunjukan budaya, ia pernah berfungsi sebagai sesuatu yang lebih keras, lebih mendesak. Beduk adalah suara yang dulu menandai waktu, memberi peringatan, bahkan di masa-masa genting membangkitkan kesiagaan.
Tradisi memainkan beduk telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Keberadaan instrumen ini di wilayah Nusantara diyakini berasal dari peradaban India dan Tiongkok. Dadan Sujana, penulis buku Identifikasi Kesenian Khas Banten, seperti dikutip dalam Tempo.co (14/4/2022) mencatat bahwa pada abad ke-15, Laksamana Cheng Ho pernah singgah di Semarang dan memberikan beduk sebagai hadiah kepada raja.
Versi lain mengenai asal-usul beduk juga disampaikan Cornelis de Houtman, seorang pemimpin ekspedisi dari Belanda, melalui catatan perjalanannya De Eerste Boek. Ia menyatakan bahwa pada abad ke-16, beduk telah digunakan secara luas. Saat mengunjungi Banten, ia menggambarkan adanya genderang yang digantung di tiap persimpangan jalan dan dibunyikan dengan tongkat pemukul. Berfungsi sebagai penanda waktu sekaligus alat peringatan bahaya.
Namun waktu, seperti juga bunyi beduk, punya cara sendiri untuk berubah. Hari ini, dalam perayaan Gebrag Ngadu Bedug, beduk tak lagi mengirim sinyal bahaya. Dari penanda konflik, menjadi jembatan antarkampung.
Saung Tagog yang Berbicara
Ada satu hal yang terus-menerus aku perhatikan sepanjang kegiatan: bagian saung tagog. Selama kegiatan, aku memilih untuk berjalan pelan dari satu saung ke saung lain. Tata letaknya memungkinkan penonton untuk mengitari arena secara leluasa. Saung-saung berdiri melingkar mengelilingi alun-alun, sementara panggung utama berada di tengah. Tapi yang menarik, pusat gravitasinya tidak tunggal, karena sejatinya, setiap saung adalah panggung bagi kelompoknya sendiri. Tak ada yang jadi pusat mutlak; semuanya penting dalam orbitnya masing-masing.
Semua saung tagog dibangun dan dihias dari bahan yang sama: daun kelapa. Sebuah isyarat visual sekaligus simbolis tentang daya hidup, ketekunan, dan keberlanjutan. Foto berikut merekam tiga dari dua puluh saung yang berpartisipasi. Ketiganya bukan sekadar struktur tempat tampil, melainkan juga bisa dibaca sebagai pernyataan budaya visual masing-masing kampung: tentang bagaimana mereka menafsirkan identitas, hingga merekayasa ruang pertunjukan. Dalam tiap detail arsitekturnya, perbedaan artistik tampak jelas, tapi justru dari situ kekayaan kreativitas warga muncul.
Saung di kiri berbentuk datar dan melebar dengan atap rumbia rendah, menyerupai bale terbuka. Kesan yang kutangkap: sederhana dan lugas. Saung tengah tampil lebih simetris, dengan atap lengkung setengah kubah yang cukup tinggi. Bentuknya mengingatkanku pada wajah resmi tradisi, desainnya cukup formal. Sementara saung kanan berdiri lebih tinggi dan tampak eksploratif, dengan struktur vertikal yang mencolok. Ia memberi kesan berani dan penuh eksperimen bentuk.
Di antara semuanya, ada satu saung yang cukup menyita perhatianku. Gerbangnya dihiasi dua burung besar di kiri dan kanan, entah garuda atau bangau, dengan sayap mengembang. Detail ini kumaknai sebagai penjaga panggung atau lambang keluhuran suara kampung. Portal pada saung ini tampil sebagai pernyataan visual yang kuat. Ia tak hanya menjadi penanda gerbang, tapi juga ikon panggung, semacam “gapura budaya” yang mengantar pertunjukan.
Dan lebih dari sekadar struktur, semua saung tagog ini betul-betul menjadi ruang silaturahmi. Aku melihat warga saling mengunjungi, membawa anak-anak mereka, mengobrol ringan, bertukar sapa.


Gema yang Tak Selesai
Tradisi bukanlah sesuatu yang diam, terpaku dalam bentuk, dan tertinggal di masa lalu. Contohnya melalui Gebrag Ngadu Bedug: tradisi terus bergerak, menyerap perubahan. Ia tidak dikurung dalam museum, tapi hadir dalam tabuhan yang terus diperbarui, dalam saung yang dibangun bersama, dalam tubuh-tubuh yang percaya bahwa budaya adalah merawat dan menumbuhkan.
Di masa kini, kegiatan berkumpul untuk membangun saung, menyiapkan pertunjukan, dan hadir utuh sebagai komunitas bukanlah sesuatu yang bisa dianggap “biasa”. Kegiatan ini tidak lahir dari kemegahan instan, tapi dari ketekunan proses: dari tangan-tangan yang memotong daun kelapa, menyusun bambu, menyamakan ritme beduk, hingga sabar menanti giliran tampil di hadapan publik. Tak banyak tubuh-tubuh hari ini yang mampu memberi waktu bagi proses semacam itu.
Dan suara beduk itu, belum selesai. Ia masih bergaung di dalam diri.
Referensi:
Fachreinsyah, D. (2024, 21 April). Gebrag Ngadu Bedug Didorong Jadi Agenda Nasional. Radio Republik Indonesia (RRI), https://rri.co.id/banten/hiburan/646557/gebrag-ngadu-bedug-didorong-jadi-agenda-nasional.
Setyawan, H. (2022, 14 April). Sejarah Bedug sebagai Seruan Ibadah Salat di Masjid. Tempo.co, https://www.tempo.co/ramadhan/sejarah-bedug-sebagai-seruan-ibadah-salat-di-masjid-370352.
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.
Penulis yang gemar jalan, dan menyelami pengalaman hidup melalui karya seni.