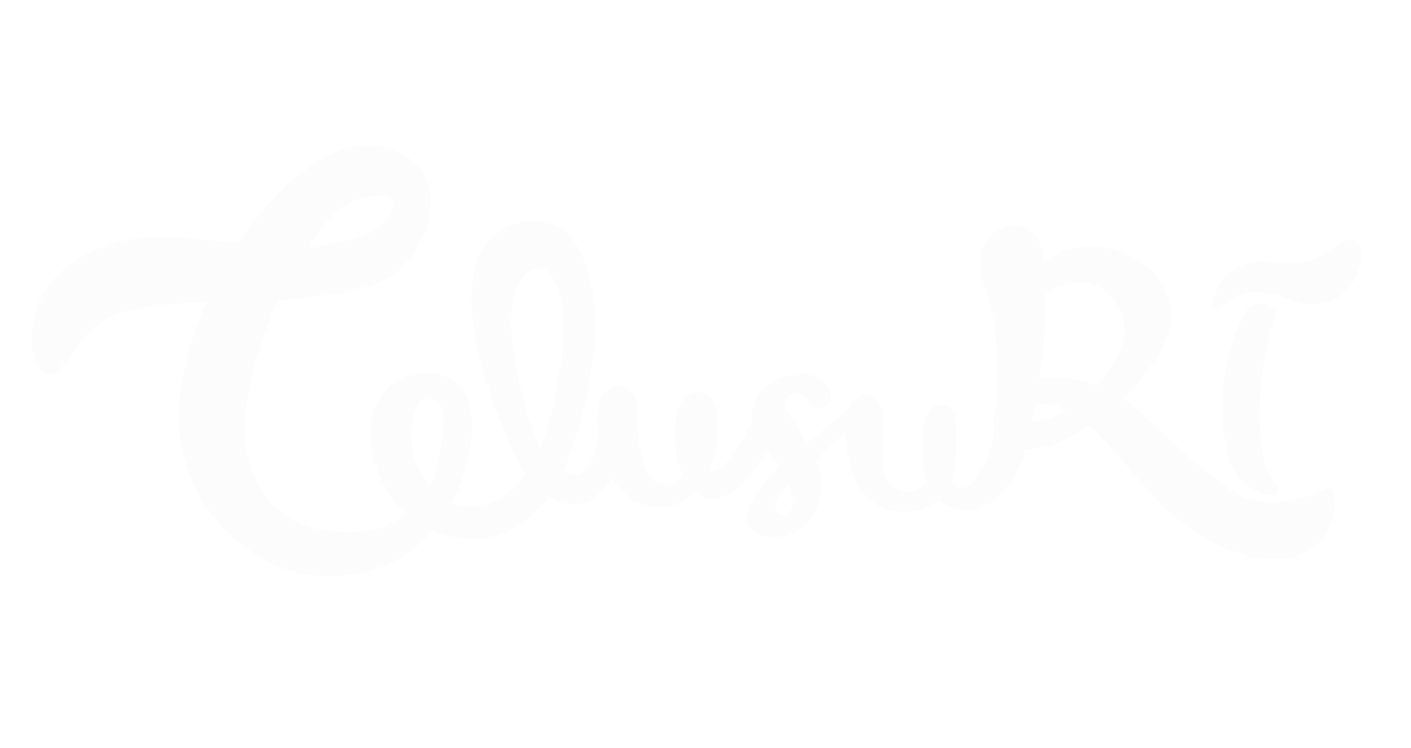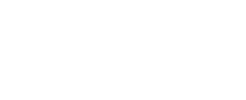“Padi dan sekam yang bercampur mesti ada tangan yang setia mengayaknya dan dengan napas kebaikan meniup sisanya”
—Forest Art Camp 2025
Ada sesuatu yang magis tentang menunggu. Tentang berkendara dalam gelap malam menuju tempat yang belum pernah dikunjungi, bersama teman-teman Sabana Tak Bertepi yang seperti biasa penuh celoteh tak karuan. Tanggal 2 Agustus 2025, kami meluncur ke Air Terjun Goa Slandak, Pakis, Kabupaten Magelang—tempat Forest Art Camp merayakan dekade pertamanya. Sepuluh tahun. Dalam hitungan manusia, itu seperti masa kanak-kanak yang beranjak remaja, penuh dengan segala pembelajaran dan sukacita.
Melalui Google Maps, saya melihat Air Terjun Goa Slandak berada di tengah hutan pinus. Setiap pohon berdiri seperti tiang katedral yang menjulang. Tempat ini sangat mungkin menciptakan akustik alami untuk simfoni yang akan dimainkan selama tiga hari (1–3 Agustus 2025). Secara geografis, lokasi ini terletak pada koordinat UTM X: 0427781 dan UTM Y: 9178307 dengan ketinggian sekitar 880 meter di atas permukaan laut—sebuah paradoks yang indah antara aksesibilitas dan ketersembunyian.
Forest Art Camp (FAC) sendiri, dalam kamus para pejalan, memiliki status setara dengan lebaran. Bukan karena keagamaan konvensional, melainkan ini adalah saat semua yang tercerai-berai sepanjang tahun—oleh pekerjaan, jarak, dan rutinitas yang menggerinda—berkumpul kembali dalam satu titik. Dari dalam-luar kota, dalam-luar pulau, mereka datang. Seperti burung yang tahu musim migrasi, para pejalan ini memiliki naluri yang sama: menemukan akar dalam gerakan, menemukan rumah dalam perjalanan.
Kami memang terlambat berangkat—hari kedua rangkaian FAC. Cukup disayangkan memang. Betapa banyak peristiwa menenteramkan yang jelas kami lewatkan. Namun, keterlambatan tersebut bukan tanpa didasari alasan yang jelas pula. Terlepas itu semua, pada akhirnya, yang terpenting dan patut disyukuri, kami tidak melewatkan semuanya secara cuma-cuma.

Pasar Rakyat di Tengah Hutan
Sesampainya di lokasi, satu agenda yang semula saya bayangkan seperti festival besar pada umumnya ternyata lebih menyerupai republik kecil. Punya mata uang sendiri, hukum sendiri, dan kultur yang sama sekali berbeda dari dunia luar.
Yang pertama kali mencuri perhatian adalah deretan di pinggir jalan masuk. Stan-stan sederhana milik warga lokal yang menjual jajanan, makanan, dan minuman.
Ini bukan sekadar stan biasa, melainkan manifestasi nyata dari semangat ekonomi kerakyatan yang jarang saya temukan di festival-festival besar lainnya. Tidak ada sponsor multinasional yang mendominasi, tidak ada booth mewah dengan brand ambassador cantik. Yang ada adalah para ibu, bapak, dan anak-anak muda yang bangga menawarkan hasil bumi lokal mereka.

Reuni Para Pejalan dan Soundtrack Satu Dekade
Belum jauh dari pintu masuk, kami sudah bertemu dengan kawan-kawan lama: Mas Alen Cantigi yang bohemian, Mas Benny dengan semangat rock-nya, dan Mas Rohmen penyeduh Kopi Tanah Mati dari Tebet, Jakarta—nama yang sendirinya sudah mengatakan ribuan kisah horor.
Pelukan dan tegur sapa kami seperti ritual tahunan yang sudah dinanti-nanti. Ada kehangatan dalam pertemuan para pelancong seperti ini—sebuah solidaritas yang terbentuk karena sama-sama mencintai hal-hal yang dianggap “tidak penting” oleh sebagian besar masyarakat. Setelah sebentar saling menanyai kabar—siapa yang baru pulang dari mana, siapa yang sedang menggarap proyek apa, siapa yang baru putus atau jatuh cinta—kami bergegas menuju pusat keramaian.
Panggung Forest Art Camp bukanlah panggung mewah yang menghabiskan biaya besar. Tidak ada LED screen raksasa, tidak ada sound system bernilai ratusan juta. Yang ada adalah panggung yang dikelilingi pepohonan—altar bumi yang diapit riuh raya ranting dan dedaunan pinus, menciptakan ruang yang pas untuk menari, berteriak, bernyanyi, melompat, dan meluncur.
Malam itu, panggung berdiri kokoh. Band-band mulai bermain: Kepal SPI, Kolektif AMPSKP, Proyek Liar, Sukatani, Indra Soekma, dan musisi atau penampilan lain yang membuat greget. Setiap instrumen yang dimainkan mengudara sepenuhnya, menyatu dengan rutinitas alam.
Yang membuat malam itu semakin berkesan adalah kehadiran Mas Ragil dan Mbak Kiki sebagai MC. Bukan sekadar pembawa acara biasa, mereka adalah kombinasi unik antara komedian, filsuf jalanan, dan motivator spiritual. Setiap jeda antarpenampilan, mereka selalu berhasil membuat penonton tertawa dengan observasi-observasi jenakanya, tentang kehidupan anak muda urban yang memilih datang ke tengah hutan ketimbang ngelitih di jalanan.


Pertunjukan Sukatani (kiri) dan tarian api/Tsan Sod Ai
Perkemahan di Bawah Bintang
Setelah puas menikmati musik, kami turun mencari spot untuk mendirikan tenda. Di sinilah letak keajaiban Forest Art Camp: ia menciptakan mikrokosmos tersendiri. Selama tiga hari, di tengah hutan pinus yang hijau, tercipta sebuah utopia temporer. Para pelancong dan penduduk tetap berkumpul dalam suasana yang egaliter. Tenda-tenda bermunculan bak jamur setelah hujan, masing-masing menjadi rumah bagi mimpi-mimpi yang ditanggung dari kota.
Setelah cukup lama mencari tempat camping, kami memutuskan untuk mengisi perut. Kami kembali ke jalanan pintu masuk, menuju “Pasar Rakyat” dengan ragam masakan lokal yang sejak awal sudah menarik hati.
Dengan perasaan takjub dan penasaran, saya menjumpai fenomena yang belum pernah dialami sebelumnya: transaksi menggunakan sistem kepik. Ya, kepik, semacam mata uang lokal yang harus kami tukar terlebih dahulu dengan rupiah. Bukan rupiah, kartu kredit, maupun e-wallet yang sedang tren.
Saya masih ingat betapa uniknya sensasi menukar selembar Rp50.000 dengan segenggam kepik kecil yang terasa seperti token permainan anak-anak. “Ini seperti main monopoli sungguhan,” celetuk salah satu kawan. Dan memang begitulah rasanya—seperti bermain dalam dunia paralel.
Dengan kantong penuh kepik, saya seperti anak kecil yang baru pertama kali ke pasar malam. Pilihannya beragam: soto dengan kuah bening yang hangat, sayur lodeh dengan santan kental, tumis bihun dengan wangi bumbu, gorengan yang masih panas dari wajan, bakso dengan cabai rawit yang membuat berkeringat, teh hangat, kopi tubruk khas desa, dan berbagai makanan lokal yang namanya tak saya ketahui tapi terlihat menggugah selera.
Akhirnya, saya memesan nasi dengan lauk yang terlihat paling menggoda: telur berkuah kuning, tumis bihun yang masih berasap, dan dua lapis tempe goreng yang cokelat sempurna. Total biaya: enam kepik. Dalam perhitungan rupiah, mungkin sekitar dua belas ribu. Tapi dalam pengalaman, ini tak ternilai harganya. Ada sesuatu yang berbeda ketika makan di tengah alam terbuka, dikelilingi teman-teman baru dan lama.

Komedi Tengah Malam
Malam semakin larut, dingin semakin menggigit, dan kami berkumpul di tenda untuk sesi ngobrol tengah malam. Di sinilah karakter-karakter unik dalam grup kami mulai bermunculan.
Mas Jazuli a.k.a Juju bercakap-cakap seperti komedian papan atas yang terampil. Gelak tawa tak terelakkan, udara yang semula dingin menjadi hangat penuh keringat.
Ada pula Miko, yang sedang dalam fase apa yang kami sebut “transformasi Gandhi”. Entah pengaruh buku-buku filsafat yang dibacanya atau karena sedang dalam masa pencarian jati diri, Miko tiba-tiba menjadi sangat minimalis dan kontemplatif. Dia bisa tidur di mana saja, dalam posisi apa saja, dan terbangun dengan wajah damai seperti orang yang baru mendapat pencerahan spiritual. “Gandhi yang kebanyakan tidur,” begitu kami menyindirnya, dan dia hanya tersenyum bijak seperti benar-benar sedang menjalani meditasi berkelanjutan.


Lebih dari Sekadar Festival
Pukul empat subuh, ketika langit mulai menunjukkan warna abu-abu samar, kami mulai membereskan tenda dan bersiap pamit. Bukan bosan atau tidak nyaman, melainkan karena sore harinya ada komitmen lain yang tak kalah penting: mini tour dari BudiSNI dengan judul puitis “Cintaku, Kalah”. Ironis memang, meninggalkan satu acara untuk mengejar acara lainnya. Tapi begitulah hidup seorang penikmat keindahan—selalu ada dilema memilih di antara pilihan-pilihan yang sama-sama menenteramkan.
Kehadiran warga lokal sebagai penjual makanan dan minuman bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan praktis pengunjung. Ini adalah manifestasi dari konsep pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya. Event budaya tidak melulu menjadi privilese kelas menengah urban, tapi bisa menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar.
Pemilihan lokasi yang tersembunyi di tengah hutan pinus juga bukan kebetulan. Kawasan air terjun dengan akses jalan yang mudah dijangkau ini menjadi metafora tentang bagaimana agenda yang baik seringkali tersembunyi—butuh upaya untuk ditemukan, tapi memberikan dampak tak terlupakan bagi mereka yang bersedia mencarinya.
Sistem kepik sebagai mata uang lokal bukan sekadar gimmick kreatif, melainkan eksperimen sosial yang mengingatkan kita bahwa nilai sejati sebuah pengalaman tidak selalu bisa diukur dengan standar konvensional. Dalam segenggam kepik kecil itu, tersimpan filosofi tentang bagaimana komunitas bisa menciptakan sistem, nilai, dan cara hidupnya sendiri.
Satu dekade dalam sebuah kepik. Terdengar sederhana, tapi di dalamnya tersimpan kompleksitas dan kedalaman yang mungkin perlu satu dekade lagi untuk benar-benar saya pahami.
Foto sampul: foto bersama para pejalan yang bertahan sampai akhir acara Forest Art Camp 2025 (Azzriel K.)
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.
Kind Shella, seorang pegawai swasta yang kelewat batas menyukai keindahan. Selain bekerja, ia juga tergabung dan aktif belajar semesta keredaksian di Penerbit Kobuku.