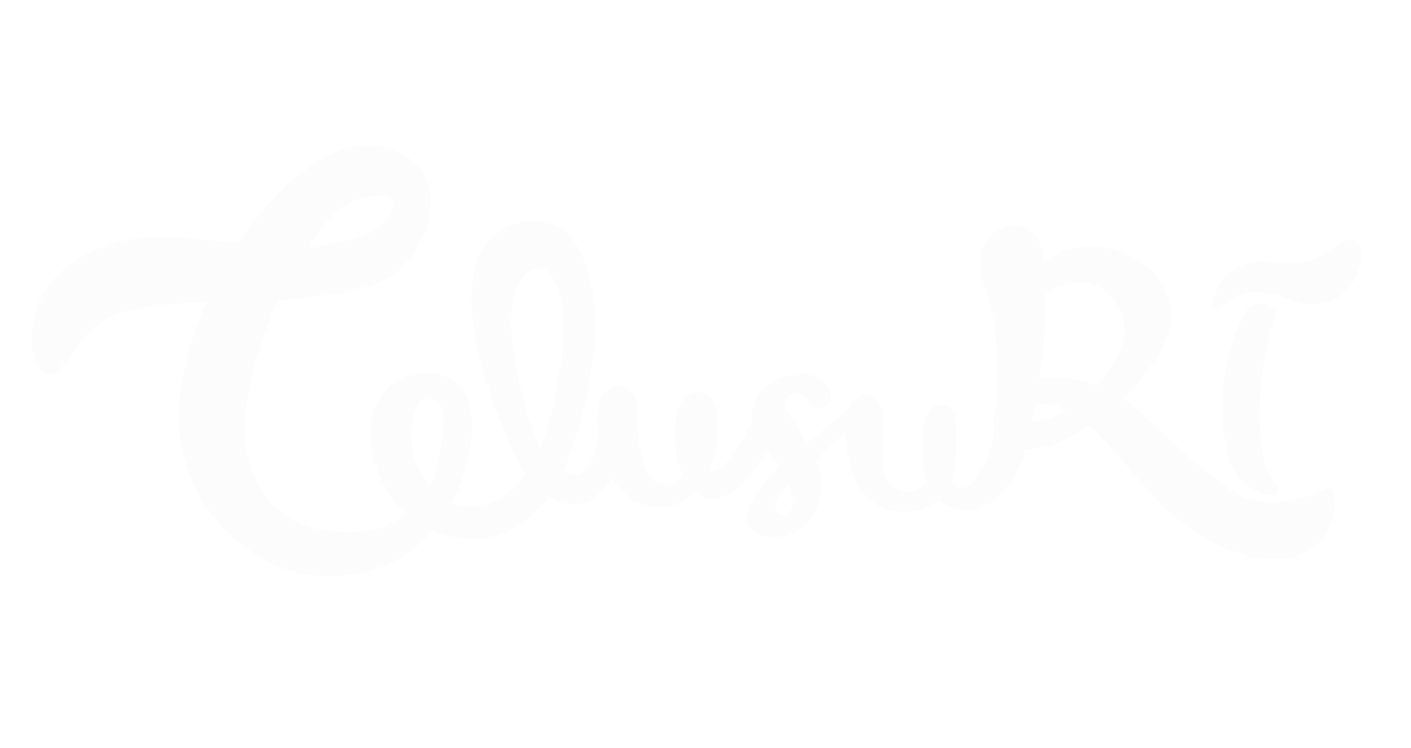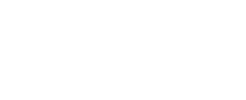Titu, teman saya, mengirim pesan WA pukul 01.00 WIB. Ia bilang, tidak jadi berangkat karena diarenya tambah parah. Saya baru baca sekitar pukul 05.00 pada Minggu (22/6/2025). Saya pun gamang untuk berangkat ke situs Petirtaan Ngawonggo. Sebelumnya, kami memang sudah janjian berangkat bareng dengan motor masing-masing. Sempat berpikir tidak berangkat, tapi kemudian saya lekas bersiap-siap ketika jam dinding menunjukkan pukul 08.30. Saya pergi.
Dengan motor matic Yamaha merah, saya menuju Petirtaan Ngawonggo. Ingatan saya akan lokasi Ngawonggo terbilang samar-samar. Maklum saja, saya tahu letak tempat ini secara tidak sengaja. Ceritanya, beberapa bulan lalu saat mengantar anak rekreasi ke Pemandian Gentong Mas, ternyata rutenya melewati Dusun Nanasan, Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, lokasi petirtaan ini berada. Untuk itu saya tetap membutuhkan petunjuk Google Maps. Butuh waktu kurang lebih 25 menit dari rumah saya di pinggiran Kota Malang menuju Petirtaan Ngawonggo.

Uang Pring sebagai Alat Transaksi
Sesampainya di lokasi, saya agak terperangah begitu mengetahui letak petirtaan yang terbilang masih menyatu dengan permukiman penduduk. Tepatnya di belakang rumah warga. Seorang lelaki berusia sekitar 50 tahun mengarahkan saya agar memarkir motor di sebelah kiri. Bagian kanan untuk parkir mobil. Usai memarkir, saya berjalan menuju petirtaan, melewati rumah penduduk hingga sampai di mulut jalan area petirtaan yang ditandai dengan jalan berbatu mengarah ke bawah.
Beberapa pengunjung yang tiba mengenakan busana dengan motif tradisional, semisal batik atau kebaya dan jarik. Pilihan lainnya, memakai baju hitam-hitam. Saya memilih yang kedua. Pengunjung yang baru saja datang harus mengisi daftar hadir terlebih dahulu, meski sebelumnya sudah melakukan registrasi daring. Di sini, saya menukar uang Rp25.000 dengan lima keping uang pring yang nantinya dipakai membeli makanan di area petirtaan. Kata “pring” dalam bahasa Jawa berarti bambu, karena terbuat dari bambu persegi panjang. Tak ada ketentuan khusus nominal rupiah yang ditukar. Seandainya uang pring masih sisa, nantinya bisa ditukarkan dengan rupiah saat akan pulang.
Sebelum memasuki area petirtaan, pengunjung harus melepas alas kaki. Jadi, selama acara setiap orang akan bertelanjang kaki. Usai menuntaskan urusan di meja registrasi, saya melangkah menuju area lapang. Saya mendapati sejumlah orang menunggu di depan meja dengan aneka barang dagangan yang mereka jual. Ada yang menjual dawet, jamu, cenil, sayur-mayur serta pala pendem, buah-buahan, dan alat-alat musik tradisional. Saya menuju meja paling ujung. Dua perempuan tengah bertransaksi. Mereka menukarkan beberapa uang pring dengan jajanan seperti jemblem, apem yang dibungkus daun, dan lepet.
“Mbak, saya mau ini dua lalu apem satu dan satunya lagi ini,” ucap saya kepada dua perempuan muda.
“Satunya lagi apa, Mbak? Masih sisa seribu?”
“Ini berapa, Mbak?” tanya saya dengan telunjuk tertuju ke jemblem. “Seribu.”
Dengan dibungkus daun pisang, saya mendapatkan dua lepet, satu apem, dan satu jemblem. Ada satu lagi yang saya lupa namanya (bahannya ubi kayu), saya kira nagasari ternyata bukan. Selain makanan, saya juga membeli segelas dawet senilai Rp3.000.

Tari Topeng Padepokan Mangun Dharma
Usai melalui area pasar, sambil membawa makanan, saya menuruni anak tangga yang berkerikil. Di kiri, ada bangunan terbuka yang difungsikan sebagai tempat makan dan dapur. Saya tidak berhenti di sini karena sudah banyak pengunjung dan hampir tidak menyisakan tempat.
Turun lagi, saya melihat deretan pengunjung lainnya yang duduk di tikar. Di hadapan mereka, kelompok karawitan bersiap untuk tampil. Saya pergi ke tempat duduk yang masih kosong. Di dekat saya duduk pula sekelompok penari menggunakan topeng.
Sesudah kata-kata sambutan, termasuk pengelola Petirtaan Ngawonggo Ahmad Yasin, pengunjung kemudian dihibur dengan penampilan tari topeng dari Padepokan Mangun Dharma. Orang-orang yang semula duduk di dekat saya, satu per satu berdiri untuk bersiap. Saya tidak menghitung secara pasti, sepertinya lebih dari lima penari yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kurang lebih selama lima menit mereka menari diiringi gamelan serta suara dari Ki Sholeh Adi Pramono, pemimpin padepokan. Gemerincing gelang kaki penari beradu dengan suara gamelan.
Mendapati para penari tersebut berusia muda juga sempat membuat saya terperangah. Sekadar informasi, para pemain karawitan termasuk sindennya juga masih sangat muda (ABG). Saya salut karena masih mau melestarikan seni dan budaya tradisional. Bahkan, salah satu sindennya, sebagaimana keterangan Ki Sholeh Adi Pramono, masih bersekolah di tingkat SMK. Soal suara, juga tidak perlu disangsikan. Suara sinden yang mendendangkan lagu Jawa sempat membuat saya terhanyut.
Kembali ke Alam
Sejak pertama memasuki Petirtaan Ngawonggo, saya langsung terkesan dengan nuansa alam yang menaungi. Sejauh mata memandang, pepohonan rindang beserta tanaman lainnya mendominasi pandangan. Belum lagi jalan berkerikil yang harus dilewati begitu masuk area. Berjalan tanpa alas kaki alias nyeker, menambah kesan menyatu dengan alam makin kuat. Suasana asri kompleks petirtaan juga terasa makin syahdu dengan dominasi pohon bambu.
Area Petirtaan Ngawonggo tidak hanya meliputi bagian pemandian saja. Sebelum ke sana, pengunjung bisa menikmati suasana alam pedesaan yang ada di kompleks. Berada di sini, pengunjung seolah-olah ditarik ke masa kerajaan kuno. Saya pun jadi teringat akan sinetron-sinetron kolosal yang pernah tayang di stasiun televisi swasta beberapa tahun lampau.
Seingat saya, di kompleks ada dua bangunan dengan konsep terbuka tanpa pintu. Dindingnya terbuat dari bambu yang berfungsi sebagai dapur. Bedanya, bangunan satu digunakan untuk memasak nasi dan lauk pauk, sementara satunya lagi sebagai dapur untuk membuat wedang uwuh. Di dapur terakhir ini, pengunjung bahkan bisa belajar meracik wedang.
Tepat di sebelah dapur wedang uwuh yang dibatasi gapura buatan, ada lapangan kecil yang dipakai untuk dolanan (bermain) permainan tradisional, seperti egrang, gasing, dan dakon. Alat permainan sudah tersedia dan pengunjung bisa memainkannya. Dipisahkan jalan setapak, di samping lapangan tersedia sarana MCK dan musala kecil.
Saat siang tiba, penyelenggara mempersilakan para pengunjung untuk menikmati makan siang dengan menu ndeso. Dengan piring enamel di tangan, saya mengambil nasi jagung dan sayur lodeh. Lauknya tempe dan tempe kacang goreng yang dibalur tepung. Sederhana, tetapi amat berkesan dan enak.



Sejarah Petirtaan Ngawonggo
Sekitar sejam menjelang acara berakhir, saya dan pengunjung lainnya berkesempatan mendengarkan cerita dari Ahmad Yasin mengenai Petirtaan Ngawonggo. Bisa dibilang, Ahmad Yasin adalah penduduk setempat yang mbabat alas sehingga kompleks Petirtaan Ngawonggo terbentuk. Ia memberitahu bahwa masyarakat sekitar sudah tahu keberadaan petirtaan sejak lama. Hanya saja tidak terekspos saat itu.
Kami tidak langsung menuju petirtaan. Laki-laki berpakaian hitam ini mengajak kami terlebih dahulu ke sisi kompleks. Area petirtaan berada di seberang. Ada jembatan yang menjadi penghubung dengan parit di bawahnya.
Melewati pohon-pohon bambu yang menguasai kompleks petirtaan, kami menerobos semak-semak. Ada jalan setapak. Saya berjalan dengan hati-hati mengingat di pertengahan kegiatan, telapak kaki kanan sudah terasa sakit. Ahmad Yasin memandu kami hingga hampir ujung.
“Sekarang kita bisa lihat di sana. Ada empat struktur utama kompleks petirtaan. Jadi, setiap struktur punya ragam hias atau relief yang berbeda. Ada relief ganesha, sosok penunggang kuda yang digambarkan sebagai Dewa Surya, ada juga relief meander,” ujarnya.
Ahmad Yasin melanjutkan, petirtaan ini berada di tepi parit yang ukurannya sudah melebar. Relief-relief yang ia sebutkan sudah banyak yang tak utuh karena aus, termasuk relief ganesha yang tak berbentuk lagi. Ia juga mengibaratkan empat struktur utama kompleks petirtaan berupa kolam memanjang seperti candi, menggambarkan tingkatan dari yang kecil hingga paling tinggi.
Diperkirakan petirtaan ini berasal dari sekitar abad X–XIII Masehi, saat peralihan dari Kerajaan Kediri ke Singhasari. Petirtaan memiliki arti air suci yang digunakan untuk peribadatan. Dalam bahasa Bali, petirtaan sering disebut beji yang bermakna tempat untuk mengasah diri.
Selain relief atau arca yang banyak tak berbentuk, struktur petirtaan juga tidak lengkap karena longsor. Menurut Ahmad Yasin, panjang petirtaan mencapai kurang lebih 150 meter, terimpit Sungai Manten dan sungai irigasi. Di petirtaan juga terdapat lingga dan yoni yang dalam ajaran Hindu melambangkan Dewa Siwa dan Dewi Parwati.
Ahmad Yasin juga bercerita, saat SD menanam selada air di kolam-kolam petirtaan bersama ibunya. Ia sempat bertanya kepada sang ibu soal siapa yang membangun petirtaan. Ibunya menjawab, orang-orang kuno. Bahkan ia sempat terperosok saat mencari sayur pakis lalu mendapati relief.
Bertahun-tahun tidak ke petirtaan, selanjutnya pada 2017, Ahmad Yasin menengok petirtaan. Oleh teman-temannya, situs ini diunggah ke Facebook lalu mendapat tanggapan Balai Pelestarian Budaya yang kemudian melakukan ekskavasi dan zonasi.
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.
Dewi Sartika, ibu rumah tangga yang tinggal di Malang. Menyukai hal-hal yang berhubungan dengan sejarah dan menulis tulisan "historical fiction". Menjadi anggota komunitas literasi serta telah menghasilkan sejumlah antologi.