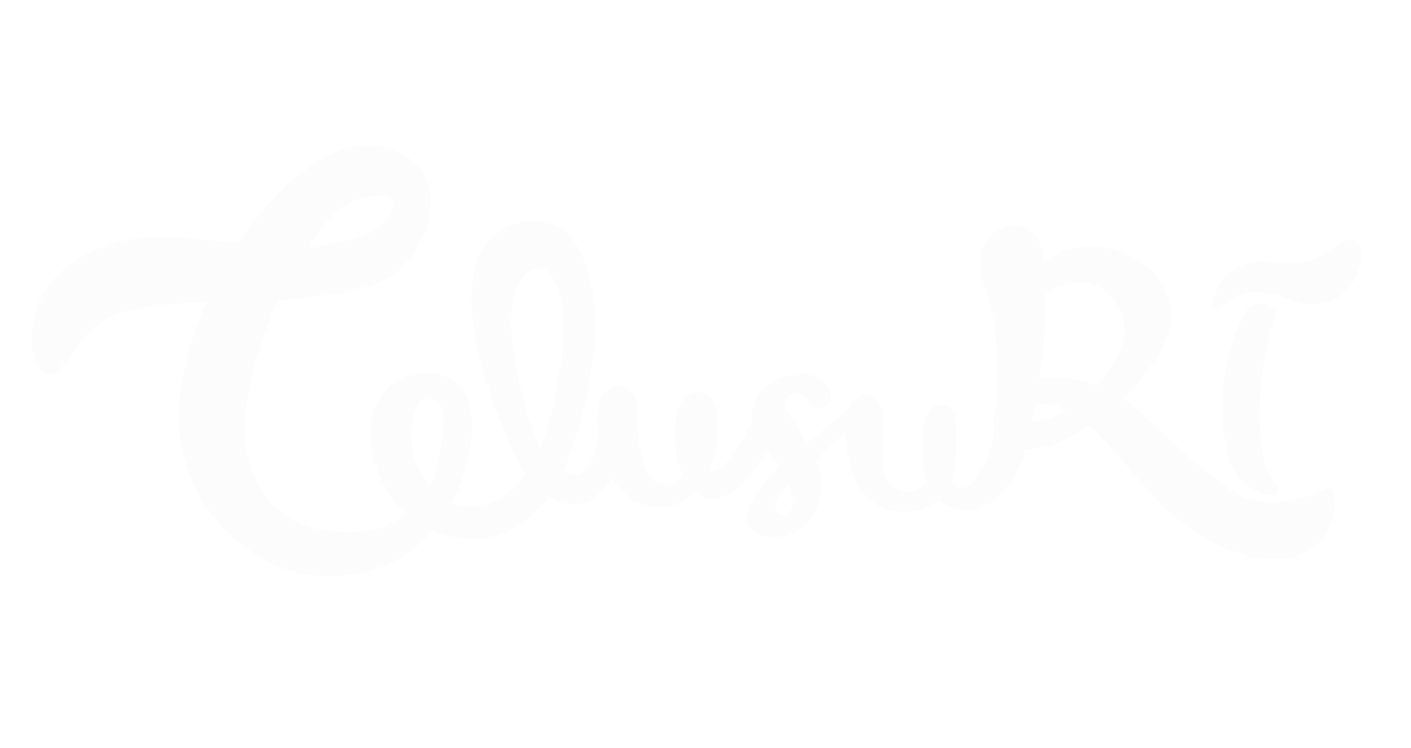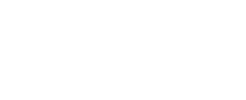Siang itu, saya melangkah pelan menyusuri Liang Galang. Udara sejuk menyelimuti ruang gua, kontras dengan hawa panas yang sedari tadi saya rasakan di luar sana. Deni, Wakil Ketua Pokdarwis Liang Bua, berada tak jauh dari tempat saya berdiri.
Obrolan kami kemudian perlahan memecah kesunyian. Bermula dari pertanyaan kecil yang saya sampaikan, Deni mulai menjelaskan banyak hal tentang destinasi yang terletak di Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Manggarai ini.

Tempat Ritual Adat
“Jadi, gua ini dulunya dijadikan tempat untuk melaksanakan ritual adat, karena dipercaya bahwa gua ini bisa mengabulkan atau memberikan apa yang kita minta,” jelasnya tentang sejarah Liang Galang. Konon, ritual adat di Liang Galang ditujukan untuk berbagai keperluan, seperti meminta keturunan, jodoh, atau pekerjaan yang bagus, dengan dipandu oleh seorang tukang torok/tudak.
“Di depan gua situ ada semacam altar,” jelas Deni sembari menunjuk ke luar, ke arah pintu gua. Batu menyerupai altar yang ia maksud memang terletak di pintu masuk Liang Galang, dan menjadi titik awal prosesi.
Dalam prosesnya, setiap orang yang akan melaksanakan ritual, harus meletakkan sebutir telur ayam kampung pada lubang altar batu tersebut. Tujuannya untuk meminta kepada nenek moyang agar dibukakan pintu, sehingga bisa masuk dan melakukan ritual adat di dalamnya.
Ritual inti akan berpusat di galang. Dalam bahasa Manggarai, galang berarti bak mandi atau tempat makanan babi ternak dalam arti yang lain. Keberadaan galang ini mendasari nama Liang Galang.
Ada empat galang yang terdapat di gua. Masing-masing memiliki fungsi penting dalam ritual masyarakat zaman dahulu. Satu galang berukuran paling besar dikhususkan bagi laki-laki, dengan satu galang yang sedikit lebih kecil untuk perempuan. Sementara itu, dua galang lainnya masing-masing bagi anak pertama dan anak kedua.
Selain telur ayam kampung, syarat lain dalam ritual ini adalah menyiapkan seekor ayam jantan putih, yang nantinya akan disembelih di samping galang. Pemandu kemudian akan mengoleskan darah ayam tersebut pada dahi laki-laki atau perempuan yang mengikuti ritual.
Selanjutnya, pemandu juga mengambil air dari galang menggunakan gayung tradisional yang terbuat dari tempurung kelapa (leke nio). Air ini kemudian dituangkan di kepala peserta ritual, yang ditujukan untuk menyucikan hati dan jiwa dari berbagai hal negatif.
Dalam hal ini, jika ritual dilaksanakan untuk laki-laki, maka pemandu akan mengambil air dari galang paling besar yang khusus untuk laki-laki. Begitu pula sebaliknya.
“Setelah semua proses ritual dilaksanakan, dan membawa hasil sesuai yang diharapkan, orang bersangkutan juga harus kembali ke Liang Galang untuk melakukan ritual adat yang sama,” tutup Deni tenang.


Simbol dari Pintu Gua
Beberapa hari sebelum ke sini, saya pernah diceritakan perihal keunikan dua pintu masuknya, yang menyerupai kelamin laki-laki dan perempuan. Hari itu saya bisa melihat secara langsung, terutama dari dalam gua. Secara budaya, ketika melaksanakan ritual adat di Liang Galang, seseorang harus masuk melalui pintu sesuai jenis kelaminnya.
Dua pintu gua tersebut dianggap berkaitan erat dengan budaya umum masyarakat Manggarai, khususnya penduduk penduduk sekitar. Mengutip penjelasan Kae Tigor, Ketua Pokdarwis Liang Bua, pintu gua turut mencerminkan keteraturan peran secara adat. Dalam hal ini, laki-laki memimpin, perempuan mengikuti, tetapi keduanya saling melengkapi.
Selain keunikan pintu gua dan keberadaan beberapa galang, terdapat juga batu kristal yang berkilau, gua kecil di dalam gua, serta beberapa batu yang menyerupai manusia. Salah satunya terdapat di bagian depan gua, berupa batu yang menyerupai seorang ibu yang menggendong dua orang anak di depan dan belakang. Ada pula sekitar 10 batu lain yang tersebar di bagian bawah gua, tepatnya di bagian depan galang.
Letak Liang Galang yang berdekatan dengan Liang Bua, juga dikisahkan memiliki hubungan yang menarik. Deni menuturkan, menurut cerita zaman dahulu, Homo floresiensis yang mendiami Liang Bua kerap datang maupun singgah ke Liang Galang untuk menyucikan diri, membersihkan hasil buruan, atau sekadar beristirahat.

Pengalaman Wisata di Liang Galang
Sebagai destinasi wisata, Liang Galang menawarkan beragam pengalaman wisata yang dikemas penuh kehangatan. Hari itu, kedatangan kami disambut ramah oleh anggota Pokdarwis Liang Bua dan masyarakat setempat.
Sebuah mbaru tiba, dengan desain bangunan menyerupai mbaru gendang (rumah adat Manggarai), menjadi tempat penerimaan tamu. Di sana, setiap pengunjung dipakaikan kain tenun dan selendang songke. Laki-laki juga mengenakan songkok (topi adat), sementara perempuan memakai retu (hiasan kepala wanita).
Kopi Manggarai pun disuguhkan bersama olahan pangan lokal, seperti teko (ubi talas), latung bombo (bubur jagung), hingga kue serabe. Di dekat kami, beberapa rombongan wisatawan mancanegara tampak menikmati hidangan lokal tersebut, sembari menikmati pemandangan persawahan yang terbentang luas di depan sana.
Di halaman, tepat di depan mbaru tiba, permainan tradisional rangkuk alu berlangsung. Dua bilah bambu beradu ritmis, sementara pemain melompat masuk-keluar dengan lincah. Beberapa dari kami tak tahan untuk ikut mencoba, lalu segera larut dalam kebersamaan hari itu.

Liang Bua sebagai Situs Perabadan
Jelang sore, Deni memandu kami menuju Liang Bua. Sebelum memasuki gua bersejarah itu, kami lebih dulu menyinggahi museum untuk menggali informasi.
Dari museum, kami lalu melangkah menuju Liang Bua. Di depan mulut gua yang megah, saya terdiam. Tempat yang sebelumnya hanya saya kenal lewat buku kini terhampar nyata di hadapan saya.
Sembari melangkah masuk, Deni banyak bercerita tentang potensi wisata dan posisi penting Liang Bua dalam sejarah. Terutama soal penemuan Homo floresiensis.
Deni menyampaikan fakta lain yang baru saya dengar, bahkan mungkin belum banyak diketahui publik. Katanya, pada masa lampau, Liang Bua juga pernah digunakan sebagai tempat belajar (sekolah). Lantas saya menelusuri beberapa literatur, sampai menemukan catatan sejarah yang membenarkan penjelasan Deni tersebut, yang terjadi sekitar tahun 1946–1949.
Cerita tentang Liang Bua menjadi tonggak penting dalam penelitian dan penemuan Homo floresiensis. Pada kisaran tahun itu, seorang pastor bernama Theodore Verhoeven mendatangi Liang Bua pada 1950-an (Jatmiko, 2015).
Ia kemudian meninjau situs ini dan menemukan indikator temuan arkeologis berupa pecahan tembikar dan serpih-serpih batu di permukaan lantai Liang Bua. Temuan ini kemudian didalami melalui penelitian pada 1965, yang kemudian menemukan lebih banyak bukti dan catatan sejarah penting lainnya.


Selanjutnya penelitian diteruskan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional hingga 1989. Dalam kurun waktu tersebut, ditemukan lebih banyak bukti yang memperbanyak informasi terkait jejak sejarah masa lalu di Liang Bua.
Setelah 1989, penelitian berlanjut lewat kerja sama peneliti Puslitbang Arkeologi Nasional dengan beberapa peneliti dari universitas luar negeri, termasuk University of New England pada 2001–2004. Periode ini jugalah yang menjadi babak penting dalam sejarah penemuan Homo floresiensis di Liang Bua.
Pada kisaran 2003–2004, mereka menemukan rangka manusia, yang kemudian diberi nama Homo floresiensis atau manusia Flores. Penelitian dan penggalian ini menemukan beberapa unsur penting, seperti sebuah rangka manusia yang tergolong lengkap (dengan beberapa fragmen tulang dari individu lain), unsur budayanya (alat-alat litik), serta sisa tulang fauna endemik (Stegodon, komodo, sejenis tikus, dan burung besar).
Menariknya, temuan dan hasil analisis terhadap jenis manusia purba ini, membuat Homo floresiensis dijuluki “hobbit”. Sebab, tingginya hanya sekitar 106 cm serta bobot tubuh sekitar 27,5 kg.
Liang Bua dan daerah sekitarnya, sejauh yang saya amati, terbilang daerah yang subur. Kawasan persawahan dan perkebunannya asri. Selain itu, tak jauh dari sana, terdapat juga Sungai Wae Racang yang mengalir cukup deras.
Liang Bua disebut memiliki potensi besar sebagai ruang hidup yang ideal bagi manusia purba untuk menetap. Hal ini tidak terlepas dari kondisinya yang sejuk, sirkulasi udara yang baik, cahaya matahari yang cukup, serta didukung pula dengan permukaan lantai gua yang luas dan datar. Di sisi lain, keberadaan hutan dan adanya aliran sungai di sekitarnya, turut menunjang ketersediaan sumber kebutuhan hidup bagi manusia purba pada zaman dahulu (Jatmiko, 2015).
Perjalanan ini membuat saya membawa pulang banyak informasi dan pengetahuan baru. Seiring gelap yang kian menjelang, saya dan rekan-rekan seperjalanan dari Ruteng akhirnya pamit pulang. Sembari memacu kendaraan menyusul rombongan, saya kembali teringat sebuah tulisan di ruangan museum. A message from Liang Bua: Life from the past for a better future.
Referensi:
Jatmiko. (2015). Flores dalam Lintas Budaya Prasejarah di Indonesia Timur. Yogyakarta: Penerbit Galangpress.
Jejaring Desa Wisata. Desa Wisata Liang Bua. Kementerian Pariwisata, https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/liang_bua.
Pariwisata Kabupaten Manggarai. Liang Bua. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai, https://pariwisata.manggaraikab.go.id/destinasi/liang-bua/.
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.
Oswald Kosfraedi, saat ini berdomisili di Kupang. Gemar mengisi waktu luang dengan menulis dan mendengarkan lagu karya seorang musisi yang menginspirasi saya dalam menulis.