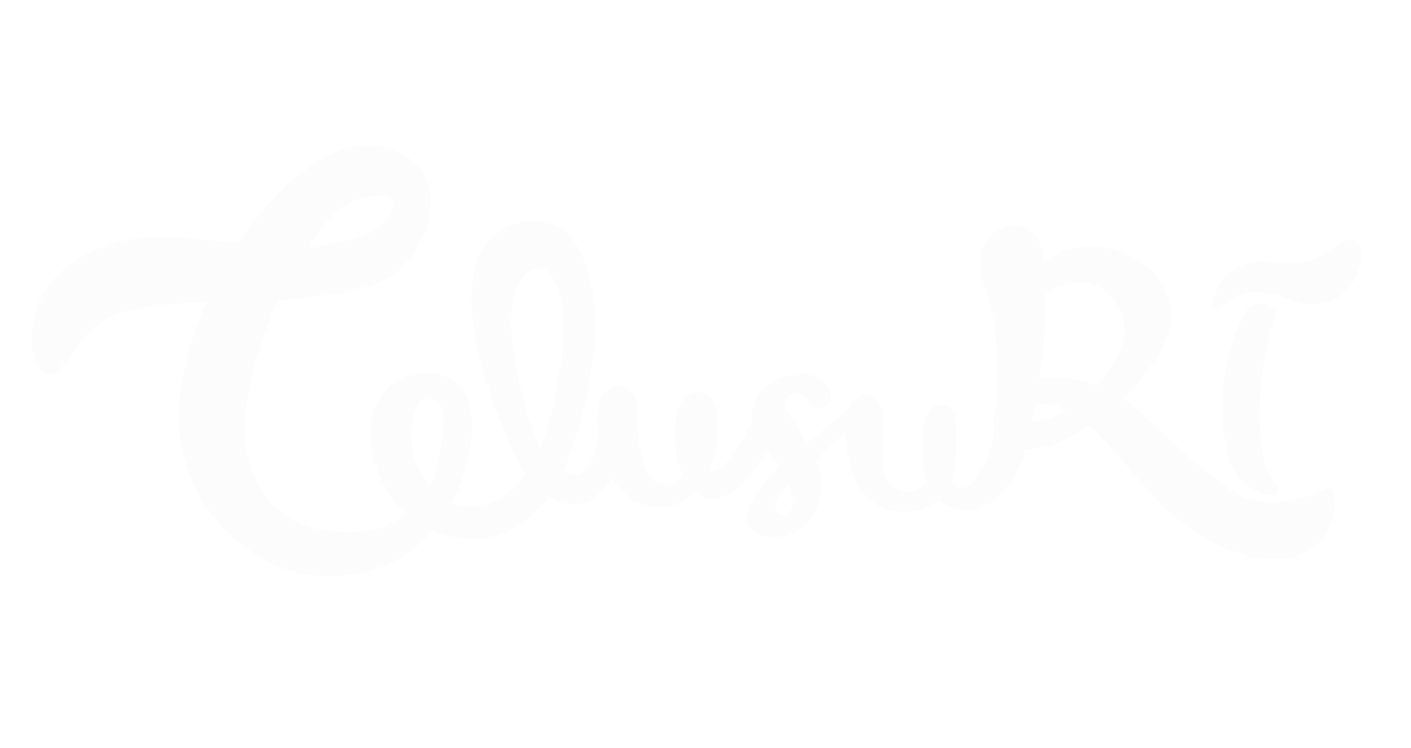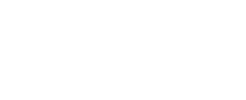Perjalanan saya menuju Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dimulai dengan kapal nelayan berukuran lebih 30 GT. Kapal ini sudah menempuh perjalanan panjang sejak dari Pulau Sapeken, Madura, mengantarkan saya menyelesaikan sebuah penugasan. Tugas itu selesai, tapi perjalanan belum.
Arah kapal kemudian diputar ke timur, menembus lautan yang birunya seolah tak ada ujung, menuju sebuah nama yang selama ini hanya singgah di telinga saya. Pulau Sailus, Kecamatan Liukang Tangaya, salah satu daerah pesisir dan pulau terluar Provinsi Sulawesi Selatan.
Saya datang bukan sekadar singgah. Ada pekerjaan yang membawa saya ke sini, sebuah kesempatan untuk mengenal lebih dalam tentang wajah sosial, budaya, kesehatan masyarakat, dan ekonomi kepulauan. Bagi saya, tugas ini seperti membuka lembar baru sehingga tidak sekadar menambah catatan lapangan, tapi juga pengalaman batin.
Pagi harinya, kapal kami akhirnya mendekati tujuan. Garis pantai Pulau Sailus mulai terlihat. Matahari belum tinggi, tetapi cahaya keemasannya memantul di permukaan air. Laut sedang surut sehingga kapal tak bisa bersandar di dermaga kayu. Kami harus berpindah ke perahu (boat) kecil untuk benar-benar bisa menjejak pulau. Dari geladak yang luas ke ruang sempit perahu kayu, saya merasakan perpindahan lain dari hiruk mesin besar ke dengungan pelan motor tempel, dari laut lepas ke sebuah pulau kecil yang segera saya jejaki.


Kondisi permukiman Pulau Sailus. Tergambar perjuangan masyarakat yang bertahan hidup di tengah keterbatasan/Adipatra Kenaro Wicaksana
Pulau yang Hidup di antara Keterbatasan
Begitu menginjak daratan, suasana yang saya temui jauh dari keramaian kota. Pulau Sailus adalah pulau yang hidup dengan ritme keterbatasan. Resmi masuk kategori pulau terluar, masyarakat di sini sudah terbiasa dengan listrik yang hanya menyala enam jam setiap malam.
Ketika malam turun, bunyi genset menjadi latar belakang kehidupan: mengisi ruang kosong, menggantikan sunyi, sekaligus menandai batas aktivitas. Akses telekomunikasi pun tampak sederhana. Hanya satu provide XL yang bertahan di sini. Itu pun sinyalnya tidak selalu setia.
Saya sempat berpikir, di pulau ini kata akses punya arti lain. Ini bukan diukur dari jarak tempuh atau waktu perjalanan, melainkan dari kemampuan masyarakat untuk tetap bertahan dengan kondisi yang seadanya.
“Aksesnya bukan soal jauh atau dekat,” kata Pak Rasyid, nelayan berusia 50 tahun yang saya temui di beranda rumahnya. “Tapi soal apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang ada.”
Pernyataan itu segera terasa nyata. Bahkan di Pulau Sailus, pasar tidak tersedia. Untuk kebutuhan sayur-mayur, masyarakat hanya mengandalkan hasil kebun seadanya atau pedagang keliling yang mendorong gerobak dari rumah ke rumah. Daging segar hampir mustahil didapatkan.
Karena itulah, ikan, terutama ikan layang, menjadi tumpuan utama. Dari laut sebagian besar kebutuhan hidup mereka ditopang, bukan hanya soal pangan, melainkan juga identitas. Tak heran, laut adalah poros kehidupan masyarakat Sailus.
Mayoritas masyarakat Sailus adalah etnis Mandar. Aktivitas sehari-hari mereka sebagai nelayan ditentukan oleh angin, arus, dan cahaya bulan. Laut bukan sekadar ruang kerja, melainkan sahabat yang harus dipahami, guru yang harus dihormati, dan kitab yang terus dibaca ulang dari generasi ke generasi.
Relevansi Tiga Falsafah Hidup Etnis Bugis
Di titik inilah saya mulai memahami bahwa kehidupan masyarakat kepulauan tidak bisa dilepaskan dari pandangan hidup yang mereka warisi. Setiap kali berbincang dengan warga, baik di tepi pantai maupun di beranda rumah panggung, selalu ada semacam keyakinan yang mereka ucapkan berulang. Hidup harus dijalani dengan kesadaran bahwa laut memberi sekaligus mengambil.
Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan anak-anak berlarian di tepi pantai, saya berbincang dengan seorang bapak tua beretnis Bugis. Ia sedang memperbaiki jaringnya.
Dari mulutnya saya mendengar tiga kata yang kemudian menjadi kunci memahami bagaimana orang-orang Sailus dan etnis Bugis di kepulauan ini memaknai hidup: Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi.
Sipakatau, katanya, adalah sikap saling menghargai dan memanusiakan sesama. Saya melihat wujudnya dalam kebiasaan sederhana warga yang tak segan berbagi hasil laut.
Ikan layang, yang menjadi pangan utama mereka, kerap dibagikan ke sesama tetangga. Ketika ada yang tidak sempat melaut, mereka tetap bisa makan berkat solidaritas ini. Bahkan, pangan lokal seperti sabal, nasi dicampur kelapa parut sangrai, menjadi pengingat bahwa bertahan hidup di kepulauan adalah soal kebersamaan.

Sipakainge, lanjutnya, berarti saling mengingatkan. Dalam sebuah obrolan lain, seorang pemuda bercerita bahwa sering kali orang tua di Sailus mengingatkan mereka untuk berhati-hati saat melaut. “Kalau sudah ada tanda angin kencang, jangan nekat,” katanya menirukan pesan bapaknya.
Bagi mereka, saling mengingatkan bukan hanya soal keselamatan di laut, melainkan juga soal hidup bersama. Saya bahkan teringat ketika seorang ibu menegur remaja yang hendak membuang sampah plastik ke laut. “Nak, jangan buang di situ. Laut ini tempat kita cari makan.” Kalimat sederhana ini menjadi bentuk nyata jika Sipakainge mengingatkan dengan kasih, agar generasi berikutnya tetap bisa hidup dari laut yang sama.
Terakhir, Sipakalebbi, yang berarti menjaga martabat dan tidak merampas hak orang lain. Nilai ini saya temukan dalam harapan masyarakat terhadap pendidikan anak-anak mereka. Sekitar 30 persen anak muda Sailus sudah bisa kuliah dengan bantuan beasiswa, banyak di antaranya memilih bidang kesehatan dan pendidikan. Ada semacam kesadaran bahwa martabat orang Bugis di Pulau Sailus hanya bisa dijaga bila generasi muda juga turut andil hingga diberi kesempatan untuk belajar lebih tinggi, bukan dibiarkan terjebak dalam keterbatasan.
Dari cerita-cerita itu, saya sadar bahwa falsafah Bugis bukan hanya warisan lisan yang tinggal slogan. Ia hidup dalam dapur-dapur sederhana yang memasak ikan layang, dalam kritik warga soal layanan kesehatan yang masih timpang, hingga dalam tekad orang tua menyekolahkan anak mereka ke perguruan tinggi.
Laut mungkin memberi sekaligus mengambil. Namun, falsafah hidup inilah yang membuat orang Sailus tetap berdiri tegar menghadapi ombak kehidupan.


Kapal-kapal nelayan Sailus yang berlabuh di pantai, potret harapan masyarakat yang bertumpu pada laut/Adipatra Kenaro Wicaksana
Refleksi dari Pulau Sailus
Melihat kehidupan Sailus membuat saya berpikir. Meski keterbatasan masih banyak, masyarakatnya punya modal sosial yang luar biasa. Mereka memiliki filosofi hidup yang jika benar-benar dipraktikkan, bisa menjadi benteng dari intoleransi dan keretakan sosial.
Saya membayangkan, jika falsafah ini dibawa ke ruang-ruang lebih luas ke kota besar, yang sering kali kering oleh kompetisi. Mungkin, kita akan lebih mudah saling menghargai, saling mengingatkan, dan saling memuliakan.
Ketika perahu kecil membawa saya meninggalkan Pulau Sailus, saya sempat menoleh. Pangkajene tampak kecil dari kejauhan, dikelilingi laut biru yang nyaris tanpa ujung. Namun, bagi saya, pulau itu justru memperluas pandangan bahwa perjalanan bukan sekadar soal jarak yang ditempuh, melainkan tentang bagaimana kita menemukan cara baru memahami manusia dan kehidupan.
Bahkan dalam sesi menjejak dan menyimak, saya paham bahwa kehidupan bukan hanya tentang bertahan di tengah keterbatasan, tapi juga tentang bagaimana kita menautkan diri pada nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur. Laut memang memberi sekaligus mengambil; tetapi selama ada falsafah hidup yang dijaga, masyarakat akan tetap menemukan jalannya.
Perjalanan ke Pangkajene tidak hanya memberi catatan tentang keterbatasan infrastruktur, tetapi juga pelajaran tentang kelapangan hati. Di tengah keterbatasan listrik, sinyal, dan fasilitas publik, masyarakat tetap punya kekuatan: filosofi hidup yang membuat mereka bertahan dan tetap manusiawi.
Dan mungkin, di sinilah esensi perjalanan itu sendiri. Bukan sekadar melihat laut, pulau, atau nelayan yang berangkat pagi, melainkan belajar dari masyarakat kecil di pulau terluar yang mampu memberi jawaban sederhana untuk pertanyaan besar: bagaimana kita bisa hidup bersama tanpa kehilangan rasa kemanusiaan.
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.
Lulusan S1 Kesehatan Masyarakat dengan Ilmu Terapan Kesehatan Lingkungan, Sesekali menjaga lingkungan agar tetap sehat, sambil mencoba untuk tetap ingat kapan terakhir kali menyiram tanaman di rumah.