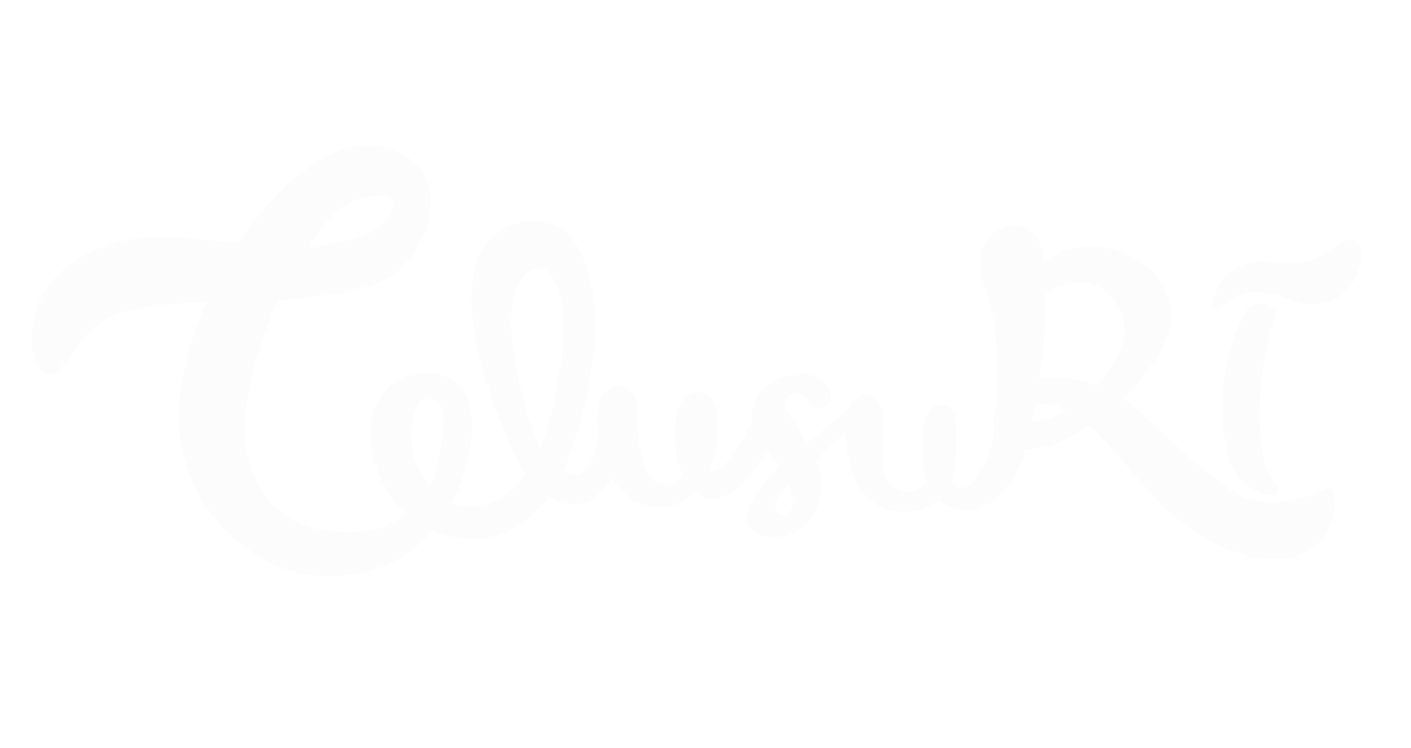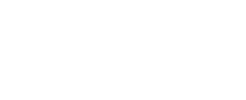Kangean, gugusan kepulauan di timur jauh Madura. Terdiri dari puluhan pulau, Kangean sebagai “induknya” senantiasa hadir sebagai kepanjangan tangan Madura.
Bagaimanapun, begitulah definisi paling umum hingga kini. Seperti penamaan, Kangean disebut tak terlihat ketika musim pasang datang, sehingga Madura menyebutnya ka-aengan, terkena air.
Betapa tak masuk akal membayangkan pulau yang sepanjang tubuhnya dijalari bukit-bukit panjang berbatu, tempat pohon-pohon raksasa bersemayam sebagai hutan purba dapat tersapu gerak laku bulan yang menarik air laut ke bibir pantai. Namun, begitulah Kangean (Timur) didefinisikan oleh Madura (Barat).
Seolah tak cukup dengan ka-aengan, Kangean kemudian disebut sebagai tempat para bromocorah-pembangkang kerajaan akan dikumpul-satukan sebagai orang buangan. Kangean adalah Pulau Buru bagi kemasyhuran keraton yang megah nun jauh di Sumenep sana. Karenanya, dalam versi sejarah paling umum, Kangean dihuni kalangan paling buruk dari kelas-kelas sosial yang pernah ada.
Keadaan ini harus diperiksa kembali. Pasalnya, gugusan Kepulauan Kangean merupakan rumah bagi para suku bangsa yang berasal dari berbagai penjuru mata angin, bukan cuma mereka yang “dibuang” dari Madura.

Jika ditelusuri, mereka yang berasal dari Jawa, Melayu, Bali, Bugis, Bajo, Mandar, dan Sunda Kecil telah lebih dulu menegaskan keberadaannya di Kepulauan Kangean. Tandanya macam-macam, antara lain produk kebudayaan yang muncul, cara hidup, bahasa, kesenian, dan urusan hajat hidup manusia lainnya.
“Sulit mengharapkan keluhuran dari setiap manusia di pulau ini mengingat penghuninya bukan berasal dari kalangan terbaik,” ujar F. Schelfhorst, seorang misionaris Belanda, dalam laporan misinya: Mededeelingen over Kangean.
Interpretasi serampangan terhadap manusia Kangean, sebagaimana dilakukan Schelfhorst, sedikit banyak tentulah berangkat dari narasi umum yang tak pernah diperiksa kembali keabsahannya. Seolah sejarah manusia Kangean memang cuma tentang raja-raja yang menghukum anak nakalnya untuk dibuang di sana.
Karena sejak mula tulisan ini menyangsikan istilah ka-aengan dalam penamaan Kangean, maka merasa perlu membeberkan beragam versi tentang penamaannya.

Kangayan, Kahyangan, Kakaraengang
Musahur (2025) menyebut kemungkinan lain penamaan Pulau Kangean (hingga kini versi itu tak populer). Kabarnya, Kangean sebagai nama diilhami sebuah desa yang dipercaya menjadi permukiman mula-mula di pulau itu: Kangayan.
Kangayan terletak di punggungan bukit paling timur pulau. Tempat air menyembul dari balik tanah subur, hutan-hutan rimbun, hingga sepasang mata telanjang manusia dapat meluaskan pandangan ke laut jauh.
Paling tidak, tiga alasan itu dapat menguatkan posisi Kangayan sebagai “tempat yang dijanjikan” sebagai rumah bagi banyak manusia Kangean mula-mula. Air, hutan, dan letak geografis di ketinggian agar terus awas pada setiap bahaya yang mungkin datang. Selanjutnya, dari mana ‘Kangayan’ sebagai nama berasal? Ada dua kemungkinan paling kuat.
Sebuah bundel manuskrip yang memuat sisa-sisa khazanah sastra Kangean telah menuntun hipotesis awal. Ihwal keberadaan dua suku yang dapat ditengarai paling kuat untuk menentukan muasal istilah Kangayan, sebelum menjadi Kangean.
Dua suku itu adalah Jawa dan suku-suku yang berasal dari Sulawesi (Bugis, Bajo, Mandar). Salah satu genre sastra Kangean paling penting untuk dibahas dan diberi tempat adalah sastra bermuatan sabda-nasihat dari orang-orang atau tokoh yang dianggap penting oleh masyarakatnya.
Kenapa sastra Kangean penting? Sebab, ia memuat informasi ihwal tokoh penting itu sendiri, khususnya soal asal keberadaannya. Hal ini perlu diurai sejak awal guna melihat posisi dan keberadaan Kangean, serta keterkaitannya dengan berbagai kawasan di sepanjang pulau-pulau Nusantara.

Untuk konteks Kangean, sastra semacam ini biasanya bicara ihwal sabda-nasihat yang disampaikan oleh tokoh keturunan Sulawesi. Misalnya, Rato Daeng Tjokro Bangkandhana Paq Dhalima; atau kisah Jawa macam Dewi Rengganes hingga Radhin Djokomoerko.
Keberadaan sastra Kangean menerangkan keberadaan serta posisi dua suku tersebut bagi masyarakat di Kangean. Misalnya, kenapa mereka dianggap penting sehingga mesti ditimbang segala sabda-nasihatnya. Posisinya sebagai tokoh penting ditengarai sebagai suku-suku awal yang dapat dianggap dominan dan menentukan terbentuknya jalinan kolektif antarmasyarakat, termasuk soal pemberian nama pulau.
Kangayan, jika ditilik dari suku Jawa, dekat dengan istilah kahyangan. Hal ini diperkuat dengan penemuan sebuah peta yang menyebut ‘kayangan’ sebagai nama lokasi permukiman masyarakat di Desa Kangayan. Istilah ‘kangayan’ bukan tidak mungkin diserap dari kahyangan (bahasa Jawa Kuno), merujuk kepada tempat tinggi di mana Hyang bersemayam.
Selanjutnya, jika hendak ditilik dari suku bangsa Sulawesi, istilah kangayan mungkin saja diadopsi dari bahasa Makassar, kakaraengang, ke-karaeng-an (kata dasar karaeng). Keberadaan suku-suku Sulawesi hingga kini masih tetap eksis di Kangean, tetap mempertahankan bahasa ibunya, dan memiliki jumlah yang cukup besar.


Bekisar Kangean sebagai Simbol Budaya
Bicara Kangean rasanya tidak bisa melewatkan “ayam” bekisar. Bekisar dihasilkan dari persilangan antara ayam hutan hijau jantan dan ayam kampung betina. Kini, bekisar merupakan fauna identitas Jawa Timur. Bagaimana sebetulnya posisi bekisar bagi masyarakat Kangean?
Bertahun-tahun silam masyarakat Kangean telah mengawinkan ayam hutan hijau dengan ayam kampung. Keberadaan bekisar bagi masyarakat pulau itu mestinya perlu dipahami lebih. Misalnya, pertanyaan soal apa yang “mengilhami” orang-orang Kangean untuk mengawinkan dua spesies berlainan, yang kemudian menghadirkan jenis baru dan sangat berbeda?
Bagi masyarakat Kangean sendiri, cerita-cerita muasal bekisar hadir dalam banyak versi. Salah satunya ialah karena permukiman mula-mula pulau itu terletak di Kangayan yang dilingkupi hutan. Artinya, perkawinan ayam hutan hijau dengan ayam kampung yang dipelihara masyarakat Kangean terjadi secara alamiah.
Selain itu, terdapat dua versi lain ihwal bekisar di Kangean. Keduanya menyebut perkawinan ayam hutan dengan ayam kampung disengaja oleh manusia. Sayangnya cerita berhenti di sana, tak pernah sampai pada pembahasan motif melakukan kawin silang. Artinya, dalam versi mana pun bekisar cuma dibahas sejarah kemunculannya, bukan kenapa ia “dimunculkan”.
Pandangan paling berpengaruh dan kontroversial dalam antropologi di masa sekarang ini adalah pemikiran Claude Levi-Strauss, tokoh pendekatan analisis kebudayaan Strukturalisme Prancis. Jika pandangan strukturalisme sebelumnya (Radcliffe-Brown, misalnya) fokus pada elemen-elemen masyarakat yang berfungsi sebagai sistem, maka Levi-Strauss lebih berkonsentrasi pada asal usul sistem itu sendiri.
Levi-Strauss memandang kebudayaan manusia, yang dinyatakan dalam kesenian, upacara-upacara, dan pola kehidupan sehari-hari sebagai perwakilan lahiriah dari struktur pikiran manusia. Lebih jauh, interpretasi Levi-Strauss tentang gejala kebudayaan berkonsentrasi pada kognitif masyarakat primitif, yakni cara-cara manusia memandang hal-ihwal di dunia sekitarnya atau menggolongkan hal-hal itu.
Kelompok-kelompok manusia yang mempunyai teknologi primitif sekalipun telah merumuskan cara-cara klasifikasi tumbuhan dan binatang. Bukan melulu karena maksud-maksud praktis, melainkan juga kebutuhan akan aktivitas intelektual. Pun soal keberadaan bekisar bagi masyarakat Kangean, ia merupakan aktivitas intelektual. Maka menjadi penting membahas motif keberadaannya, bukan cuma versi sejarah di balik kemunculannya.
Berangkat dari pikiran-pikiran Levi-Strauss, untuk kali pertama bekisar akan disebut sebagai aktivitas intelektual. Kemunculannya bukan semata kebetulan, melainkan disengaja oleh manusia Kangean. Tapi kenapa?
Masyarakat Kangean begitu majemuk. Hingga kini berbagai suku menegaskan jejaknya di sepanjang kepulauan. Musahur merekam satu energi kolektif masyarakat antarsuku untuk menegaskan diri sebagai satu bangsa baru, kelak nenek moyang Kangean dari suku-suku heterogen itu bakal beranak-pinak menjadi suku Kangean.
“Kita sama, kita senasib. Buat apa bersuku-suku? Sangat bijak kalau kita menjadi satu suku di pulau kita ini, yakni Suku Kangean.” (Musahur, 2024).


Alat menirukan suara ayam hutan (kiri) dan bagaimana alat itu dimainkan/Farhan Naufal
Bisakah posisi bekisar ditimbang lebih jauh? Bahwa bekisar tak kebetulan tercipta, tetapi juga kemegahan simbol budaya yang memuat satu pernyataan ke-aku-an masyarakat Kangean. Melalui simbol-simbol budaya masyarakat mengekspresikan solidaritas, menciptakan batasan, dan terlibat dalam memori kolektif, yang menyoroti signifikansinya dalam membentuk dinamika sosial.
Simbol budaya merupakan elemen penting masyarakat. Ia mewakili makna, nilai, dan kepercayaan bersama di antara anggota suatu kelompok. Simbol-simbol ini membantu individu berkomunikasi dan memperkuat identitas mereka dalam suatu budaya. Proses sosialisasi memainkan peran penting dalam mengajarkan simbol-simbol yang seringnya sangat terkait dengan aspek budaya material (objek fisik) dan nonmaterial (nilai, norma).
Ketika suku Kangean diumumkan, tanggal juga suku-suku lain yang membentuk suku Kangean itu. Konsep tersebut sama dengan bekisar yang dalam tulisan ini disebut sebagai simbol budaya. Tak peduli ia berasal dari kawin-mawin ayam hutan hijau dengan ayam kampung, ketika telur menetas dan bekisar melengkingkan cukirnya, ia sama sekali berbeda. Bukan ayam hutan hijau atau ayam kampung lagi; sepenuhnya bekisar sebagai entitas, spesies, dan makhluk baru.
Sejak awal, cukir, bunyi bekisar itu, adalah teriakan panjang ke berbagai penjuru bahwa suku bangsa baru telah lahir dari campur-baur kelompok manusia Jawa, Sulawesi, serta pelbagai kolektif lain. Suku Kangean telah dilahirkan, bekisar simbol utamanya.
Referensi:
Djojoprajitno, S. (2022). Pulau Kangean dalam Lintasan Tiga Zaman. Indis: Surabaya.
Musahur. (2024). Kangean Selayang Pandang. Sumenep: Komunitas Pencinta Buku Kangean.
Ihromi, T.O. (1980). Pokok-pokok Antropologi Budaya. Jakarta: Gramedia.
Foto sampul: Persiapan warga Pulau Kangean sebelum menangkap ayam hutan (Farhan Naufal)
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.
Syauqi Khaikal Zulkarnain, lahir di Kangean, berkegiatan di Yogyakarta. Alumni Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan. Kini memilih fokus untuk aktif menghimpun dan mendokumentasikan sisa-sisa khazanah kebudayaan manusia di kampung halamannya.