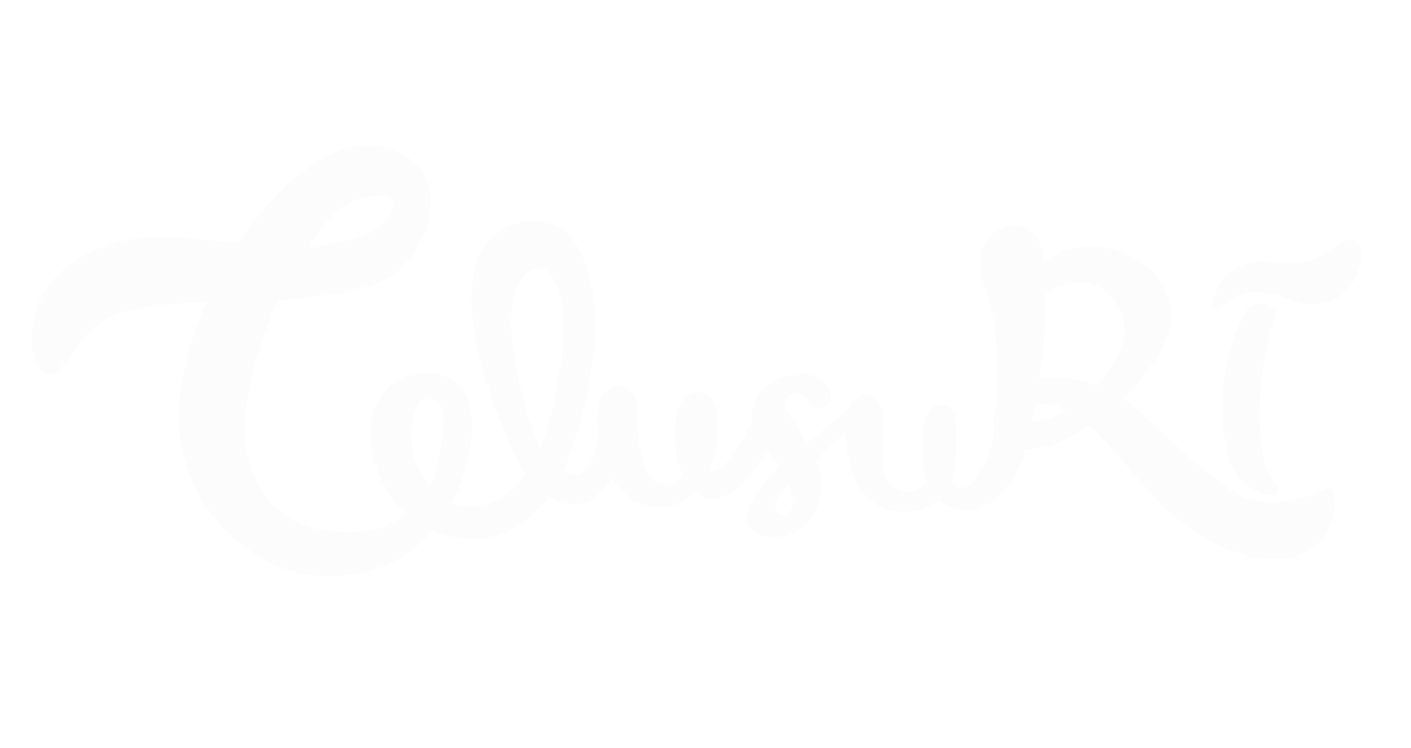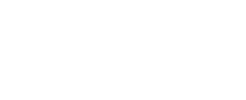Di ujung muara Sungai Selapan, masyarakat pesisir jatuh bangun bertahun-tahun untuk bertahan hidup. Alam jadi sasaran demi menjaga asap dapur mengepul. Namun, di tengah tantangan geografis dan sosial-ekonomi, kolaborasi lintas sektor berupaya meniti jalan yang lebih lestari.
Teks: Rifqy Faiza Rahman
Foto: Deta Widyananda
Suara-suara mesin tempel perahu menyelak keheningan Sungai Selapan, yang menembus pesisir timur Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan. Hilir mudik kelotok hingga speed boat menyiah gelombang air sungai selebar 200 meter yang bermuara ke Selat Bangka, menepikan riak yang menerjang akar-akar nipah dan mangrove di tepian. Hamparan hutan nipah dan mangrove ini melengkapi ekosistem tumbuhan khas rawa lainnya, membentuk lorong alam dari dermaga Tulung Selapan menuju Sungai Lumpur, Kecamatan Cengal, salah satu desa terakhir di ujung muara. Warga setempat kerap menyebutnya “Kuala Lumpur”, karena ‘kuala’ berarti muara. Tentu saja yang dimaksud bukan Kuala Lumpur di Malaysia.
Tidak hanya Sungai Selapan. Sepanjang hari, pasang surut sungai-sungai besar lainnya menjadi jantung yang menggerakkan kehidupan masyarakat di 10 desa yang menghuni perairan rawa OKI. Desa-desa tersebut tersebar di empat kecamatan, yakni Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal, dan Sungai Menang; membentuk 75% wilayah lahan basah dataran rendah (mangrove, rawa, gambut) dan mendominasi kabupaten yang beribu kota di Kayu Agung tersebut.
Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Selatan pada 2017, seperti dikutip dalam kajian Ulqodry dkk (2022), kawasan pesisir OKI merupakan daerah dengan garis pantai terpanjang di provinsi ini, sekitar 295,14 km yang membentang dari Kecamatan Air Sugihan (berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin) ke Kecamatan Sungai Menang (berbatasan dengan Provinsi Lampung). Kawasan pesisir OKI juga merupakan pesisir paling timur Pulau Sumatra dan berhadapan langsung dengan Pulau Bangka.
Menariknya, meski berada dekat pesisir, mayoritas penduduk justru bermata pencaharian sebagai petambak (38,8%) daripada nelayan perikanan tangkap (28,7%). Sisanya berprofesi sebagai ASN, bidan, peternak, pemberi jasa, buruh tambak, petani, buruh tani, pekerja kelapa sawit, dan karet dengan persentase di bawah 35%. Ini tercermin dalam citra satelit wilayah empat kecamatan tersebut. Petak-petak tambak bertebaran, bagaikan labirin-labirin yang berdempetan dengan garis-garis tanah yang menyekat antara satu lahan dengan lahan tambak lainnya.
Keberadaan tambak-tambak tersebut merupakan salah satu pembentuk sejarah perubahan fungsi lahan di pesisir timur OKI sejak lebih dari tiga dekade. Pada tahun 1990, sebelum banyak berubah menjadi tambak, bentang alam pesisir timur OKI dipenuhi ekosistem hutan mangrove seluas 48.332,20 hektare (ha), terbesar kedua di Sumatra Selatan setelah Kabupaten Banyuasin (157.071,37 ha).
Angka itu menyusut cukup drastis, seiring bertambahnya luasan lahan tambak udang windu dan bandeng hingga saat ini. Dalam analisis citra satelit PlanetScope oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) melalui kajian Hidayat dkk (2024), luas lahan tambak di empat kecamatan pesisir OKI mencapai 39.649 ha, nyaris mendekati luas mangrove terkini sebesar 40.020 ha. Akan tetapi, Hidayat dkk menambahkan, tambak bukan satu-satunya faktor tunggal penyusutan ekosistem mangrove. Aktivitas industri dengan Hak Pengusahaan hutan (HPH) dan pembalakan liar pada periode 1980–1990, ditambah kebakaran hutan dan lahan berskala besar semasa Reformasi dan terulang tahun 2015, juga turut andil.
Mengingat pentingnya peran ekosistem mangrove bagi kehidupan pesisir Sumatra Selatan, khususnya OKI, sejak 2021 YKAN mengimplementasikan program Mangrove Ecosystem Restoration Alliance (MERA). Program serupa juga berlangsung di Berau (Kalimantan Timur) dan Bengkalis (Riau). MERA merupakan aliansi bersama pemerintah daerah, sejumlah perusahaan hingga lembaga internasional untuk berkolaborasi merestorasi mangrove di sejumlah kawasan pesisir yang terdegradasi. Peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat juga jadi perhatian.

Wanamina: titik temu ekonomi dan konservasi
Pada sepertiga awal periode 1990-an, budi daya tambak tradisional di kawasan pesisir OKI mengalami masa-masa jaya. Di masa-masa ini, YKAN mencatat luas lahan tambak baru 17 ha, sebelum akhirnya meningkat dua ribuan kali lipat dalam tiga dekade. Komoditas yang paling banyak digunakan mulanya udang windu, lalu bandeng menyusul setelah mendapat pengaruh dari petambak asal Lampung sejak tahun 2006. Sebagai salah satu kawasan terluar dan terpencil di Indonesia, ketika tidak ada jalan raya, akses air bersih, listrik negara, hingga layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai, maka sumber penghidupan sebagian besar masyarakat pesisir OKI bergantung pada budi daya tambak.
Pembukaan lahan tambak di pesisir OKI menempati atau mengambil alih ruang-ruang ekosistem mangrove dengan ragam zonasi kawasan. Mengacu pada data Peta Mangrove Nasional Tahun 2021 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ekosistem mangrove di OKI termasuk dalam empat kriteria fungsi kawasan: a) Hutan Konservasi (hutan lindung) seluas 26.632,80 ha (69%); b) Areal Penggunaan Lain seluas 7.035,26 ha (18%); c) Hutan Produksi seluas 4.968,21 ha (13%); dan d) Laut-air seluas 21,58 ha (kurang dari 1%). Tutupan hutan mangrove di OKI mencapai 23% dari total luas ekosistem mangrove Sumatra Selatan. Sebagai informasi, luasan hutan mangrove Sumatra Selatan menempati posisi kedelapan di tingkat nasional, setelah Papua Selatan, Papua Barat, Papua Tengah, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Maluku.
H. Jamaluddin (50) atau Haji Juma, warga Desa Sungai Lumpur, termasuk dalam generasi pertama yang membuka tambak di pesisir OKI. Hasil tambak yang menggiurkan pun menggoda sebagian masyarakat mengikuti jejaknya sebagai petambak. Namun, terlalu banyaknya petambak, kurang tepatnya pengelolaan lahan tambak, abrasi dan intrusi air laut, hingga perubahan iklim menguak sisi lain, yakni betapa terbatasnya kapasitas alam untuk dieksploitasi.


Haji Juma, pemilik lahan tambak yang dijadikan demplot percontohan wanamina bersama YKAN (foto kiri). Haji Juma mengecek tambak miliknya di Sungai Lumpur yang dikhususkan sebagai lahan pembibitan udang dan bandeng/Deta Widyananda
Seperti halnya sifat khas perairan rawa dataran rendah, keberadaan tambak pun juga mengalami pasang surut. Dari yang dulunya tiga bulan sekali bisa panen, kini semakin panjang setidaknya enam bulan sekali baru bisa mendapat hasil. Itu pun tidak menentu, sekalipun musim kemarau dianggap sebagai masa siklus budi daya paling optimal. Laiknya hukum kurva law of diminishing return dalam ilmu ekonomi, perolehan hasil tambak—baik dari kuantitas produksi dan pendapatan—pun ikut mengalami penurunan hingga 30–50%. Sebab, skala produksi sudah mencapai titik puncak pada periode Reformasi lalu.
Oleh karena itu, melalui MERA, YKAN menghadirkan jalan tengah bernama SECURE (Shrimp-Carbon Aquaculture). SECURE merupakan upaya restorasi mangrove dengan pengelolaan budi daya tambak udang tradisional ramah lingkungan. Salah satunya menggunakan metode silvofishery atau wanamina, sebuah sistem budi daya perikanan terpadu dengan memperhatikan kearifan lokal dan pelestarian mangrove. Prinsip dari wanamina adalah mengalokasikan sebagian tambak untuk menjadi lahan penanaman mangrove. Meskipun luas lahan mengecil, pendekatan ini diharapkan tetap mampu meningkatkan produktivitas tambak udang hingga 30%. Di sisi lain, diharapkan pula kelak hutan mangrove bisa beregenerasi secara alami.
Tomi Prasetyo Wibowo, MERA Site Manager, mengungkap bahwa YKAN hendak mengubah paradigma tentang program pelestarian mangrove. Selama ini, yang umum terjadi, upaya penyelamatan mangrove hanya sekadar menanam tanpa adanya keberlanjutan. Bahkan spesies mangrove yang ditanam kerap kurang sesuai peruntukan dan kondisi habitatnya, sehingga angan-angan kelestarian pun layu sebelum berkembang.
Padahal, banyak hal yang perlu dikaji sebelum mengeksekusi sebuah program rehabilitasi mangrove. Mulai dari aspek sosial, ekonomi, budaya, hingga ekologi. “Itu semua butuh data dan kajian yang selanjutnya dikembangkan menjadi desain (restorasi),” tegas Tomi. Tak terkecuali status hukum suatu kawasan yang ingin dipulihkan peruntukannya, dengan tetap memperhatikan multiaspek tersebut. Sebab, tak sedikit area tambak yang ada di sejumlah tempat berada di kawasan hutan lindung.
Di pesisir OKI, YKAN berkegiatan di tiga desa, yaitu Desa Sungai Lumpur1, Desa Simpang Tiga Abadi, dan Desa Simpang Tiga Jaya. Adapun dari tiga desa tersebut, salah satu titik demplot percontohan untuk penerapan wanamina adalah tambak milik Haji Juma di area Parit 1, Desa Simpang Tiga Abadi. Sekitar dua kilometer dari rumahnya di Sungai Lumpur, atau kurang lebih 100 kilometer dengan speed boat dari Dermaga Tulung Selapan, tempat daratan terakhir menuju ujung muara. Tambak seluas empat hektare ini berada di tepian kanal pasang surut yang dikelilingi ekosistem mangrove serta nipah. Tampak di tengah-tengah tambak, terdapat sejumlah instalasi mangrove yang ditanam dengan jarak beraturan menggunakan media tanam berupa bilah-bilah bambu.
Penetapan lokasi rehabilitasi dan demplot tersebut juga didasarkan pada rekomendasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Musi dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan selaku pemangku kawasan. Menurut Tomi, kolaborasi lintas stakeholder tersebut bergerak dalam kerangka rehabilitasi hutan dan lahan, seperti diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
Dalam perkembangannya, sejak mulai diterapkan pada 2023, metode wanamina di lahan demplot milik Haji Juma telah berlangsung sebanyak dua siklus budi daya. Pada siklus pertama, hasil panen mengalami sedikit penurunan dari periode sebelumnya. Berdasarkan keterangan Achmad Soleh (48), petambak mitra dari Desa Simpang Tiga Abadi yang ikut mengurus tambak demplot, hasil panen udang baru mencapai satu kuintal, sedangkan bandeng 800 kilogram (size ⅔) dan 400 kilogram (size ⅚). Lalu di siklus kedua menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, panen udang naik menjadi sebanyak empat kali lipat. Rata-rata harga jual udang adalah Rp80.000 per kilogram (isi standar 30 ekor) dan bandeng Rp10.000 per kilogram (isi standar 2–3 ekor). Harga jual bisa lebih rendah atau lebih tinggi tergantung pada bobot dan ukuran hasil panen.
Melihat perbedaan hasil tersebut, Haji Juma menganggapnya sebagai proses adaptasi, sehingga tambak membutuhkan waktu untuk “terbiasa” dengan metode baru. Menurut Tomi, masih perlu beberapa siklus lagi di sejumlah lahan demplot untuk membuktikan konsistensi hasil yang diharapkan, sebelum akhirnya bisa diterapkan sepenuhnya di lahan-lahan tambak yang lain.
Achmad mengaku, program SECURE dengan metode wanamina membuka lebar pemikirannya soal budi daya tambak tradisional. Termasuk memilih spesies mangrove yang tepat (sesuai habitat) untuk ditanam di area tambak. “[Ternyata] begini cara berbudidaya yang benar dan ramah lingkungan. [Bisa] menjaga dua-duanya (tambak dan mangrove). Kita tetap berbudidaya, tapi kita juga jaga lingkungan (mangrove) kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Achmad berharap ada perubahan positif dari metode wanamina di lahan demplot milik Haji Juma. Meskipun, ia mengakui tetap butuh proses secara bertahap karena cuaca yang tidak bisa diprediksi. “Mudah-mudahan memang kita ada lebih hasilnya itu lebih meningkat. Harapan saya, [metode wanamina] bisa dicontoh kawan-kawan di sini, yang tadinya [budi daya] asal-asalan. [Kalau] ada contoh ini kan bisa ditularkan ilmunya,” pungkas perantau berdarah Trenggalek, Jawa Timur itu.

“Kami ingin mencontohkan tambak-tambak di sini…”
“Sebenarnya saya juga merasa bersalah karena dulu banyak membabat mangrove untuk tambak,” celetuk Haji Juma tiba-tiba pada satu malam yang santai di rumah, sembari mengisap sebatang rokok diselingi kopi hitam panas yang diseduh istrinya. Di rumah, setelah seharian bekerja di tambak, ia biasanya mengenakan kaus oblong dan peci putih, serta sarung.
Suami Siti Aminah itu mengenang masa-masa puluhan tahun silam, sekitar tahun 1991, tatkala merintis usaha budi daya tambak alam bersama mendiang ayahnya di sekitar Sungai Lumpur dan Simpang Tiga Abadi. Mereka membuka sepetak lahan seluas empat hektare, yang kini jadi lahan demplot percontohan SECURE dengan metode wanamina (silvofishery). Ayahnya melihat ada potensi ekonomi dari tambak karena adanya temuan indikator berupa udang, kepiting, dan ikan berlimpah. “Jika berhasil, syukur. [Tapi] jika gagal, [kami akan] pulang ke Sulawesi,” kenangnya.
Pekerjaan tambak memang sempat memberikan gelimang kejayaan. Satu di antara yang dianggap berhasil adalah Haji Juma dan ayahnya. Keuletan yang mengalir di darah orang Bugis seakan mengular kepada kesuksesan. Puncak-puncak kejayaan tambak terjadi pada periode 1993–1998. Di era itu, hanya dengan modal 10 juta rupiah, sekali panen bisa mendapatkan pendapatan 100 juta rupiah setelah tiga bulan budi daya. Pencapaian Haji Juma merecik petambak-petambak baru bermunculan dan membuat lahan-lahan tambak semakin meluas.
Meski teknik budi daya masih tradisional, tetapi pembukaan lahan tambak telah mengambil alih ekosistem hutan mangrove alami yang dulu dominan. Kehidupan di rawa serba terbatas dan teramat keras, seakan takdir tidak menyediakan pilihan jalan hidup yang lebih baik, yang menuntut Haji Juma dan masyarakat pesisir OKI bertahan hidup. Betapa pun caranya. Tak terkecuali menggantungkan nasib pada pohon-pohon mangrove untuk ditebas, dimanfaatkan kayu-kayunya, dan dirambah untuk membuka ruang terbuka bagi tambak-tambak baru.
Seiring merosotnya produktivitas tambak dalam satu dekade terakhir, tampaknya alam pun mengirimkan alarm darurat. Haji Juma sadar akan sesuatu. Betapa kehilangan hutan mangrove justru berdampak sangat nyata pada lahan penghidupannya. “Abrasi makin parah, air laut makin naik ke daratan,” ungkap Haji Juma. Katanya, kerja di tambak sudah tidak teduh lagi karena tidak ada hutan mangrove.
Maka tatkala program-program awal restorasi mangrove mulai hadir lewat sejumlah LSM sejak 2017, termasuk melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh pemerintah semasa pandemi COVID-19, Haji Juma sangat antusias. Ia bersama sebagian besar masyarakat Sungai Lumpur dan Simpang Tiga Abadi mulai giat untuk menanam mangrove kembali di area tambak. Program SECURE dengan metode wanamina oleh YKAN dengan aliansi MERA turut melengkapi proses rehabilitasi hutan dan lahan mangrove di area tambak tersebut.
“Saat YKAN minta [lahan] demplot untuk tambak, kami sangat mendukung,” ujar Haji Juma. Ia mengaku rela untuk memberikan sepetak tambak seluas empat ha itu sebagai salah satu demplot percontohan metode wanamina. “Kami ingin mencontohkan tambak-tambak di sini, [agar] bisa berkembang lagi seperti sebelum-sebelumnya.”
Pernyataan Haji Juma tersebut seperti menjadi pesan bagi setiap petambak di pesisir OKI. Ia ingin mengajak untuk mengubah pola pengelolaan tambak menjadi lebih berkelanjutan. Salah satunya aktif menanam mangrove, baik di dalam tambak maupun di daerah penyangga tambak sekitarnya. Baginya, keberadaan mangrove memberi dampak lingkungan yang nyata, mulai dari mencegah abrasi dan intrusi (naiknya air laut ke daratan), hingga memberi nutrisi alami bagi pertumbuhan udang windu dan bandeng yang dibudidayakan.2

Pintu harmoni itu kini terbuka lebar
Di usianya yang sudah mencapai setengah abad, keterbukaan Haji Juma terhadap pendekatan wanamina layak diapresiasi. Ditambah kekompakan petambak mitra lintas generasi yang ikut mengurus lahan demplot tersebut dan merestorasi ekosistem mangrove di sejumlah lahan tambak tak produktif.
Sebab, menurut Tomi, resistensi warga terhadap program tersebut mulanya sempat terlihat. Sangat wajar ketika para petambak sempat enggan menanam mangrove di area tambak, yang dianggap mempersempit area pelataran tambak untuk menumbuhkan pakan alami bandeng. Selain itu, terdapat kekhawatiran juga bahwa keberadaan mangrove dalam tambak membikin air makin kotor, hingga mengundang burung-burung datang mencari mangsa di tambak yang pada akhirnya menurunkan produktivitas tambak.
“Kami sangat bersyukur sekali ketika Haji Juma mau [menerima permintaan demplot]. Meskipun dia melihat sendiri bahwa setelah mangrove ditanam di tambak, itu juga muncul persoalan baru,” terang Tomi.
Namun, pada akhirnya begitulah proses rehabilitasi dengan pendekatan berbasis masyarakat. Untuk mampu mengelola program konservasi dengan jangka waktu panjang—tidak bisa tidak—akan lebih bijaksana ketika melibatkan masyarakat yang sudah lama menghuni kawasan. Perlu diakui bahwa mangrove di pesisir Kabupaten OKI yang rentan merupakan wilayah kelola dengan aksesibilitas yang cukup sulit, telah lama berada di luar jangkauan kelola pemerintah daerah (lost of government control).3
“Yang selalu saya dengar, Haji Juma adalah orang yang mau belajar hal-hal yang baru,” kesan Tomi. Bahkan menurutnya, dengan pengalaman dan perjalanan hidup yang ditempa begitu keras di alam yang begitu liar, sosok-sosok seperti Haji Juma layak diberi gelar profesor. Sudah tidak berkutat dengan teori lagi, tetapi langsung praktik di lapangan yang kenyang dengan segala suka dan duka.
Sebagai Site Manager, Tomi pun tak kalah menaruh asa pada keberlangsungan program SECURE yang dibuat YKAN melalui aliansi MERA. Bicara soal pengelolaan alam berkelanjutan, ia menekankan pentingnya untuk tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekologi dan ekonomi.
“Harapan terbesar saya adalah adanya pengakuan negara [terhadap keberadaan masyarakat dalam kawasan hutan]. Solusinya sudah jelas, [lewat pengajuan] perhutanan sosial,” kata Tomi. Saat ini, negara telah mengakomodasinya lewat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Namun, pria asal Semarang itu menegaskan, penerapan perhutanan sosial (perhutsos) di OKI bukan berarti menjadi pembenaran sebagai alat untuk melegalkan aktivitas ilegal. Perlunya perhutsos agar masyarakat memiliki andil dan peran yang jelas di dalam wilayah kelolanya melalui izin perhutsos. Masyarakat petambak yang berada dalam kawasan hutan tetap menjalankan aktivitas tambaknya, sekaligus berperan sebagai penjaga (ranger) alam (mangrove) di sekitarnya.
Bagi Tomi, sangat penting untuk memiliki paradigma bahwa masyarakat lokal itulah aktor utama program restorasi, yang akan menentukan keberlanjutan dari ekosistem yang ada di sekitarnya. Baginya, akan sulit jika “meminta” alam memulihkan dirinya sendiri tanpa bantuan manusia, karena manusia adalah bagian dari ekosistem itu sendiri dan tidak bisa dikesampingkan. “Siapa lagi yang mau mengawasi 24 jam di sini?” tanya Tomi retoris.
Hasil kajian Hidayat dkk (2024) menguatkan itu. Kegiatan rehabilitasi ekosistem bukan hanya bertujuan untuk memulihkan lahan kritis, melainkan juga diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap kawasan dan masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat setempat menjadi jembatan penghubung supaya program rehabilitasi menjadi kegiatan bersama, sehingga terbangun rasa memiliki agar kelestarian dapat tercapai.
Asa harmoni ekonomi dan ekologi itu masih terbuka lebar. YKAN berharap di masa mendatang ada pengembangan ekonomi berkelanjutan dari kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove. Di antaranya pengembangan produk turunan mangrove dan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Sebab, tujuan besar dari perhutanan sosial adalah masyarakat sejahtera, hutan (dan laut) terjaga.
- Di Desa Sungai Lumpur, YKAN juga memperkenalkan pendidikan lingkungan hidup (PLH) untuk siswa kelas 4-6 SD melalui implementasi proyek Kurikulum Merdeka. ↩︎
- Alasan penting mangrove mesti ada di tambak adalah karena perakaran mangrove dibutuhkan untuk proses remediasi tanah tambak tua. Mangrove akan menjadi habitat tidak hanya bagi udang windu, tetapi juga bagi biota macrobenthos lainnya—organisme kecil yang hidup di kolom air dan berperan dalam dekomposisi serasah tanaman mangrove. Keragaman biota yang bernaung di mangrove akan jadi pengendali hama utama trisipan (Certhidea sp.) agar tidak terlalu dominan. Hama utama dimaksud merupakan fenomena yang umum terjadi di tambak tradisional di OKI. Moluskisida yang biasa dipakai petambak tidak menjadi solusi. ↩︎
- Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah Sumatera Selatan, 2024, hlm. 1. ↩︎
Referensi:
Hidayat, T., Prakoso, D., Bayyan, M. M., Fahmi, dan S., Fajariyanto. 2024. Desain Rehabilitasi Mangrove Sumatera Selatan. Diterbitkan di Palembang oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Musi.
Ulqodry, T. Z., Fauziyah, Rozirwan, Agustriani, F., dan Sarno. 2022. Laporan Akhir: Kajian Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat di Pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Yayasan Konservasi Alam Nusantara.
Foto sampul: Area tambak udang dan bandeng di tengah hamparan hutan mangrove yang berdekatan dengan permukiman Desa Sungai Lumpur, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan (Deta Widyananda).
Publikasi artikel ini merupakan kerja sama TelusuRI bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara.
Kenali Indonesiamu lebih dekat melalui Instagram dan Facebook Fanpage kami.
Tertarik buat berbagi cerita? Ayo kirim tulisanmu.
Jika tidak dituliskan, bahkan cerita-cerita perjalanan paling dramatis sekali pun akhirnya akan hilang ditelan zaman.